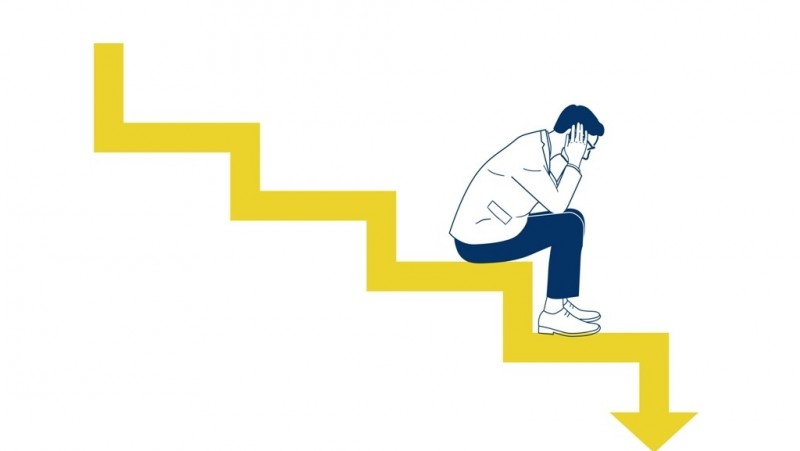
Jika semua layanan diserahkan kepada robot, maka saatnya kita menyiapkan diri tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan unsur dasarnya, yaitu spiritual (makhluk rohani).
Thobib Al Asyhar
Kolomnis
Belakangan ramai dibincang soal jabatan eselon III, IV dan V di pemerintahan akan dihapus. Tidak sampai di sini, muncul ungkapan presiden Jokowi dua kali yang memerintahkan Kemenpan RB, Cahyo Kumolo, agar eselon III dan IV digantikan dengan Artificial Intelligent (kecerdasan buatan). Artinya, beberapa sektor tugas dan fungsi pelayanan publik akan ditempati sosok "smart robot" (si robot yang cerdas).
Apa alasan Jokowi mengambil kebijakan ini? Seperti yang pernah disampaikan, Jokowi ingin Indonesia memiliki birokrasi yang slim nan lincah. Tidak bertele-tele seperti ikan lele, tidak berbelit-belit seperti orang tidak punya duit, tapi cepat seperti ikan sepat. Birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang sangat amat disruptif. Karenanya, fenomena itu menuntut penghuni bumi dan kantor-kantor pemerintah harus mengikuti ritme mekanik.
Sudah tidak zamannya lagi mengadakan Rapat Koordinasi mengumpulkan pejabat Pusat dan daerah di hotel mewah dengan biaya mahal. Sudah tidak relevan lagi monitoring dan evaluasi program dengan cara "berkunjung" di sana dan di sono, sambil selfie-selfie. Apalagi datang rombongan pula. Semua itu bisa dilakukan dengan smart technology. Canggih, cepat, murah, dan bervisi masa depan.
Menteri millenial, Nadiem Makarim, pernah menyampaikan pidatonya yang futuristik. Indonesia, katanya, tidak akan bisa menyamai negara-negara lain jika masih mempertahankan kondisi saat ini. Birokrasi yang gemuk dan lemot. Perlu lompatan-lompatan besar. Menurutnya, diperlukan revolusi kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang serba praktis dan simpel.
Nadiem menekankan bahwa output lompatan-lompatan itu bukan pada penggunaan teknologi itu sendiri sebagai "media", tetapi bagaimana membentuk manusia (generasi) yang memiliki paradigma dan budaya teknologi. Kenapa? Karena teknologi adalah buatan manusia yang bisa saja membelenggunya, tetapi manusia-manusia yang memiliki sikap dan cara pandang teknologi yang cepat, adaptif, responsif, dan "apa adanya".
Lalu bagaimana sikap kita? Apakah perlu khawatir akan terjadi kegoncangan birokrasi? Jawabnya gampang dan sederhana. Meminjam istilah Gus Baha, "ora usah piye-piye, yo biasa-biasa wae" (tidak perlu gimana-gimana, ya biasa-biasa saja). Artinya, perubahan merupakan kemestian pada setiap periode kehidupan. Yang diperlukan adalah kesiapan menghadapi itu semua.
Apakah kita siapa? Harus! Ingat apa yang sering diulang-ulang oleh para motivator, bahwa orang hebat itu bukan karena dia pintar, tapi karena dia mampu beradaptasi dengan perubahan. Lalu apa dampak perubahan dan kehidupan mekanistik yang akan kita hadapi?
Dehumanisasi Birokrasi
Diskursus tentang dampak teknologi dan sains bagi manusia sudah dimulai sejak abad-abad awal revolusi industri di Inggris, yaitu akhir abad 18. Ditemukannya mesin-mesin industri telah membuat banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Satu efek negatif paling nyata dari kemajuan teknologi dan sains adalah terjadinya kerusakan alam secara massif.
Mari kita cek usia alam ini. Konon, alam ini sudah berusia jutaan, atau bahkan milyaran tahun lalu. Bumi pun telah mengalami berbagai perubahan dari kondisi bagus, rusak, bagus lagi, rusak lagi, dan seterusnya. Namun, sejak manusia menemukan teknologi dalam semua lini kehidupan, kerusakan alam ini makin menjadi-jadi.
Jika revolusi industri terjadi pada akhir abad 18 dan sekarang berada di abad 20, artinya hanya sekitar 1.5 abad alam ini sudah mengalami kerusakan yang dahsyat. Berapa banyak manusia mati sia-sia akibat peperangan, polusi udara, pencemaran lingkungan, terkena dampak banjir, depresi, munculnya berbagai wabah penyakit akibat gaya hidup, fenomena bunuh diri, dan lain-lain. Entah berapa banyak lagi kehancuran alam ini dengan keserakahan manusia melalui kecanggihan teknologi.
Albert Einstein saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa California Institute of Technology begini: "Dalam peperangan, ilmu menyebabkan kita saling meracun dan saling menjegal. Dalam perdamaian, dia membikin hidup kita dikejar waktu dan penuh tak tentu. Mengapa ilmu yang amat indah ini, yang menghemat kerja dan membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit sekali kepada kita?" Pertanyaannya, apakah lalu di akhir hayatnya Einstein yang notabene "nabi" sains bisa hidup bahagia? Entahlah.
Apa yang disampaikan Einstein adalah keprihatinan, dimana sains dan teknologi banyak yang menjadikan manusia semakin kurang bahagia. Hal sama pernah dinyatakan oleh cendekiawan muslim Cak Nur (Nurcholis Madjid), bahwa teknologi modern --sebagai anak kandung ilmu pengetahuan-- dan pilihan-pilihannya mengandung masalah yang tidak boleh dipandang enteng. Menurutnya, dampak nyata dari kemajuan teknologi adalah "dehumanisasi", yaitu menipisnya tata nilai kemanusiaan dalam setiap etape kehidupan ini.
Menurut Amalialaisa (Dictio), dehumanisasi merupakan hilangnya atau menurunnya harkat manusia. Dehumanisasi bisa dalam bentuk sikap atau tindakan menyangkal nilai-nilai luhur manusia lainnya. Korban dehumanisasi akan kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan(estetik) dan kesucian. Mereka hanya peka dan menghargai nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan "pleasure principles" (prinsip-prinsip kesenangan), yaitu terkait materi (pemilikan kekayaan), hedonisme (kenikmatan jasmani) dan gengsi (prestise).
Dehumanisasi terjadi tatkala nilai-nilai luhur yang ada dalam teks ideologi, budaya, dan agama tidak lagi berfungsi efektif sebagai pegangan hidup manusia sehari-hari. Kebudayaan, termasuk di dalamnya agama, kehilangan dukungan kolektif. Manusia cenderung hidup tanpa basis keluhuran kebudayaan dan nilai-nilai mulia.
Globalisasi dengan seperangkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kepada terjadinya proses dehumanisasi, yakni manusia menganggap manusia lain tidak setara dengannya. Pada saat manusia menganggap manusia lain sebagai sesuatu yang derajatnya di bawah manusia, maks rasa empati tidak muncul ketika dia mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun kesakitan.
Fakta ini sudah kita lihat sehari-hari di lingkungan kehidupan kita. Tingkah pola para netizen makin menjadi-jadi. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan sesama gegara teknologi. Dengan smartphone atau gadget telah nyata-nyata membuat manusia-manusia telah kehilangan rasa hormat dan empati kepada ulama, tokoh masayarakat, guru, teman, atau sesama. Dengan teknologi pula, manusia lupa akan hakikat kedirian yang memiliki kemuliaan, sehingga dengan mudah menghujat, mencela, membully, bahkan menyebarkan gambar-gambar tidak senonoh kepada orang banyak.
Tidak sampai di situ, dengan kemudahan komunikasi melalui smartphone, banyak orang seperti tidak memiliki kemampuan menjaga sense kepada sesama, karena semua serba otomatis dan praktis. Demikian juga suasana di ruang-ruang tunggu bandara, bis, kereta api, pelabuhan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain, semua sibuk dengan gadget. Sedikit sekali adanya tegur sapa untuk saling kenal, cengkerama tukar cerita, dan lain-lain.
Lalu apa hubungannya dengan birokrasi? Birokrasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam konteks bernegara, birokrasi adalah pilar utama pemerintahan. Pada zaman Orba, birokrasi dijadikan alat untuk kekuasaan, selain Golkar dan ABRI saat itu. Posisinya yang sangat penting ini, jika benar nanti birokrasi akan diubah secara radikal, dimana jabatan eselon III, IV dan V yang jumlahnya sekitar 430 ribu diganti dengan AI (robot), maka akan terjadi proses dehumanisasi yang nyata. Kok bisa?
Setidaknya ada tiga fakta dehumanisasi saat birokrasi digantikan fungsinya oleh AI, yaitu: pertama, berkurangnya respek pemerintah kepada masyarakat karena sistem pelayanan bersifat mekanistik. Masyarakat berhadapan dengan mesin, bukan manusia yang memiliki sense dan empati. Seorang pejabat eselon III, IV atau V dalam peta birokrasi kita adalah tulang punggung pelayanan publik. Ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah tiga level jabatan tersebut.
Mari kita lihat. Seorang pejabat eselon III memiliki kewenangan untuk menentukan arah kegiatan dan program secara riil dalam setiap level Satuan Kerja, termasuk layanan publik. Meski eselon I dan II jauh memiliki otoritas kebijakan, tetapi jika tidak dieksekusi oleh pejabat di bawahnya, program tidak akan jalan. Pihak yang membuat rencana, yang melaksanakan, sekaligus yang mempertanggung jawabkan adalah mereka yang ada di bawah eselon I dan II. Contoh paling sederhana, siapa yang memanej staf, siapa yang menghadapi auditor, dan lain-lain.
Praktis, kontrol pelayanan publik ada di level ini. Bagaimana pelayanan menjadi lebih manusiawi dalam menghadapi ragam orang dengan penuh senyum, sapa, dan salam. Saat semua pelayanan berbasis teknologi, dimana masyarakat dilayani oleh AI atau benda mati berupa mesin robot, maka yang harus bertanggung jawab adalah sistem yang dibuat oleh ahli IT di bawah kendali langsung eselon I dan II.
Kedua, manusia-manusia birokrasi (birokrat) akan cenderung berfikir mekanistik dimana membangun hubungan kemanusiaan akan dilakukan jika dianggap perlu. Kerja-kerja "ikhlas" seperti tagline Kementerian Agama hanya menjadi slogan karena semua pekerjaan dikuantifikasi dengan angka, dan ukuran-ukuran material. Karena masyarakat berhadapan dengan robot, maka perilaku pegawainya pun bisa jadi seperti robot.
Mungkin suatu saat akan muncul perkataan seperti ini: "buat apa saya sering-sering menyapa anak buah, menghadap atasan, dan bercengkerma dengan rekan kerja, toh semua bisa dilakukan dengan teknologi smartphone". Yang lebih parah lagi buat para penyuluh agama atau guru, "buat apa saya cape-cape membina umat beragama atau anak didik dengan terjun ke lapangan (mengajar), kan saya sudah membagikan link ceramah/konseling melalui channel Youtube, IG, atau livestraming di WAG", dan lain-lain.
Tugas dan fungsi ASN yang tinggal "klik" melalui aplikasi inilah yang harus diantisipasi agar para pegawai tetap memiliki sense, inovasi, dan kreatifitas. Nanti, pegawai yang paling banyak dibutuhkan adalah mereka yang mampu dan memiliki keterampilan di bidang teknologi, bukan mereka yang ahli manajemen, ahli bahasa, apalagi ahli agama.
Ketiga, keringnya lapis spiritual dalam pelayanan publik. Pelayanan publik hakikatnya terkait dengan kehadiran hati sebagai bagian dari implementasi ajaran Tuhan. Bukankah Tuhan sering bilang agar kita selalu melayani orang lain? Saat semua serba pratis, serba teknologi dengan kemampuan artificial (buatan), maka kehadiran sense akan sangat minim, bahkan hilang.
Penulis pernah berkunjung ke Jepang dan menyaksikan di sebuah Mall di wilayah Odaiba, ada robot "cantik" sebagai petugas front office. Para pengunjung yang ingin bertanya tentang lokasi atau info-info seputar mall dan destinasi di Jepang tinggal menulis kata pertanyaan di komputer dan "si catik" itu akan menjawab dengan mulutnya yang bawel secara lengkap. Lalu apa yang dirasakan pengunjung? Mendapat jawaban sih iya, tapi sama sekali tidak mendapat sentuhan rasa kemanusiaan.
So, apa yang penulis alami benar-benar akan dialami oleh manusia-manusia modern yang sangat mekanistik. Tidak heran manusia di era disrupsi ini akan mengalami banyak gangguan jiwa karena kosong, kurang atau bahkan tidak mendapat siraman spiritual yang cukup. Saat banyak orang Jepang, Korea, Amerika, Eropa dan banyak lagi negara modern melakukan bunuh diri, di situlah manusia telah kehilangan hakikat kediriannya yang disebut "dehumanisasi".
Lalu apakah kita akan meninggalkan dan tidak mau menggunakan teknologi seperti zaman batu? Jawabnya tentu tidak. Hanya saja, jika semua layanan diserahkan kepada robot yang memiliki AI, maka saatnya kita menyiapkan diri tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan unsur dasarnya, yaitu spiritual (makhluk rohani) dan semua itu kembali kepada masing-masing. Wallahu a'lam bish-shawab.
Thobib Al-Asyhar, Penulis buku, Alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Pengajar pada SKSG Universitas Indonesia.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua





















