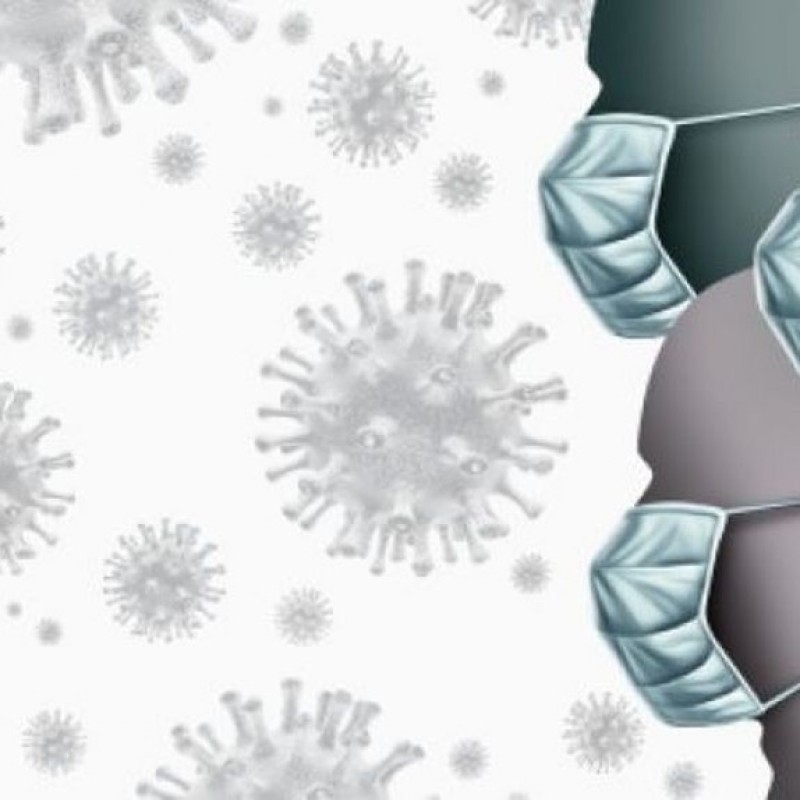Penjelasan soal Larangan Shalat Jumat dan Berjamaah saat Wabah Covid-19
NU Online · Rabu, 25 Maret 2020 | 08:30 WIB
Ahmad Naufa
Kontributor
Jumlah kasus terinfeksi virus Corona atau Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan tren kenaikan. Sebagian sembuh, sebagian lagi menjalani perawatan, dan sebagian lain meninggal dunia. Bahkan, sangat mungkin sebagian orang yang terinfeksi belum masuk data laporan Kementerian Kesehatan RI karena sejumlah keterbatasan.
Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) pada 19 Maret 2020 berdiskusi dan menerbitkan keputusan seputar hukum penyelenggaraan shalat Jumat dalam situasi wabah seperti ini. Ketetapan disusun berdasarkan sejumlah dalil dan pertimbangan maslahat dan mudarat yang matang. (Baca: LBM PBNU Keluarkan Larangan Shalat Jumat bagi Masyarakat Muslim di Zona Merah Covid-19).
Meski demikian, rupanya sebagian orang ada yang masih salah dalam memahami keputusan tersebut. Berikut ini penjelasan KH Afifuddin Muhajir, Rais Syuriyah PBNU yang juga salah satu perumus keputusan LBM PBNU tentang aturan shalat Jumat di tengah maraknya Covid-19. Penjelasan ini merupakan hasil wawancara tim dari Ma’had Aly Situbondo sebagaimana tayang di saluran Youtube.
Mengapa yang ditutup hanya masjid dan yang diliburkan hanya shalat Jumat dan jamaah sementara pasar, mal, dan lain-lain masih jalan terus?
Fatwa yang berisi pelarangan shalat Jumat dan jamaah sekaligus penutupan masjid itu tidak berlaku umum. Akan tetapi khusus zona-zona merah, zona-zona bahaya, zona-zona rawan. Sedangkan untuk zona-zona yang aman, maka shalat jamaah harus jalan terus. Kenapa sebab? Karena jamaah dan shalat Jumat terutama, harus jalan terus. Karena shalat Jumat ini, kita tahu, adalah fardlu ‘ain (hukumnya) yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat.
Kemudian saya sampaikan bahwa fatwanya para ulama menyangkut pelarangan dan penutupan masjid ini, hanya bermanfaat dan penting untuk mereka yang rajin melaksanakan (shalat) Jumat dan shalat jamaah. Karena ada kemungkinan sebagian dari mereka ada yang tidak tahu, bahwa pada saat-saat tertentu, apa yang wajib seperti (shalat) Jumat menjadi tidak wajib. Bahkan dalam kondisi tertentu, apa yang wajib bisa menjadi haram. Ada kemungkinan.
Sedangkan mereka yang memang malas ke masjid, atau bahkan sama sekali tidak mau ke masjid, untuk mereka tidak perlu fatwa. Karena tanpa fatwa pun mereka sudah tidak (shalat) Jumat. Tanpa fatwa pun mereka sudah tidak melaksanakan shalat jamaah.
Pertanyaannya, kenapa kok hanya masjid saja yang ditutup? Kok hanya shalat Jumat dan jamaah saja yang dilarang? Saya menjawab begini: yang wajib saja itu menjadi haram, apalagi yang tidak wajib seperti (ke) mal. Kalau orang-orang yang bisa sedikit berpikir sudah dapat memahami: dari pelarangan kumpul-kumpul di masjid dalam rangka shalat Jumat dan jamaah dilarang, ya apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
Dan bedanya lagi, shalat jamaah dan Jumat ini kan diperlukan kedisiplinan yang luar biasa. Shaf-nya rapat, dan seterusnya. Sementara aktivitas-aktivitas di luar, meskipun mereka banyak orang, kan bisa menjaga jarak satu sama lain. Untuk menghindarkan penularan bisa kalau di luar. Tapi kalau shalat Jumat dan jamaah sulit. Kecuali kalau shaf-nya dibuat renggang, sebagaimana yang kadang dilakukan orang.
Kalau tempat-tempat maksiat, di situ tidak berlaku istilah penutupan. Kenapa sebab? Karena sejak dari awal, tempat-tempat itu tidak boleh dibuka. Iya, kan?
Ada yang menganggap fatwa ulama (untuk meliburkan shalat Jumat) bertentangan dengan ajaran tawakal. Apa benar?
Islam itu tidak hanya memiliki ajaran tawakal. Akan tetapi Islam juga memiliki ajaran mawas diri dan ajaran waspada, iya kan? Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi yang mengajak kita agar supaya selalu tawakal kepada Allah SWT. Pasrah.
Akan tetapi juga banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi yang memerintahkan kita agar supaya mawas diri dan waspada. Salah satu contohnya, Allah SWT berfirman:
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
Artinya: Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.” (QS at-Taubah: 51).
Katakanlah bahwa tidak ada musibah apa pun yang akan menimpa kita, kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, marilah kaum mukminin bertawakal kepada Allah SWT. Ini kan ajaran tawakal.
Ayat lain mengatakan:
أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ
Artinya: “Di mana saja kamu berada, akan terkejar oleh maut, kematian. Walaupun kamu berada di benteng-benteng yang kokoh dan kuat” (QS an-Nisa:78).
Allah subhanahu wata’ala juga berfirman:
قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا
Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Lari tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian (kamu terhindar dari kematian) kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja’,” (QS al-Ahzab: 16)
Kalau kamu mau lari dari kematian dan pembunuhan, maka larimu tidak bermanfaat bagimu, kalau memang sudah ditakdirkan mati. Ini ajaran takdir namanya.
Akan tetapi juga banyak ayat dan hadits yang memerintahkan kita agar supaya kita ini waspada dan mawas diri. Misalnya firman Allah SWT:
وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS al-Baqarah: 195)
Ayat ini mengandung arti begini: “Janganlah kalian melakukan hal-hal yang menyebabkan kamu celaka”. Sebaliknya: “jangan kamu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kamu celaka”. Ini kan ajaran mawas diri namanya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: firra minal majdzûmi firaraka minal asad. “Hendaklah kamu lari”–maksudnya menghindar–“dari orang yang terjangkit penyakit kusta, sama halnya kamu harus lari dari singa”. Dekat-dekat dengan orang yang mengidap penyakit kusta, sama dengan orang yang dekat dengan singa. Artinya dalam kondisi bahaya. Ini kan harus mawas diri namanya.
Ini artinya bahwa ajaran tawakal dan ajaran waspada harus berjalan seiring. Dalam waktu yang sama kita tawakal, dan dalam waktu yang sama pula kita harus mawas diri dan harus waspada. Artinya tidak ada pertentangan antara ajaran tawakal dan ajaran waspada dan mawas diri. Harus sama-sama dilakukan.
Ada dua hadits yang sekilas terlihat bertentangan: “firra minal majdzûmi firaraka minal asad” dan “laa ‘adwa walaa tiyarata”. Bagaimana menurut kiai?
Memang ada hadits yang secara dhahir bertentangan. Satu hadits mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi itu: “firra minal majdzûmi firaraka minal asad”. Hendaklah kamu menghindar dari orang yang terjangkit penyakit kusta, sebagaimana kamu harus menghindar daripada singa. Hadits yang satu mengatakan: “lâ ‘adwa walâ tiyrata”. Hadits ini mengatakan bahwa yang namanya menular itu tidak ada. Sementara hadits pertama kan mengesankan penularan itu ada. Hadits yang kedua tegas mengatakan lâ ‘adwa, yakni penularan tidak ada. Kan bertentangan, itu. Ini yang dalam ilmu hadits disebut dengan ilmu mukhtalifil hadits. Yang pertama-tama membuat istilah ini dan konsepnya sekalian adalah Imam Syafi’i radliyallahu ‘anh. Yaitu ada dua hadits yang tampaknya bertentangan.
Menghadapi hal yang seperti ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan al-jam’u, melakukan kompromi. Hal yang seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa tak mungkin kita memahami satu hadits, tanpa dikaitkan dengan hadits yang lain. Kita tidak akan memahami hadits “firra minal majdzûmi..,” kalau tanpa dikaitkan dengan hadits “laa ‘adwa…”. Sebaliknya, kita tidak akan memahami apa arti daripada “laa ‘adwa…” kalau tanpa dikaitkan dengan “firra minal majdzûmi..”. Ini artinya bahwa, penularan itu tidak ada dengan tabiatnya sendiri. Tidak ada sesuatu yang menular dengan tabiatnya sendiri. Sebaliknya: penularan itu ada dengan kehendak Allah SWT. Kehendak Allah SWT terkait dengan penularan ini akan terjadi jika dikaitkan dengan salah satu sebab. Salah satu sebab yang menyebabkan penularan adalah “mukhalathathus shahiihi lil mariidli,” yakni berkumpulnya orang sehat dengan orang yang sakit. Berkumpulnya orang sehat dengan orang yang terjangkit penyakit kusta.
Jadi kalau dua hadits ini dimaknai, bahwa pada hakikatnya penularan itu tidak ada, terkecuali kalau dikehendaki oleh Allah SWT, melalui sebab-sebab yang Allah SWT sendiri ciptakan.
Dalam kondisi darurat perang saja masih dianjurkan shalat jamaah, mengapa saat menghadapi virus Corona dilarang?
Shalatul khauf atau shalat dalam suasana perang termasuk di dalamnya adalah shalat jamaah, sesungguhnya melihat tata-caranya itu, merupakan perpaduan antara ajaran tawakal, dilihat dari satu sisi, dan ajaran mawas diri dan waspada, di sisi lain.
Kita tahu bahwa jamaah dalam suasana perang itu tidak sepenuhnya mereka shalat bersama-sama. Karena begini: kalau dikatakan bahwa musuh sedang berada di arah kiblat, maka jamaah yang ada dalam suasana perang itu dibagi menjadi dua shaf. katakanlah shaf pertama dan shaf kedua. Mereka tidak sujud bersama-sama. Ketika shaf yang pertama itu sujud, maka shaf yang kedua tetap berdiri menjaga-jaga musuh. Baru ketika shaf yang pertama itu bangun, maka shaf yang kedua itu baru sujud. Begitu seterusnya.
Pada saat musuh itu tidak berada di arah kiblat, maka jamaah, yang tak lain adalah para tentara, itu dibagi dua kelompok, gantian shalat.
Ini dari satu sisi adalah ajaran tawakal. Dalam suasana perang pun masih dianjurkan untuk shalat jamaah. Tapi di sisi lain di situ ada ajaran mawas diri. Buktinya, ya ada praktik shalat seperti itu: gantian.
Di dalam Al-Qur’an dikatakan: walya’khudzu khidzrahum, hendaklah mereka itu mawas diri dan waspada. Ini kan dalam rangka kehati-hatian dan waspada. Tetapi menghadapi Corona ini kan tak bisa dibagi, karena kita tidak tahu Corona sekarang sedang ada di mana? Tidak bisa dibagi-bagi jamaah itu, seperti jamaah dalam suasana perang, kan? Tak mungkin.
Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali ya dilarang itu. Seandainya kita tahu bahwa yang sedang mengidap Corona itu Si A, barangkali SI A ini dikeluarkan saja dari masjid. Atau Coronanya berada di selatan. Walhasil, ya tak mungkin kita melakukan antisipasi sebagaimana kita melihat musuh yang kasat mata, yaitu manusia itu.
Apa pesan kiai untuk santri, alumni pesantren dan warga Nahdliyin?
Taatilah ulil amri. Ulil amri ini adalah pihak yang memiliki otoritas. Atau ulil amri itu siapa? Kalau dalam soal agama – terutama agama Islam – adalah para ulama, khususnya para fuqaha (ahli fikih). Kalau dalam bidang kesehatan, para ulil amri atau orang yang punya otoritas adalah dokter dan pakar-pakar kesehatan. Para ulama sendiri tidak mungkin berfatwa menyangkut pelarangan tanpa lebih dulu tanya kepada para dokter dan ahli kesehatan. Mereka wajib ditaati. Kalaupun ada sebagian ulama yang berbeda, meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun negara kita sudah mengikuti para ulama yang melarang. Dengan demikian, maka seluruh warga negara terikat dengan keputusan negara itu. Jadi, dengan negara kita ini mengambil pendapat yang melarang, berarti khilaf sudah tidak ada. Jadi, hukmul hakim yarfa’ul khilaf. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, kaum muslimin, yang sekaligus menjadi warga negara yang baik, harus taat kepada ulil amri-nya.
Pentranskrip: Ahmad Naufa Khoirul Faizun.
Editor: Mahbib Khoiron
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen oleh Polisi Dinilai Keliru dan Salah Sasaran
5
Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri
6
Polisi dan Militer Tembakan Gas Air Mata di Sekitar Kampus Unisba dan Unpas, Rakyat Jadi Korban
Terkini
Lihat Semua