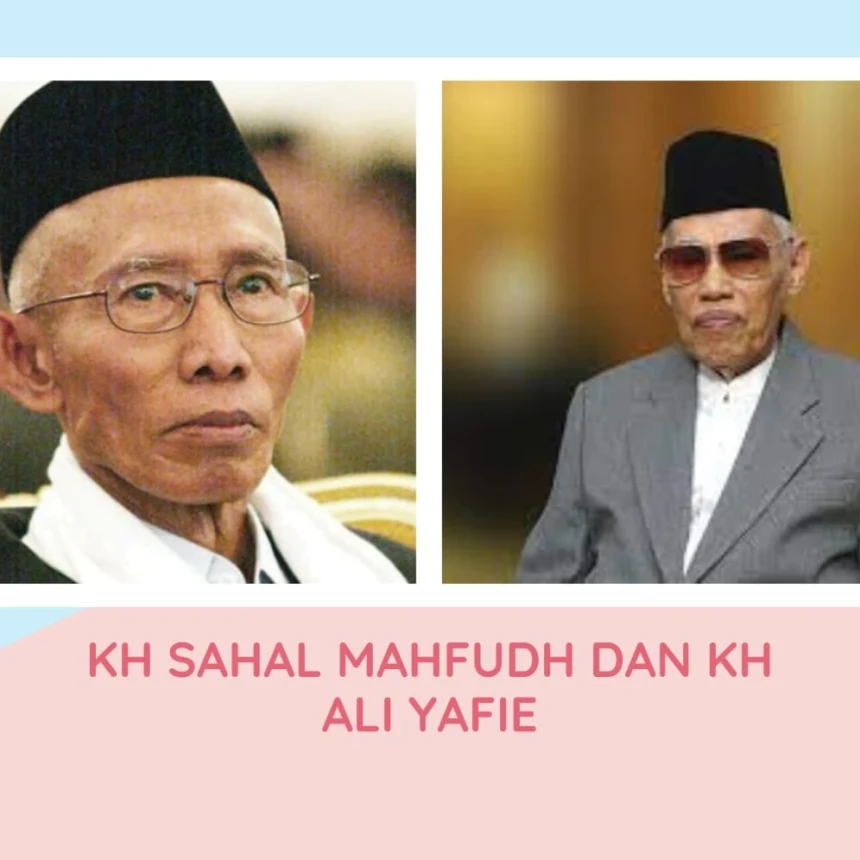Ekoteologi dan Siri' na Pacce: Etika Lokal Atasi Krisis Lingkungan
NU Online · Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:06 WIB
A. Tenri Wuleng
Kolomnis
Di Bulukumba, tanah para pelaut dan panrita lopi (para ahli pembuat perahu pinisi), laut melampaui ruang ekonomi, melainkan juga arena spiritual. Setiap gelombang yang datang, setiap angin yang berembus, adalah bagian dari ritus kosmis yang menghubungkan manusia dengan langit.
Namun kini, sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia ke-80, merdeka dirayakan dengan gelombang pasang yang semakin tak menentu, banjir rob yang merendam pesisir, dan musim tanam yang kian kacau hanyalah sebagian tanda zaman: krisis iklim telah menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan lagi oleh masyarakat, pemangku kebijakan dan negara untuk kembali melihat alam sebagai prioritas, sumber hidup dan jati diri maritim bangsa Indonesia.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa rata-rata suhu udara di Indonesia meningkat 0,8°C dalam empat dekade terakhir (BMKG, 2024). Tahun 2024 bahkan dicatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pengukuran iklim di negeri ini.
Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) tahun yang sama menempatkan Indonesia pada skor ancaman ekologis 2,82, dengan kelangkaan air sebagai risiko utama (IEP, 2024).
Angka-angka ini bukan statistik dingin semata; ia bergema, dirasakan langsung di pesisir Bira yang terus tergerus abrasi, di Kindang yang sawahnya gagal panen, hingga di Kajang di mana air bersih semakin sulit diakses.
Krisis ekologi di Bulukumba dengan demikian tidak bisa hanya dilihat dalam isu lingkungan, melainkan juga krisis eksistensial. Ia meretakkan fondasi kebudayaan, spiritualitas, bahkan martabat manusia yang sejak lama dibangun dalam dialektika dengan alam.
Ekoteologi: Mengembalikan Alam sebagai Subjek
Ekoteologi hadir sebagai jawaban filosofis dan teologis atas krisis ini. Ia berangkat dari kesadaran bahwa relasi Tuhan–manusia–alam bukanlah relasi yang timpang, melainkan koeksistensi yang saling menyokong.
Dalam tradisi Islam, Surah Ar-Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah tangan manusia. Ayat ini tidak hanya menjadi teguran moral, tetapi peringatan ontologis bahwa manusia hanyalah satu simpul dalam jejaring kosmos yang rapuh.
Filosof Hans Jonas (Jonas, 1979) menyebut prinsip ini sebagai The Imperative of Responsibility: kewajiban manusia adalah memastikan bahwa setiap tindakannya tidak mengancam keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Sementara Karen Armstrong (Armstrong, 2019) dalam Sacred Nature mengingatkan bahwa tradisi keagamaan menyimpan reservoir etika ekologis yang dalam, yang bisa menjadi penopang peradaban di tengah krisis planet.
Dalam konteks Bulukumba, ekoteologi menemukan wujud konkret melalui kearifan Ammatoa Kajang. Prinsip “kamase-masea”, hidup sederhana, menjadi inti kosmologi Kajang.
Bagi masyarakat adat ini, hutan atau borong karama’ adalah ruang sakral yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Pelanggaran terhadap hutan bukan sekadar tindak kriminal, tetapi juga pengkhianatan spiritual yang mengguncang keseimbangan kosmos. Dengan demikian, ekoteologi di Bulukumba bukan berakhir dalam wacana akademik, melainkan praksis sehari-hari yang berakar pada tradisi lokal.
Siri’ na Pacce: Etika Keberlanjutan dari Selatan
Bagi masyarakat Bugis-Makassar, siri’ na pacce adalah fondasi moral yang mengikat komunitas. Siri’ berarti harga diri, bukan berhenti dalam dimensi personal, melainkan martabat kolektif yang menubuh dalam tanah, laut, dan hutan. Menghancurkan alam sama dengan melukai siri’ suatu komunitas. Sementara pacce adalah empati yang radikal, yakni kesediaan merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri.
Dalam horizon ekologi, pacce menuntut kita merasakan getir nelayan Bulukumba yang kehilangan ikan akibat laut yang semakin rusak, atau pedihnya petani yang sawahnya gagal panen karena kemarau panjang.
Siri’ na pacce dengan demikian dapat dibaca sebagai bentuk ekoteologi praksis: menolak eksploitasi yang merendahkan martabat manusia dan membangun solidaritas ekologis lintas generasi.
Filosofi ini sejajar dengan gagasan Arne Naess (Arne, 1973) tentang deep ecology, bahwa manusia harus mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup, melampaui nilai instrumental bagi kepentingan manusia.
Data Empirik Krisis Ekologi di Bulukumba
Krisis ekologi di Bulukumba bukan peristiwa abstrak, tetapi fakta empirik yang bisa dilihat dari sejumlah data. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju deforestasi di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari enam ribu hektare per tahun, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan sawit dan tambang nikel (KLHK, 2023).
Bulukumba, meski bukan pusat tambang, turut merasakan tekanan dari alih fungsi hutan, termasuk kawasan sekitar hutan adat Kajang. Hutan adat Ammatoa yang semula membentang sekitar 22 ribu hektare kini mulai terfragmentasi.
Di sektor pesisir, BPS Bulukumba pada 2022 mencatat bahwa 40 persen penduduk pesisir menggantungkan hidup pada laut. Namun, dalam satu dekade terakhir, produksi ikan menurun sekitar 15 persen akibat kombinasi overfishing dan perubahan iklim. Abrasi di kawasan Bira dan Herlang terus menggerus permukiman; setiap tahun sekitar tiga hingga lima meter garis pantai hilang.
Di sektor pertanian, kekeringan yang melanda Kecamatan Kajang dan Kindang pada 2023 menyebabkan sekitar 30 persen sawah gagal panen. Survei Bappeda Bulukumba pada 2024 menunjukkan 27 persen rumah tangga mengalami kesulitan mengakses air bersih di musim kemarau (BPS Bulukumba, 2022).
Semua data ini menunjukkan bahwa krisis ekologi tidak lagi wacana global, tetapi penderitaan langsung yang dirasakan masyarakat lokal.
Filsafat Dari Pappasang hingga Pinisi
Tradisi lisan Bugis-Makassar menyimpan warisan filosofis yang berharga dalam menghadapi krisis ekologi. Pappasang to riolo, petuah leluhur, selalu menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan.
Ungkapan seperti a’bulo sibatang, appa’ tallangeng (bersatu seperti batang bambu agar kuat menahan badai) adalah metafor ekologis yang relevan untuk menegaskan bahwa manusia hanya bisa bertahan jika bersatu menjaga alam.
Perahu pinisi, warisan dunia dari Bulukumba, juga bisa dibaca sebagai metafora ekologis. Pinisi tidak mungkin lahir tanpa harmoni dengan hutan (sumber kayu), laut (ruang uji gelombang), dan angin (energi kosmik).
Ia adalah teknologi yang lahir dari dialog panjang dengan alam sehingga setiap Pinisi sejatinya adalah artefak ekoteologi, bukti bahwa teknologi bisa lahir dari penghormatan terhadap kosmos, bukan dari eksploitasi brutal.
Kritik atas Nasionalisme yang Timpang
Kita harus lebih dalam merefleksikan bahwa nasionalisme sejati adalah merawat tanah dan air, bukan cuma mengibarkan bendera. Ironisnya, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus dengan gegap gempita, tetapi di hari-hari lain membiarkan hutan dibabat, tambang dikeruk, dan laut tercemar.
Pepy Albayqunie (Albayqunie, 2020) menyebut gagasan ini sebagai eco-nationalism, yakni cinta tanah air sejati adalah menjaga tanah dan air. Nasionalisme ekologis menuntut agar perlindungan lingkungan dijadikan pilar kebijakan negara.
Tanpa itu, nasionalisme kita hanyalah ritual kosong, semacam simulakra sebagaimana dikritik Jean Baudrillard, tanda tanpa makna. Kita bernyanyi “Indonesia Raya” di lapangan, namun di saat yang sama menggadaikan ibu pertiwi pada kepentingan kapital global.
Jalan Etis Ekoteologi dan Gerakan Sosial
Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Pertama, di tingkat lokal, penguatan hukum adat Ammatoa harus menjadi benteng terakhir hutan. Ekonomi rakyat bisa dikembangkan melalui penguatan pariwisata berbasis pinisi yang berkelanjutan, pertanian organik, dan koperasi nelayan.
Kedua, di tingkat nasional, negara harus berani menghentikan deforestasi atas nama investasi, melindungi pesisir dari abrasi, serta mendorong transisi energi terbarukan berbasis komunitas.
Ketiga, di tingkat spiritual, rumah-rumah ibadah perlu menjadikan khutbah, misa, dan pangngadereng sebagai ruang pendidikan ekoteologis. Menanam pohon atau membersihkan sungai tidak lagi dipandang semata aksi lingkungan, tetapi bagian dari ibadah.
Paulo Freire (Freire, 1970) menyebut upaya ini sebagai conscientization, yakni membangun kesadaran kritis masyarakat melawan struktur penindasan, termasuk penindasan ekologis. Bulukumba bisa menjadi model laboratorium ekoteologi di mana agama, adat, dan sains bertemu dalam praksis keberlanjutan.
Cintai Bumi, Langit Menyayangi
Bulukumba mengajarkan, menjaga bumi bukanlah dimensi profan saja, melainkan juga spiritual, filosofis, dan politis. Dari kamase-masea Kajang, siri’ na pacce Bugis-Makassar, hingga Pinisi sebagai simbol harmoni kosmos, semua menegaskan bahwa cinta alam adalah cinta kehidupan.
Ketika kita mencintai bumi, langit akan menyayangi kita. Kalimat itu bukan kiasan puitis, melainkan prinsip kosmik. Jika manusia merusak bumi, maka sesungguhnya ia sedang melukai dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika manusia menjaga bumi dengan penuh cinta, ia sedang merawat rumah bersama bagi anak-cucu di masa depan.
A. Tenri Wuleng, kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan; aktivis PB KOPRI PMII, menempuh studi Magister Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua