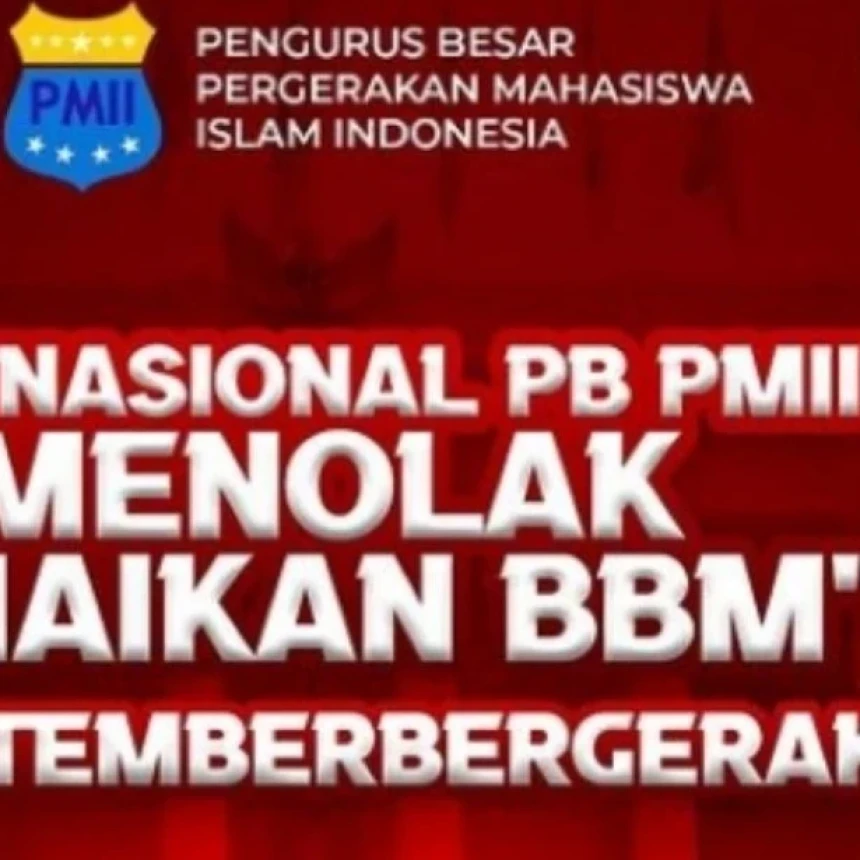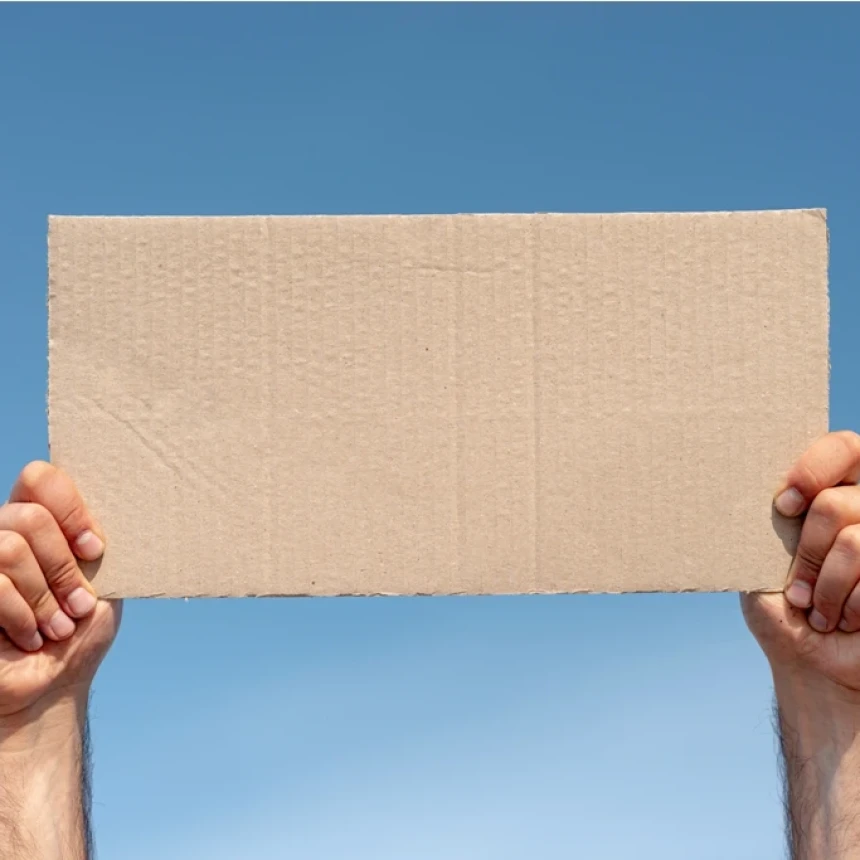Abi S Nugroho
Kolomnis
Panas dan hujan di banyak daerah sepekan terakhir tidak menghalangi mahasiswa turun ke jalan. Dengan kobaran api di beragam kota, peluru karet dan gas air mata. Unjuk rasa mahasiswa, driver gojek dan buruh adalah barometer adanya dinamika demokrasi di tanah air. Ketika mahasiswa dari berbagai BEM (Kampus Negeri dan Swasta) dan organisasi ekstra kampus (PMII, GMNI, HMI Dipo-MPO, GMKI, KAMMI, PMKRI, dll) mendatangi DPR RI pada Rabu, 3 September 2025, publik kembali diingatkan bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji di titik paling elementer. Apakah negara sanggup menghentikan kekerasan, menegakkan hukum, dan membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tidak dirampas oleh oligarki maupun aparat yang bertindak di luar kendali sipil?
Audiensi mahasiswa hari ini patut mendapat apresiasi. Mencermati pemaparan para mahasiswa dari berbagai elemen tersebut, mereka menyerukan banyak hal yang sangat penting dan substansial, sebut saja 17 + 8 yang berkembang di media sosial melalui jaringan masyarakat sipil, namun sekurang-kurangnya penulis mencatat empat agenda yang mereka sebutkan, yakni supremasi sipil, supremasi konstitusi, reformasi fiskal, dan keadilan ekonomi.
Empat hal ini jika dipahami secara mendalam sebenarnya adalah fondasi dari republik modern. Tanpa komitmen nyata pada keempat agenda itu, Indonesia hanya akan mengulang siklus krisis kepercayaan yang sudah pernah menjerumuskan negeri ini pada 1965, 1998, bahkan kini berulang dengan bentuk baru.
Supremasi Sipil Akhiri Bayang-Bayang Dwi-Fungsi
Sejak kelahiran Republik, hubungan sipil-militer selalu penuh ketegangan. Soekarno menyeimbangkan peran tentara dan sipil dalam pusaran Demokrasi Terpimpin. Orde Baru dipimpin Soeharto justru mematri “dwi-fungsi” ABRI sebagai kekuatan sosial-politik sekaligus kekuatan pertahanan-keamanan. Reformasi 1998 menghapuskan kursi militer di parlemen, memisahkan TNI–Polri, dan menegaskan larangan bisnis militer. Itu semua adalah tonggak “supremasi sipil” yang dirumuskan agar demokrasi tumbuh tanpa bayang-bayang laras senjata.
Namun, lebih dari dua dasawarsa berlalu, residu dwi-fungsi tidak pernah benar-benar hilang. Penempatan perwira aktif di jabatan sipil, wacana pelonggaran larangan bisnis militer, hingga tindakan represif aparat saat demonstrasi mahasiswa, semuanya mengindikasikan bahwa garis sipil–militer masih kabur. Di titik inilah, supremasi sipil bukan hanya konsep teoritis Samuel Huntington atau Alfred Stepan, tetapi keharusan praktis mencegah demokrasi kembali disandera.
Dalam konteks kerusuhan belakangan, mahasiswa benar ketika menuntut penghentian kekerasan oleh aparat. Kendali sipil atas aparat keamanan adalah wujud penghormatan pada demokrasi. Supremasi sipil bukan berarti melemahkan militer dan kepolisian, melainkan menempatkan mereka di bawah kontrol politik yang legitimate, transparan, dan akuntabel.
Supremasi Konstitusi Menegaskan Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan
Kalimat klasik yang kerap dikutip para ahli hukum adalah “rule of law, not of men”. Indonesia sudah menegaskan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Namun, supremasi konstitusi sering kali diuji dalam situasi krisis.
Pasca-reformasi, Mahkamah Konstitusi dibentuk guna memastikan undang-undang tidak menyalahi, atau menabrak UUD. Namun, problem utama kita bukan ketiadaan lembaga, melainkan lemahnya komitmen politik untuk tunduk pada konstitusi. Dalam penanganan unjuk rasa, misalnya, tindakan aparat yang berlebihan, kriminalisasi aktivis, atau penundaan akuntabilitas sering bertentangan dengan prinsip HAM yang sudah dijamin UUD 1945 dan ratifikasi ICCPR.
Supremasi konstitusi berarti kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif hanya sah jika sesuai UUD. Di tengah kerusuhan, DPR mestinya tidak cukup jadi pendengar aspirasi, tetapi penegak check and balance. Tugas utama DPR adalah memastikan tindakan eksekutif dan aparat tidak menabrak hak-hak warga negara. Mahasiswa benar menagih peran ini, sebab bila konstitusi tidak menjadi panglima, maka hukum berubah jadi alat kekuasaan.
Reformasi Fiskal Menutup Kebocoran, Menggeser Beban
Jika supremasi sipil dan konstitusi berbicara tentang siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan dibatasi, maka reformasi fiskal menyentuh inti dari untuk siapa kekuasaan digunakan.
Indonesia saat ini menghadapi krisis fiskal yang diam-diam berbahaya. Krisis yang bisa pemerintah gali kuburnya sendiri. Tax ratio stagnan di bawah 10%, jauh tertinggal dari rata-rata negara peers ASEAN. Pemerintah menaikkan PPN jadi 12% pada awal 2025 dengan dalih memperluas basis penerimaan. Namun, PPN pada hakikatnya adalah pajak regresif yang membebani semua orang tanpa membedakan kaya atau miskin. Sementara itu, pajak kekayaan, pajak warisan besar, dan capital gain tax masih minim kontribusi.
Keadilan fiskal seharusnya berarti yang kuat menanggung lebih banyak. Tetapi kenyataannya, kebijakan fiskal kita masih condong pada konsumsi rakyat kecil. Di sisi belanja, subsidi energi memang menjaga stabilitas sosial, tetapi jika tidak dibenahi tepat sasaran, justru lebih banyak dinikmati kelas menengah-atas. Ini jelas ketimpangan.
Dalam situasi kerusuhan, mahasiswa menyinggung isu fiskal bukan tanpa alasan. Ketimpangan beban fiskal adalah salah satu sumber frustrasi publik. Reformasi fiskal harus berani. Percepat RUU Perampasan Aset untuk memutus siklus rente. Realokasi subsidi agar progresif dan ubah orientasi insentif dari jenis padat modal ke sektor padat karya dan hijau. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh timpang, memicu ketidakpuasan yang meledak di jalanan.
Keadilan dan Pemerataan Ekonomi
Demokrasi bukan hanya soal pemilu setiap lima tahun, tetapi juga soal bagaimana roti pembangunan dibagi. Data BPS menunjukkan Gini Ratio Indonesia stagnan di sekitar 0,38. Artinya, hampir dua dasawarsa reformasi fiskal dan pembangunan belum mampu menekan jurang kaya-miskin.
Ketika harga pangan naik, pekerjaan formal stagnan, dan biaya hidup mencekik, rakyat mudah sekali merasa bahwa demokrasi gagal. Dalam titik ini, kerusuhan sosial sering kali meletus sebagai ekspresi “politik perut”.
Mahasiswa menuntut keadilan ekonomi, dan ini adalah isu paling substansial. Pemerintah harus menjamin distribusi manfaat pembangunan melalui pekerjaan bermutu, jaminan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang inklusif. Tanpa pemerataan, demokrasi hanya jadi pesta para elit.
Perlu dipertimbangkan serius, legitimasi negara bisa perlahan rapuh karena aparat kerap memilih jalan represif, sementara aspirasi rakyat justru dianggap ancaman. Agar krisis ini tidak berulang, langkah penyelamatan harus segera dirumuskan. Bukan hanya respons jangka pendek, melainkan agenda minimal yang menyentuh akar persoalan, yakni penghentian kekerasan, penguatan kendali sipil, penegakan konstitusi, pemberantasan korupsi melalui perampasan aset, serta reformasi fiskal demi pemerataan.
Langkah pertama adalah menghentikan kekerasan yang telah merenggut korban jiwa. Aparat mesti diberi perintah politik yang jelas. Kedepankan de-eskalasi, bukan represi. Kekerasan hanya memperpanjang lingkaran dendam dan menutup ruang dialog. Investigasi korban, baik sipil maupun aparat, harus dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada publik. Tanpa kejujuran dan keterbukaan, negara akan terus dicurigai melindungi kekerasan, bukan warganya.
Kedua, supremasi sipil harus ditegakkan dengan memperkuat kendali sipil atas aparat keamanan. DPR sebagai representasi rakyat wajib menjalankan fungsi pengawasan secara penuh. Praktik residu dwi-fungsi yang masih membayangi, penempatan perwira aktif di jabatan sipil atau bisnis militer yang terselubung harus dihentikan. Tanpa itu, garis batas antara keamanan dan politik akan kabur, dan demokrasi kehilangan makna substantifnya.
Ketiga, supremasi konstitusi harus dijadikan kompas utama. Semua tindakan pemerintah, dari kebijakan penanganan unjuk rasa hingga kriminalisasi aktivis harus diuji di bawah kerangka UUD 1945 dan prinsip hak asasi manusia. Negara hukum hanya hidup jika hukum berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali. Bila aparat atau pejabat merasa kebal hukum, maka konstitusi tidak lagi berdaulat, melainkan digantikan oleh logika kekuasaan.
Keempat, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk membuktikan komitmen serius terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan putusan Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2023 untuk mendorong legislatif membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset. Rakyat sudah terlalu lama muak melihat kasus korupsi yang berulang, sementara aset hasil kejahatan tidak bisa dirampas optimal. Dengan RUU ini, negara dapat menutup keran rente sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Keterlambatan dalam mengesahkan RUU ini hanya menambah kesan bahwa DPR lebih melindungi elit daripada kepentingan rakyat.
Kelima, reformasi fiskal harus diarahkan pada pemerataan ekonomi. Pajak kekayaan, pajak warisan besar, dan pengenaan pajak atas capital gain perlu diperluas agar beban fiskal tidak terus ditanggung rakyat kecil melalui PPN dan pajak konsumsi lainnya. Subsidi harus lebih tepat sasaran, ditujukan pada kelompok rentan, bukan justru dinikmati kelompok mampu. Program sosial seperti bantuan langsung, beasiswa, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas karena terbukti efektif mengurangi ketimpangan.
Langkah-langkah minimal ini bukan hanya merespons tuntutan mahasiswa yang mendatangi Senayan, tetapi juga menyelamatkan legitimasi negara di mata rakyat. Krisis yang kini terjadi merupakan gejala dari persoalan struktural yang lebih dalam. Jika pemerintah dan DPR berani menjalankan agenda ini, demokrasi Indonesia akan mendapat energi baru untuk bertahan. Dunia usaha akan memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Namun jika diabaikan, yang tersisa hanya kekecewaan publik yang sewaktu-waktu bisa meledak jauh lebih besar.
Baca Juga
Badai Perlawanan Rakyat Pati
Supremasi sebagai Jalan Menyelamatkan Republik
Belajar dari sejarah, kekuasaan yang abai pada rakyat selalu runtuh dengan cara dramatis. Orde Lama tumbang karena ekonomi memburuk dan politik represif. Orde Baru tumbang karena korupsi, krisis dan otoritarianisme. Kini, Reformasi bisa runtuh jika kita gagal menegakkan supremasi sipil, supremasi konstitusi, dan keadilan fiskal guna memulihkan legitimasi negara.
Saat ini mahasiswa sedang memainkan peran historis. Mereka tidak sekadar menuntut idealisme abstrak, tetapi menegaskan hal paling mendasar, republik hanya bisa bertahan jika kekuasaan tunduk pada rakyat dan hasil pembangunan terbagi adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang paling berhak.
Gerakan masyarakat sipil adalah alarm moral yang harus didengar DPR dan pemerintah. Demokrasi kita tidak boleh lagi jatuh pada lingkaran gelap otoritarianisme dan oligarki. Jalan satu-satunya adalah menegakkan supremasi sipil, supremasi konstitusi, dan reformasi fiskal yang berpihak pada rakyat.
Abi S Nugroho, pengurus Lakpesdam PBNU
Terpopuler
1
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat
2
Prabowo Sebut Polisi yang Langgar Hukum dalam Penanganan Demo Akan Ditindak
3
Prof. Moh. Koesnoe, Cendekiawan NU Kaliber Dunia: Ahli Hukum Adat dan Pendidikan
4
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
5
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
6
Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen oleh Polisi Dinilai Keliru dan Salah Sasaran
Terkini
Lihat Semua