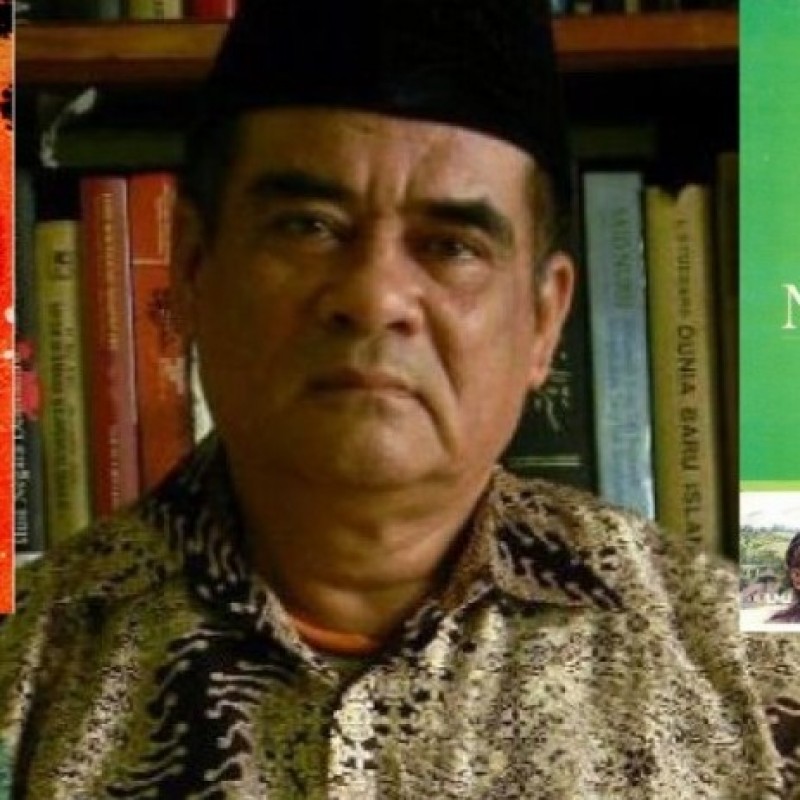Sementara ajengan di pesantrenku, membolehkan untuk menceritakan cita-cita. Menurutnya, cita-cita adalah satu tekad.
Abdullah Alawi
Penulis
Oleh Rahmatullah Ading Afandie (RAF)
Ada sebagian ajengan yang menghukumi makruh ketika menceritakan cita. Pasalnya menceritakan cita-cita akan mendekatkan diri pada ujub (sombong) dengan umur. Sombong karena kita seolah akan berumur panjang. Padahal umur bukan perkara yang harus disombongkan. Umur tiada yang pernah tahu, bisa nanti sore atau besok pagi batasnya. Begitu menurut ajengan yang menghukumi makruh.
Sementara ajengan di pesantrenku, membolehkan untuk menceritakan cita-cita. Menurutnya, cita-cita adalah satu tekad. Terus bagaimana kalau umur kita tak sampai pada cita-cita, menurut ajenganku, itu bukan urusan kita. Cita-cita adalah niat untuk sesuatu.
Suatu ketika, ajenganku mengomeli Si Salim, santri yang terbilang cerdas. Pasalnya cita-cita. Ajengan pernah bertanya soal itu. Si Salim menjawab, “Saya mah bagaimana Allah yang mengatur saja."
"Pasrah pada takdir Allah itu benar. Tapi ikhtiar merupakan kewajiban. Berharap takdir Allah tanpa ikhtiar tiada bedanya dengan seorang sehat jasmani rohani, tapi kerjaannya mengemis. Innallaha la jughayyiru ma biqaumin, hatta jughayyiru ma bi anfusihim, bagitu kata Al-Qur’an. Allah ta'ala tak akan mengubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tidak melakukan upaya untuk mengubahnya. Wa'arifta ya bunayya (ketahuilah, anak-anakku) apa yang disebut dengan kaum? Kaum adalah kumpulan nas (manusia). Jadi, sama saja Innallaha la yughayyiru ma biinsani, hatta yughayyiru ma bi anfusihi."
Begitulah, Ajengan pesantrenku memberi tekanan penting untuk cita-cita.
“Yang disebut dengan takdir dalam rukun iman itu adalah kondisi yang dibarengi dengan ikhtiar manusia. Jadi soal ikhtiar itu penting. Kalau satu kondisi jelek setelah melakukan ikhtiar untuk memperbaikinya, itulah yang disebut dengan takdir jelek. Belum disebut takdir jika belum ada upaya untuk mengubahnya. Nah, ikhtiar inilah yang terkait dengan cita-cita,” jelas Ajengan.
Sejak mendapat penjelasan ajengan seperti itu, santri-santri di pesantrenku sering tafakur memikirkan cita-cita.
Pada kesempatan lain, ajengan kadang bertanya tentang cita-cita pada santri. Mang Udin mempunyai cita-cita ingin meninggal mengikuti ajengan di pesantren.
Mendengar cita-cita seperti itu, Si Atok berkomentar:
"Cita-cita Mang Uding satu di antara dua kemungkinan. Pertama, ingin dipuji. Kedua, ingin selalu berdekatan dengan Nyi Halimah, putri ajengan."
Kang Haer bercita-cita ingin punya madrasah. Kang Usman ingin punya pondok pesantren dengan usaha sampingan beternak ikan. Si Umar punya cita-cita rada aneh, ingin jadi ajengan!
Ajengan bertanya kepada Si Umar.
"Apa sebabnya kamu bercita-cita ingin jadi ajengan?"
"Agar punya tanah wakaf!" jawabnya.
Ajengan memalingkan mukanya. Memang, ia mendirikan pesantren di tanah wakaf. Juga sawah beberapa petak yang berstatus sama.
Cita-cita tergantung pada cara berpikir lingkungan tempat seseorang tinggal. Karenanya tak heran jika aku memiliki cita-cita paling tinggi dibanding dengan santri-santri lain. Sebab, pertama, aku pernah sekolah di kota, kedua, lingkungan keluarga di kampungku. Disebut sebagai paling tinggi di antara santri lain, karena cita-citaku waktu adalah jadi penghulu! Silakan ditertawakan juga, tapi aku berani bersumpah itulah cita-citaku. Kalau ada yang tak percaya, aku bisa menyebut beberapa saksi. Ustadz Hudori, direktur sekolah panghulu di Ciamis waktu itu tentu masih ingat bahwa aku pernah diantarkan kakek agar aku diterima jadi murid di sekolahannya. Tapi ditolak karena aku masih terlalu muda.
Kemudian dia menganjurkan agar aku sekolah dulu di madrasah Miftahul Huda (miftah = kunci, huda = petunjuk). Soal aku pernah sekolah di Miftahul Huda, banyak saksinya.
Aku menjelaskan demikian karena bisa jadi ada yang menyangka bahwa cita-citaku ingin jadi panghulu hanya rekaan belaka.
"Apa sebabnya ingin jadi penghulu?” tanya seseorang. Ini yang bertanya buka ajengan sebab dia tidak mengomentari dan bertanya ketika mendengar cita-citaku. Ia malah menadahkan dua telapak tangannya, berdoa agar tercapai. Di kemudian hari, jangankan jadi penghulu, sebagai modin pun aku tidak pernah. Ini bukan doa ajengan tidak bertuah, lebih karena aku tak berikhtiar.
Mang Udin yang bertanya kenapa aku ingin menjadi penghulu. Ia bertanya seperti itu karena aku pernah mendengar bahwa Nyi Halimah bercita-cita ingin jadi istri seorang penghulu. Keinginan Nyi Halimah tak ada hubungannya dengan cita-citaku. Aku berani bersumpah cita-citaku bukan karena mendengar cita-cita Nyi Halimah. Wallahi, bukan lantaran itu! Aku juga tak percaya omongan Si Atok yang bercerita bahwa Nyi Halimah punya cita-cita jadi istri penghulu karena mendengar cita-citaku. Tidak, aku tidak percaya. Aku yakin itu akal-akalan Si Atok. Aku yakin karena ulah Si Atok pula sehingga Mang Udin begitu penasaran apa alasanku ingin jadi panghulu.
(Pembaca harus melihat bagian-bagian sebelumnya, bahwa Mang Udin sebetulnya menyukai Nyi Halimah)
Aku menjawab pendek saja atas pertanyaan Mang Udin waktu itu. Tapi, ah, buat apa aku menceritakan jawabanku waktu itu. Lebih baik aku menjelaskan versiku yang lebih lengkap. Pasalnya kalau menceritakan jawabanku waktu itu, aku terjatuh pada ghibah (bergunjing). Sebab sku masih ingat, mendengar jawabanku waktu itu, Mang Udin seperti tambah membenciku.
Cerpen ini diterjemahkan dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia oleh Abdullah Alawi dari kumpulan cerpen otobiografi Dongeng Enteng ti Pesantren. Kumpulan cerpen tersebut diterbitkan tahun 1961 dan memperoleh hadiah dari LBBS di tahun yang sama. Menurut Adun Subarsa, kumpulan cerpen tersebut digolongkan ke dalam kesusastraan Sunda modern sesudah perang.
Nama pengarangnya Rahmatullah Ading Afandie sering disingkat RAF. Ia lahir di Ciamis 1929 M. Pada zaman Jepang pernah nyantri di pesantren Miftahul Huda Ciamis. Tahun 1976, ia muncul dengan sinetron Si Kabayan di TVRI, tapi dihentikan karena dianggap terlalu tajam mengkritik. Ketika TVRI cabang Bandung dibuka, RAF muncul lagi dengan sinetron Inohong di Bojongrangkong.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri
5
Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan
6
Gus Yahya Ajak Warga NU Baca Istighfar dan Shalawat Bakda Maghrib Malam 12 Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua