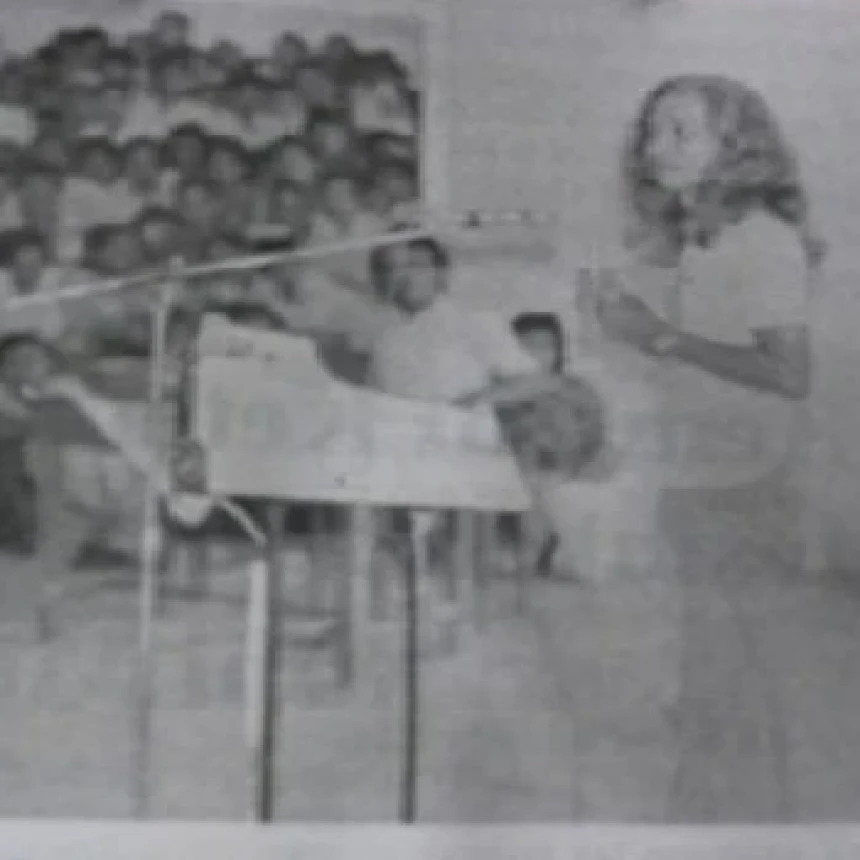Sound Horeg: Pemujaan Ledakan Audio dan Krisis Estetika
NU Online · Ahad, 13 Juli 2025 | 18:44 WIB
Nurani Soyomukti
Kolomnis
Disebut sound horeg karena bukan hanya suara (audio) yang volumenya keras dan kadang dianggap melampaui batas. Tapi juga ada efek horeg atau getaran dan hentakan bunyi yang membuat bumi dan benda-benda di sekitarnya bergerak dan bergetar keras. Efek terburuknya adalah bagian rumah yang rontok dan runtuh ketika ‘sound system’ lewat di dekatnya. Juga efek kesehatan, terutama bagi yang punya sakit jantung.
Itulah yang menyebabkan keberadaan sound horeg mendapatkan respons dari berbagai kalangan masyarakat. Puncaknya adalah dikeluarkannya fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg. Yang banyak disorot MUI Jatim adalah bahwa dampak negatifnya, bukan hanya dampak suaranya, tapi juga ekosistem performa seperti dilibatkannya para dancer yang mengumbar syahwat di ruang publik.
Awalnya sound horeg adalah soal suara. Kemampuan sound system yang menghasilkan suara pada volume yang sangat tinggi. Volume tinggi dan getaran kuat dari suara dapat menyebabkan polusi suara yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Apalagi jika kebisingan yang berlebihan dihadirkan dan terjadi pada waktu-waktu yang tidak tepat seperti larut malam atau dini hari, dapat mengganggu tidur dan menyebabkan stres pada penduduk sekitar. Selain waktu yang tidak tepat, mungkin juga tempat yang tidak pas.
Awalnya, sound system yang menghasilkan suara keras adalah kebutuhan fungsional untuk menyampaikan pesan agar suara yang disampaikan bisa menjangkau kerumunan massa yang jumlahnya besar. sound horeg digunakan dalam kampanye politik, kegiatan keagamaan, dan acara komunitas. Sound horeg digunakan untuk menyampaikan orasi, pidato, dan pesan-pesan penting kepada massa, memastikan bahwa suara orator atau penceramah terdengar jelas oleh audiens di lapangan terbuka atau ruang besar.
Tapi belakangan ini, kira-kira sekitar empat atau lima tahun terakhir, sound horeg menjadi tradisi di mana keras-kerasan volume suara dijadikan ukuran estetik dari kehadiran musik. Lalu musik yang dipilih kebanyakan juga musik ala diskotik dan ala DJ. Ditambah lagi kehadiran para perempuan seksi dengan goyang asik yang dianggap sensual yang dikhawatirkan merusak moral generasi karena dampak sosialnya—menjadikan penari seksi sebagai inspirasi yang akan ditiru anak-anak.
Tari-tarian sensual yang semata menghibur audiens yang mengeksploitasi tubuh yang biasa dilakukan di tempat tertutup (diskotik, club-club malam) tidak seharusnya disemarakkan di tempat publik.
Basis Ekonomi dan Identitas Budaya
Jika ditinjau dari aspek kebudayaan, pada perkembangannya eksistensi sound horeg bukan sekadar menjadi alat fungsional untuk memperluas jangkauan pesan dengan kemampuannya menghasilkan suara dengan volume yang terjangkau agar pesan yang disampaikan efektif. Yang terjadi kemudian adalah semacam identitas budaya yang dibangun oleh komunitas pemuja suara keras. Semakin keras dan daya horeg-nya kian tinggi, maka kebanggaan semakin tinggi.
Baca Juga
Prinsip Kebudayaan Gus Dur
Estetika seni yang ditekankan bukan lagi memperdengarkan pesan yang disampaikan, tapi seberapa besar volume suara yang dihasilkannya. Di sinilah, para pelaku sound horeg berlomba-lomba untuk menginstalasi sound system yang diharapkan menghasilkan suara sekeras mungkin. Menghadirkan sound system dengan suara keras ternyata secara teknis juga membutuhkan alat angkut dan ukuran benda-benda dan peralatan yang pada praktiknya membuat ribet. Kenyataan di lapangan yang bisa kita lihat adalah betapa iring-iringan sound horeg kesulitan lewat di jalan-jalan.
Dampaknya ternyata merusak apa-apa yang dilewatinya. Misalkan, ada rumah-rumah yang bagiannya rontok karena dekat jalan yang dilewati sound horeg akibat getaran bunyi yang melampaui batas. Jembatan dihancurkan agar iringannya bisa lewat, dan apa pun dikorbankan agar kendaraan yang membawa sound horeg bisa lewat dan diparadekan di publik. Hal yang sudah ada dan terpasang lebih dulu, harus dikorbankan hanya karena ada yang melewatinya. Dalam hal ini, tampaknya kejiwaan di mana sound horeg merasa lebih penting dari yang lainnya.
Perasaan itu seperti semacam fanatisme orang beragama, di mana klaim kebenaran suatu pemeluk agama kadang menganggap agama lain salah dan layak tidak ada atas nama kebenaran agama sendiri yang paling benar. Sound horeg menjadi semacam ekosistem pemuja “tuhan” bernama suara keras yang disembah. Alasan memuja adalah bunyi yang keras. Yang paling keras adalah dewa tertinggi. Kepemilikan dan perayaan terhadap sound horeg yang punya suara keras adalah prestise. Pemilik sound horeg yang volume suaranya paling mengagumkan menjadi tokoh yang ternama layaknya nabi yang punya banyak pengikut.
Parade sound horeg seperti sebuah ritualnya para penyembah volume bunyi itu. Mereka punya ekosistemnya sendiri, misalnya adalah pemilik sound horeg yang merupakan pilar utama budaya para pemuja bunyi keras. Tentu saja sound horeg bukanlah agama dalam makna sebenarnya. Budaya ini berbasis pada ekosistem ekonomi.
Pemilik sound horeg jelas adalah orang yang berduit karena mampu membeli perangkat-perangkat bunyi-bunyian atau sound system yang mengagumkan. Harganya ada yang ratusan juta, ada juga yang miliaran. Mereka punya motif ekonomi sekaligus motif mengejar prestise. Punya seperangkat sound system yang terkenal horeg-nya, artinya juga memungkinkan peralatan itu disewa dalam banyak acara. Keuntungan ekonomi mengalir. Prestise karena kepemilikan sound system adalah tanda bahwa mereka orang kaya.
Yang menikmati hasilnya di awal tentu saja adalah perakit sound system. Mereka bekerja untuk merakit sound system yang kemudian dijual pada orang yang menjual jasa sound. Terhadap perakit inilah pada awalnya kekaguman diberikan. Bagaimana misalnya hanya dengan berapa subwoofer dan rakitan custom, efek audio yang dihasilkan bisa mengagumkan. Terutama suara yang sangat keras tapi dianggap detail. Seperti yang belakangan terkenal dengan bunyi “nrotok” (tok tok tok tok tok tok) untuk lagu-lagu tertentu yang sering diputar dalam parade sound horeg.
Jasa yang disewakan kadang juga satu paket, termasuk di dalamnya keberadaan dancer. Para dancer juga mendapatkan penghasilan. Icha Cellow, seorang dancer paling viral di JawaTimur, mengaku pernah dapat uang lima juta sekali tampil. Selain itu, sound horeg sering digunakan dalam acara-acara menarik perhatian audiens. Orang-orang yang jualan dari massa yang berkumpul bisa memberdayakan para pedagang kecil. Inilah yang membuat sebagian kalangan memandang bahwa keberadaan sound horeg juga ada sisi positifnya.
Pemuja Volume Bunyi dan Krisis Kebudayaan?
Di balik menyebarnya kegandrungan akan bunyi keras sound system diiringi para dancer yang dieksploitasi tubuhnya oleh penonton—khususnya para lelaki—dengan goyang ritmis dan semi-eksotis itu, tampaknya tersirat krisis kebudayaan di masyarakat kita. Krisis yang paling tampak adalah pada budaya mencipta.
Krisis penciptaan lagu memang sudah terjadi lama, terutama ketika kita hanya mendapatkan sajian lagu lama yang dinyanyikan ulang. Tidak ada, hanya sedikit sekali, lagu yang baru—rata-rata oleh kalangan indie. Atau lagu-lagu baru karya Deny Caknan dan sejenisnya—yang rata-rata lagu ‘ambyar’. Keambyaran lirik lagu—atau tema kesedihan yang terlalu dominan itu sendiri—bagi saya juga punya dampak buruk, misalnya membentuk generasi cengeng, terlalu terlemahkan jiwanya karena dominasi lirik-lirik cinta patah hati.
Lagu-lagu lama di-cover oleh penyanyi baru dan disajikan lewat media sosial. Atau penyanyi satu menyanyikan lagu penyanyi lainnya, yang orangnya ya itu-itu saja. Jumlah musisi berkurang. Jumlah pencipta lagu apalagi. Dan kebanyakan orang memang lebih suka mengonsumsi atau meniru daripada mencipta. Di sinilah, krisis kebudayaan basisnya adalah krisis penciptaan.
Baca Juga
Menyegarkan Peran Kebudayaan NU
Lalu, fenomena lainnya adalah memindahkan musik ala diskotik yang biasa “diimami” oleh DJ ke ruang-ruang publik. Dengan sound horeg jadi sajian yang dianggap paling indah dalam suatu pawai atau acara yang membutuhkan pengeras suara. Utamanya adalah pawai seperti acara karnaval dalam acara peringatan hari besar nasional (PHBN), seperti Peringatan Hari Kemerdekaan.
Pawai yang seharusnya isiannya punya dampak reflektif dan punya daya memorabilitas terhadap perjuangan merebut kemerdekan serta memparadekan capaian pembangunan, justru didominasi oleh suara keras sound system dan perhatian audiens di pinggir jalan adalah tarian ‘pargoy’ diiringi musik ala diskotik. Esensi peringatan kemerdekaan tidak tercapai. Yang dominan adalah luapan hura-hura dan keberadaan para dancer seksi juga menjauhkan sebuah perayaan kemerdekaan jauh dari nilai edukasi.
Memang, sound horeg tidak hanya hadir di acara karnaval dan pawai. Kehadirannya juga ada di berbagai acara seperti acara pesta pernikahan atau acara keluarga besar. Dalam hal ini, kadang pihak yang punya hajat menginginkan sound horeg untuk memutar musik, memberikan pengumuman, dan memastikan suara pembicara terdengar oleh semua tamu.
Fungsi suara untuk menghantarkan pesan memang berbeda dengan fungsi sebagai hiburan atau yang bisa dianggap sebagai bagian dari kesenian. Musik dan bunyi-bunyian adalah cabang seni yang sebenarnya harus dianggap sebagai hak universal setiap manusia.
Artinya, mereka yang ingin berekspresi dengan peralatannya untuk menghasilkan suara dan bunyi tetap dijamin haknya. Hak ekspresi budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Orang atau kumpulan orang diberi hak untuk mengekspresikan diri melalui budayanya.Dalam negara yang berbineka seperti NKRI ini, hak ekspresi seni-budaya dianggap sebagai upaya untuk menjaga keanekaragaman budaya dan identitas suatu masyarakat.
Hanya saja, ada beberapa hal yang tak boleh dilupakan terkait hak asasi manusia di bidang kebudayaan. Pertama, hak ekspresi dari manusia tetap ada batasannya. Ekspresi hak tidak boleh melanggar hak orang lain. Hak orang untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, ketenangan. Termasuk dari suara keras dan menggetarkan (suara horeg) yang merusak rumah orang lain karena gentengnya rontok atau kacanya pecah, sakit jantung orang yang kambuh, atau merusak jembatan dan tiang agar sound horeg bisa lewat.
Kedua, negara kita sedang berupaya melakukan ikhtiar pemajuan kebudayaan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Di antaranya adalah pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Memasyarakatkan budaya DJ ke publik tampaknya tidak mengandung nilai-nilai luhur, apalagi kalau disertai dampak merusak. Keragaman budaya itu baik, tapi meninggikan budaya yang sesuai dengan jatidiri bangsa juga jauh lebih penting.
Dalam pemajuan kebudayaan juga menekankan pada upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Makanya, ekspresi budaya yang baik adalah yang edukatif. Sementara yang justru merusak moral dan memberikan inspirasi buruk pada anak-anak, seharusnya dicegah.
Sedangkan, esensi kebudayaan dari sound horeg adalah mendengarkan suara dengan ukuran estetiknya volume keras. Semakin suara keras dan menggetarkan dianggap yang indah. Padahal keindahan suara dan bunyi itu dalam kesenian biasanya bunyi atau suara yang selaras, bukan hanya urusan keras-kerasan volumenya saja. Penikmat sound horeg mengagumi sisi volume suara.
Hal lain, musik DJ dan perempuan-perempuan dancers seksi adalah estetika tubuh—yang mungkin menarik bagi kebanyakan laki-laki. Di sini ada sisi eksploitasi tubuh. Sisi inilah yang paling membahayakan ketika pemajuan budaya menitikberatkan pada daya cipta yang membiarkan orang (perempuan) menjadi objek untuk dieksploitasi orang lain.
Baca Juga
Gus Dur, Dangdut, dan Rhoma Irama
Nurani Soyomukti, penulis dan pegiat literasi, saat ini sedang “nyantri” di pasca-sarjana Akidah dan Filsafat Islam (AFI) UIN Satu Tulungagung.
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua