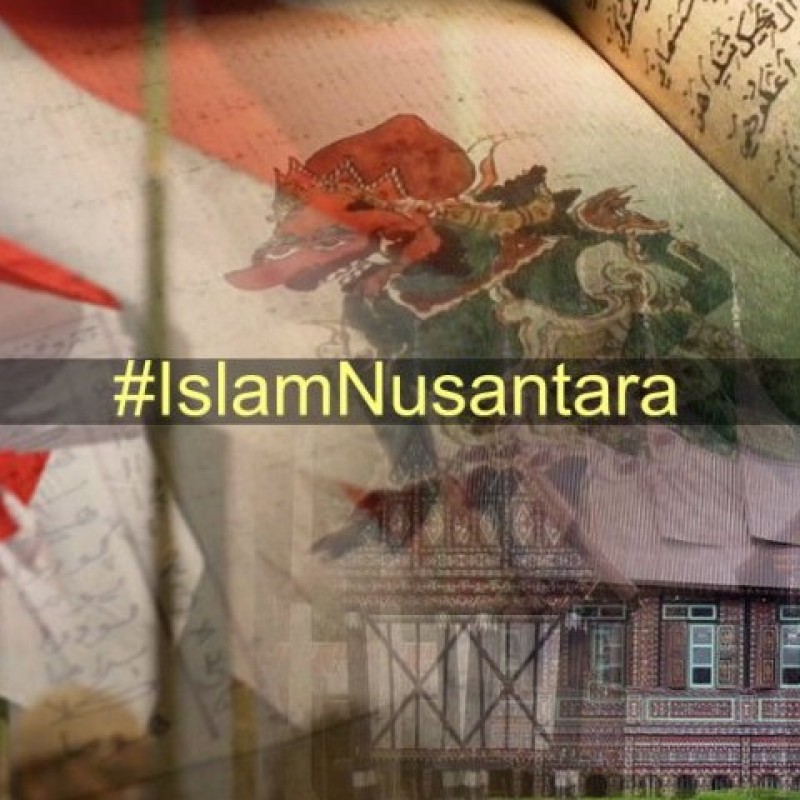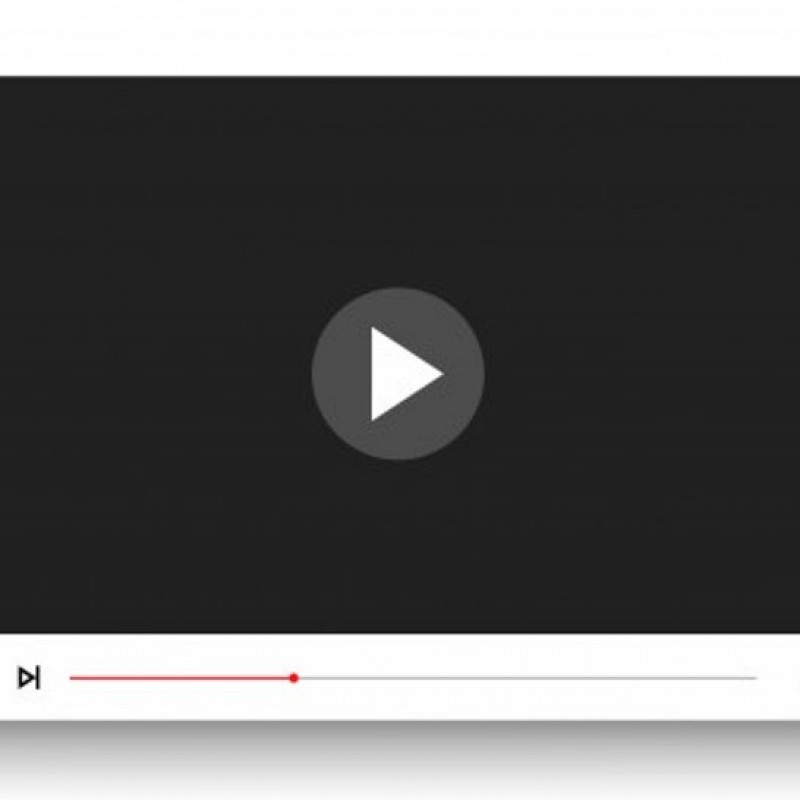Oleh Yanto Bashri
Dalam wacana keislaman istilah santri mulai diperkenalkan dalam wacana kebangsaan sejak antropolog berkebangsaan Amerika Serikat Clifford Geertz menghadirkan penelitiannya pada 1960. Dalam The Religion of Java, Geertz dengan gagahnya mengenalkan kata Santri, Abangan, dan Priayi sebagai poros keberislaman masyarakat Indonesia umumnya.
Istilah santri diperkenalkan Geertz, meski bukan kali pertama (baca: sejarah Belanda), menjadi pemantik lahirnya penelitian-penelitian baru kehidupan santri dalam sosial budaya dan sosial politk Indonesia. Penelitiannya di Mojokuto mendorong kaum intelektual terutama Barat berhasil mengungkap budaya yang bagi sebagian besar asing. Konsep trilogi –ada yang menyebut trikotomi—ala Geertz ini cukup popular di kalangan kaum intelektual telah jadi mukadimah bergairahnya kembali penelitian santri, masyarakat, dan politik.
Para peneliti menempatkannya sebagai karya monumental. Pengaruhnya tidak hanya pada dunia akademik untuk melakukan kajian baru, tapi dunia sosial masyarakat juga diwarnai kontestasi cukup dinamis sebagaimana elaborasi trilogi tersebut, mirip perjuangan kelas yang digambarkan Karl Marx.
Santri utama
Geertz menggambarkan santri sebagai individu dalam masyarakat yang paling agamis: sering berpuasa, shalat, zakat, ngaji, dan lainnya. Sementara abangan ditempatkannya sebagai individu yang seringkali melakukan bid’ah.
Gambaran semacam ini yang menarik perhatian para peneliti. Pasca Geertz menerbitkan karyanya pada 1960 tidak sedikit karya baru lahir, misalnya Mark R. Woodward, The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam (1988), Andrew Beatty Adam and Eve and Vishnu: Syncretism in the Javanese Slametan (1996), Linda S. Walbridge (1998) The Santri-Wati Of Indonesia's Pesantren: Orientations Of Students Ofthree Girls' Religious Schools, dan lainnya.
Kemudian memasuki periode berikutnya muncul karya André Möller (2006) Islam and Traweh. Prayers in Java, Muhamad Ali (2011) Muslim diversity: Islam and local tradition in Java and Sulawesi, Indonesia, Timothy Daniels (2016) Islamic Spectrum in Java, MC Ricklefs (2014) Rediscovering Islam in Javanese History, Nathan John Franklin (2014) Reproducing Political Islam in Java, dan lainnya.
Selain memperlihatkan tingkat keterpengaruhan (influence), sebagaimana juga Geertz, karya para peneliti memperlihatkan santri sebagai bagian dari kelompok masyarakat taat menjalankan agama. Pemahaman ini berjalan selama beberapa periode meski para peneliti melakukan kajian dengan metode dan perspektif berbeda.
Fenomena keterpengaruhan peneliti juga dapat dipahami sebagai bentuk keberhasilan kiai yang menempatkan pesantren sebagai subkultur di tengah menguatnya pendidikan sekolah. Kiai memperlihatkan kekuataannya membangun pesantren sebagai lembaga alternatif yang tetap konsisten melahirkan generasi-generasi utama.
Santri pinggiran
Kita melihat kemampuan kiai untuk menjadikan pesantren sebagai kekuatan alternatif teruji. Selama beberapa periode pesantren mampu melahirkan generasi berkarakter sesuai zamannya. Namun keberhasilan ini tidak berlaku dalam dunia politik. Usaha kiai untuk mengantarkan santri memiliki kemampuan kepemimpinan nasional tidak sebanding dengan bidang keagamaan. Para peneliti menempatkan pesantren sebagai political periphery (politik pinggiran).
Penilaian ini juga berkembang pada saat diskusi buku Nasionalisme Kaum Sarungan karya Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini pada 19 Juli 2018. Faishal menggambarkan kehidupan santri yang tidak berubah hingga sekarang, yaitu memakai peci dan sarung, merupakan tradisi tidak dapat dimaknai tradisionalisme sebagaimana makna simboliknya, melainkan ia mengonstruksi diri sebagai political archeologists. Santri adalah seorang yang mampu memberikan interpretasi tradisi komunal dalam rangka menumbuhkan kembali komunitas.
Diskusi dipandu Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi menghadirkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, Guru Besar Australian National University (ANU) Greg Fealy, dan wartawan senior Kompas Mohamad Bakir. Mereka sepakat pentingnya menghadirkan perilaku-perilaku santri di ruang publik sebagaimana kehidupan sehari-hari dengan kiai, guru, dan sesama santri selama di pesantren di tengah menguatnya ekstremisme politik dan agama.
Pentingnya santri berada di ruang publik dapat diukur dalam dua hal berikut. Pertama, tawadhu. Ciri khas seorang santri adalah tawadhu (rendah diri). Sifat ini ditanamkan kepada santri sejak ia berada di pondok melalui pengajaran kitab-kitab yang dikarang para ulama abad pertengahan. Pengajaran kitab semacam ini jadi ciri khas pesantren untuk membentuk sikap sosial dan individual santri.
Tawadhu merupakan derivasi dari akhlak, bahasannya ada di banyak kitab klasik. Kiai tidak mewajibkan setiap santri mengikuti pengajian, tetapi setiap santri dapat dipastikan telah mengaji kitab-kitab yang dijalankan kiai sebelum meninggalkan pesantren.
Kedua, cinta bangsa. Ciri berikutnya dari seorang santri adalah seorang pelajar yang menempatkan tanah kelahiran dan bangsanya sebagaimana rumah sendiri yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Bagi santri bangsa adalah rumah besarnya.
Cinta santri terhadap Tanah Air, sebagaimana sifat tawaduk, diperoleh juga melalui pelajaran kitab kuning. Ia ada dalam jiwa santri sebagai ruhul jihad (semangat jihad) yang ditunjukkan ketika menghadap serangan luar maupun tekadnya memelihara keberlangsungan bangsanya. Perilaku semacam ini memberikan gambaran bahwa santri adalah yang dalam jiwanya tertanam nasionalisme.
Gambaran santri sebagai kelompok masyarakat yang paling taat sebagaimana digambarkan oleh Geertz lebih karena sarung, peci, pakaian, membawa kitab, dan bermukim bersama kiai di pesantren. Sementara gambaran santri dalam bidang politik perlu mendapat perhatian serius kiai. “Nasionalisme tidak tumbuh tanpa unsur politik dan tidak ada bangsa lahir pendidikan politik terlibat di dalamnya." (Nodia, 1992: 22)
Penulis adalah Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri
5
Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan
6
Gus Yahya Ajak Warga NU Baca Istighfar dan Shalawat Bakda Maghrib Malam 12 Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua