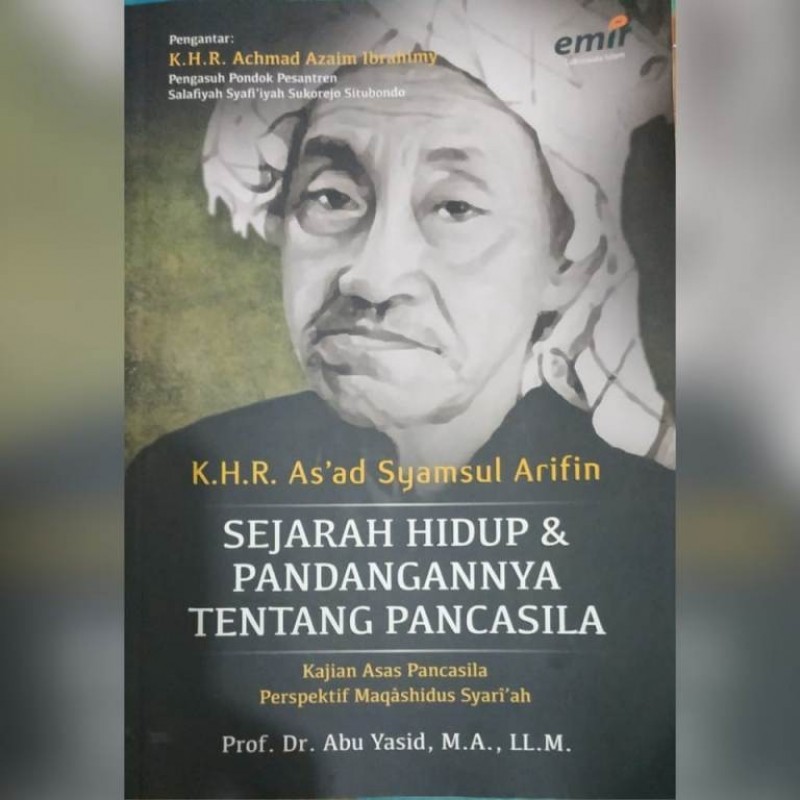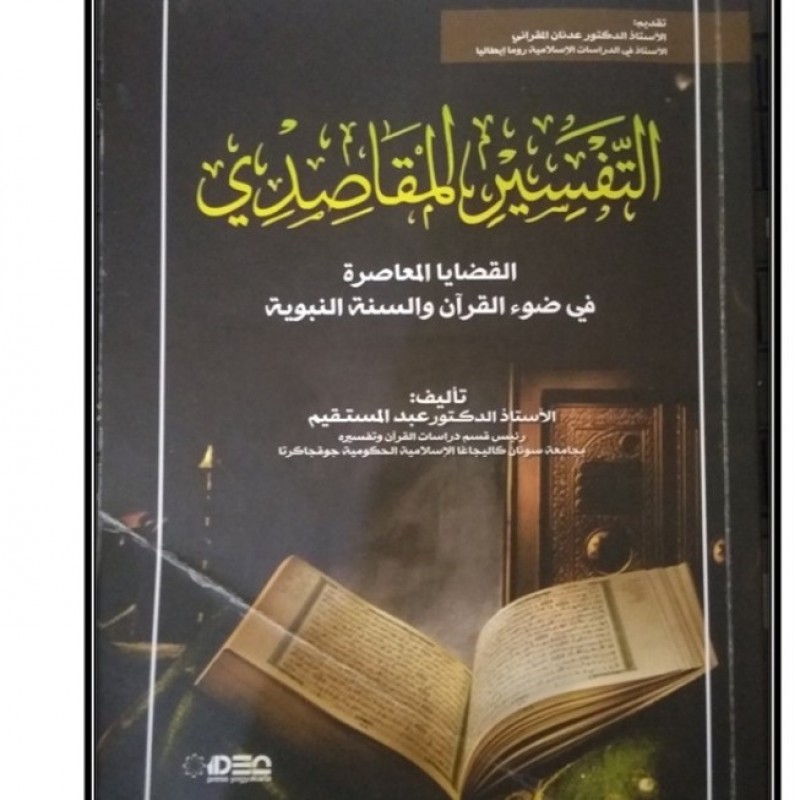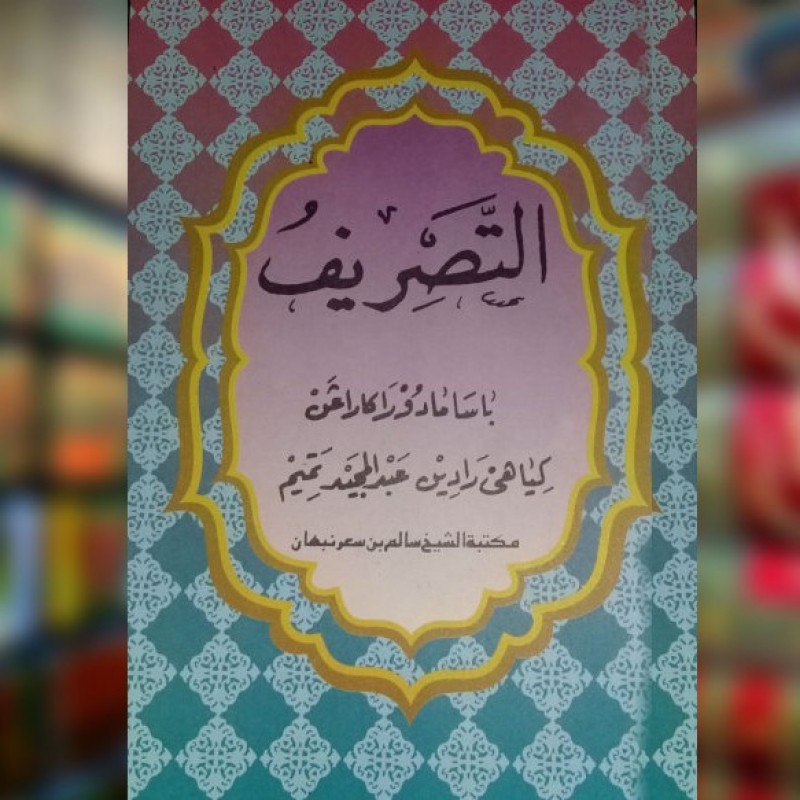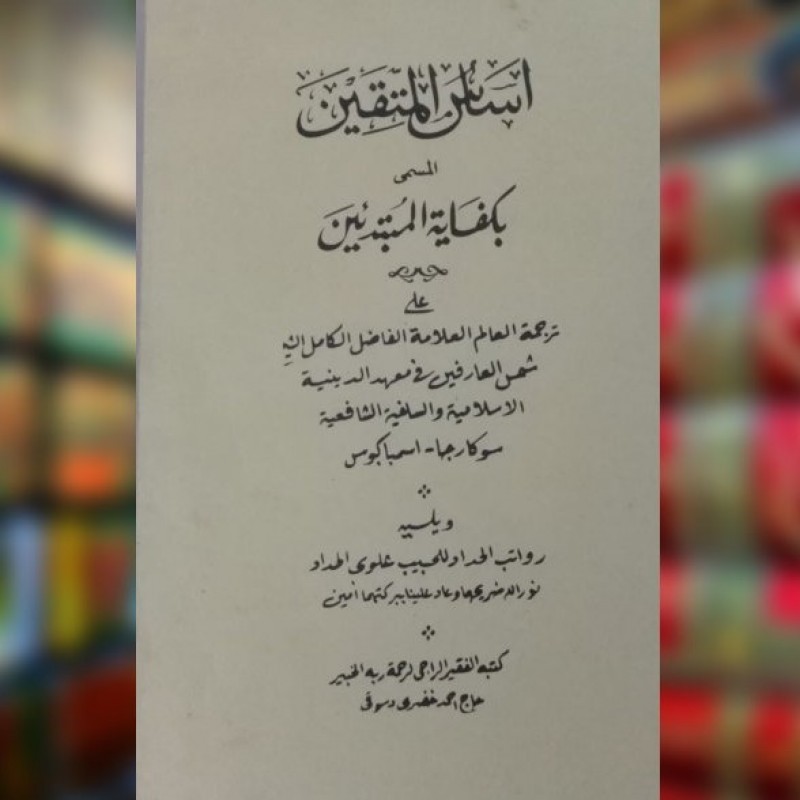Fahri Hilmi
Kolomnis
Z barangkali tak menyangka kalau sekolah yang diidamkannya justru menjadi tempat paling tidak nyaman. Secara kompak, guru agamanya dan seorang siswa merundung Z oleh sebab ia tak mengenakan jilbab.
Pikiran sang guru mungkin baik. Namun, sodorannya gelap. Ia tak membimbing. Ia meneror. Di tangannya agama tak lagi cerah, ia dibuat kelam. Nafsu berahi kebenaran telah menjadi bilik yang membutakan. Bukannya menjadi teladan, sang guru tak ubahnya sesosok menakutkan.
Perundungan itu terus berulang hingga Z tak merasa nyaman. Ia ajukan protes, tetapi dianggap lalu. Bahkan, dianggap subversif. Sang guru menutup telinga dari macam-macam keluhan dan ngotot mendaku benar. Kepala sekolah pun demikian. Z mundur.
Tak menutup kemungkinan, saking takutnya, Z malah antipati terhadap jilbab. Penanganan dari pihak berwajib jangan ditanya. Karena lamban, kini Z mesti alami trauma terhadap sekolah yang dahulu ia idamkan. Ia sudah tak mau berangkat sekolah. Ia terlanjur takut.
***
Cuplikan di atas nyata terjadi di SMAN 1 Gemolong, Sragen beberapa waktu lalu. Kasus ini menjadi burhan atas fenomena perwajahan agama yang menakutkan, seram, dan barangkali mengekang.
Sang guru gagal menyajikan agama dengan wajah yang teduh. Saya cukup yakin, guru itu mesti belajar lagi. Atau jika terlampau gengsi, setidaknya bacalah buku Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar! karya Kalis Mardiasih ini. Mari beragama dengan gembira.
Agama Tak Semenakutkan Itu
Sajian agama belakangan ini memang diwarnai dengan ketakutan. Jika tidak A, maka hukumannya cambuk neraka. Jika tidak B, jangan harap alam kuburmu riang bahagia. Tampaknya, manusia lupa kalau penentu kebijakan akhirat hanyalah Tuhan semata.
Kalis tak demikian. Ia menampilkan agama dengan wajah yang semestinya. Begitu teduh, menenangkan, dan penuh kegembiraan. Dalam tiap-tiap esainya, Kalis menulis manusia dengan posisi sebagaimana mestinya: tunduk, diam, dan mengembalikan kepada Tuhan segalanya.
Sebagai pembuka, Kalis pilih bab soal kanak-kanak dan agama. Ia sentil-sentil masa kecil manusia saat awal mula kenal agama. Kanak-kanak adalah menyambangi surau untuk mengaji tanpa tendensi apa pun. Kanak-kanak adalah masa yang polos, tanpa dendam, dan dengan siapa pun dapat bersama. Begitu indah, hanya suka cita.
Di lain waktu, saya sempat membaca barang dua-tiga cerpen dalam Batu-Batu Lapar karya Rabindranath Tagore--yang terjemahannya diterbitkan Penerbit Narasi. Di punggung buku, tertulis sinopsis yang ada benarnya.
Disebutkan bahwa nabi dan anak-anak memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama mempunyai visi dan imajinasi kreatif tentang dunia. Bedanya, nabi dapat mendistribusikan visinya pada umat manusia, dan anak-anak sekadar menikmatinya.
Kalis pun demikian. Ia adalah ‘anak-anak’ yang sedikit banyak menganut apa yang dipercaya Tagore. Anak-anak hanya tahu bahagia, menikmati risalah agama. Contohlah salah satu esainya yang berjudul “Berislam Seperti Kanak-Kanak”. Di dalamnya, tanpa malu Kalis mengisahkan masa kecilnya yang sedang riang-riangnya mengaji di surau kampung.
Bersama teman sebaya, Kalis kecil tak tanggung-tanggung menyematkan ejekan kepada sang guru ngaji: Si Jenggot Naga. Katanya, pak Ustadz kerap mengelus-elus jenggot panjangnya saat sorogan. Bocah-bocah itu riang dengan ejekan. Lalu, apakah gerombolan bocah itu dibayang-bayangi undang-undang penistaan agama? Nyatanya tidak.
Esok hari, mereka tetap menaruh hormat pada sang guru. Surau tetap dikunjungi. Begitu terus hingga lancar mengaji. Agama dapat, bahagia dapat.
Belum. Kisah kanak-kanak yang mengagumkan sekaligus lucu itu belum usai. Satu di antara gerombolan Kalis kecil ternyata adalah penganut kepercayaan lain. Sesama bocah tentunya. Lalu, dari demikian banyak hari mereka mengaji, apakah si 'kafir’ tadi dimusuhi? Sekali lagi, nyatanya tidak. Untungnya, mereka belajar agama ramah. Bukan doktrin kasar yang 'anti-asing’ dan serbamarah.
Melahap agama dengan gembira ternyata persis dengan melahap siomay dari plastik yang sama dengan kawan beda agama. Segerombolan itu tetap solid. Datang ke surau bersama-sama, mengaji, lalu berseloroh di antara antrean sorogan. Bocah berbeda tadi tetap dimintai siomaynya. Tetap berbagi tak ada curiga. Lihat, bukan? Melalui kisah polos ini, Kalis memperlihatkan agama yang tidak 'anti-anti’.
Signifikansi agama yang demikian ternyata tak perlu dicapai melalui ragam panjang filsafat kemanusiaan. Anak-anak adalah kejujuran. Bersama kejujuran itulah anak-anak tak punya amarah elektoral. Asal kita sama riangnya, kita adalah teman. Agama? Barangkali kereta dari keriangan itu. Maka, bisa jadi anak-anak justru curiga kalau ada kejengkelan darinya. Mungkin bukan agama. Siapa tahu begitu.
Bisa kita buktikan dengan esai Kalis yang lain. Judulnya “Anak-Anak Tidak Marah”. Di dalamnya, Kalis memuat cuplikan dialog dalam salah satu cerpen Naguib Mahfouz. Saya kutip utuh dialog tersebut:
“BAPAK!”
“Ya?”
“Saya dan teman saya Nadia selalu bersama-sama.”
“Tentu, sayang. Dia kan sahabatmu.”
“Di kelas, pada waktu istirahat, dan waktu makan siang.”
“Bagus sekali. Ia anak yang manis dan sopan.”
“Tapi waktu pelajaran agama, saya di satu kelas dan ia di kelas yang lain.”
“Itu hanya pelajaran agama saja.”
“Kenapa, Pak?”
“Karena kau punya agama sendiri dan ia punya agama lain.”
“Bagaimana sih, Pak?”
“Kau Islam dan ia Kristen.”
“Kenapa?”
“Kau masih kecil, nanti akan mengerti.”
Betapa polos sang anak yang bertanya itu. Untung saja sang bapak tak ceroboh mengatakan agama A lebih baik daripada agama B. Jika saja begitu, barangkali anaknya akan menggugat kepercayaan kawan sebangkunya. Lebih parah, menjauhinya. Siapa jamin?
Jauh sebelum pertanyaan kritis itu hinggap di kepala si bocah, ia hanya tahu kalau Nadia adalah teman sebangku. Lalu, layaknya teman sebangku, mereka bersahabat. Tenang dan senang bergandengan tangan ke sana-ke mari. Mereka benar-benar mesra dengan berbeda.
Di tengah kegembiraan itu, perlukah Nadia ikut kepercayaan yang dianutnya agar persahabatannya gembira? Di dalam alam pikir dewasa, barangkali iya. Narasinya: agar Nadia juga 'selamat’. Namun, bagi sang bocah, tampaknya tidak. Mereka sudah gembira jauh sebelum mengenal istilah “agama berbeda”.
Kegembiraan itu berhasil diraih melalui kejujuran kanak-kanak, kejujuran manusia. Tanpa tedeng aling-aling bernama “perasaan berbeda”, mereka bisa duduk setara di bangku yang sama. Bocah itu dengan polosnya berhasil mendeteksi persamaan di antara keduanya, yakni manusia. Ya, mereka sama-sama manusia. Dengan alasan elementer itulah mereka berkawan mesra.
Kata Kalis dalam esai yang lain, “Sedikit-Sedikit Minta Dalil”, Islam adalah agama yang tak haus anggota. Ia tak begitu bangga jika statistik jumlah pemeluk Islam meningkat. “Buat apa?” katanya, “Toh kita semua memasuki yaumul mizan hingga menantikan yaumul hisab sendirian” (hlm. 76).
Agama itu Memuat Gembira
Narasi mengenai kanak-kanak tadi bukannya hendak melucuti agama dari badan manusia. Agama tetaplah institusi yang boleh dianut. Siapa pun dan apa pun.
Namun, Kalis hendak menyentuh sisi kejujuran kita. Bahwa beragama tak perlu tegang. Ia mengajak kita meneladani masa kanak-kanak kita sendiri. Masa kanak-kanak dapat dijadikan guru terbaik untuk memahami keramah-tamahan agama.
Bukti-bukti keteduhan itu tak berhenti pada tema kanak-kanak. Kalis membawa kita ke masa dewasa. Masa bocah tetaplah jadi parameter. Misal, saat remaja Kalis sempat menggugat ayahnya yang hanya tahu amaliyah vertikal tanpa peduli urusan kemanusiaan.
Beberapa waktu kemudian, Kalis mendapati ayahnya duduk di surau samping rumah, sedang bersujud, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kalis menangis, betapa ayahnya menanggapi gugatannya dengan diam juga bukti.
Sang ayah tak menjawab balik dengan getun dan arogan. Sang ayah telah memperlihatkan bahwa beragama ialah soal yang dekat. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, menciptakan kedamaian, lalu menawarkan kedamaian itu dalam kehidupan. Maka, sikap ramah adalah implementasinya.
Jika semua menganut narasi demikian, bukan tak mungkin perdamaian dapat dicapai. Soal damai, Kalis mempertontonkan kisah pertemuannya dengan Habib Luthfi bin Yahya.
Dalam ceritanya pada esai “Bertemu Abah Maulana Habib Luthfi bin Yahya”, Kalis menunjukkan cara menyikapi agama dengan keteduhan. Keteduhan itu ia tangkap melalui perangai Abah, sebutan Kalis untuk sang habib.
Abah tak menggebu-gebu melalui paksaan saat menyampaikan wasiat keagamaannya. Begitu tenang, tenteram, dan damai sehingga membuat risalah Rasul masuk ke relung umat dengan sukarela. Nyaris tak ada ujaran kebencian dari petuahnya. Kebaikan Islam tak perlu diperlihatkan dengan mencerca pihak lain.
Islam sudah baik sejak ia diciptakan, diturunkan ke tangan manusia. Tak perlu bagi Islam menodai bagian lainnya hanya untuk terlihat putih. Kesucian itu adalah Islam sendiri. Maka, tak mungkin bila ada noda amarah yang mengalir melalui risalahnya.
Kalis berhasil menampilkan kedamaian itu melalui tiap kisah hidupnya yang hadir dalam 35 esai. Ternyata, Islam damai itu sempat kita anut dahulu, sebelum narasi Islam yang marah menjadi populer dan mengontaminasi kedamaian itu. Kalis berhasil membantu kita mengingat-ingat kembali.
Nostalgia Kalis adalah nostalgia kita semua. Namun, nostalgia yang hadir bukan sekadar untuk dikenang lalu menjadi romantisme belaka. Masa lalu itu mesti dihadirkan bersama ibadah vertikal kita. Dengan begitu, kita percaya bahwa kedamaian di antara manusia adalah juga ibadah wajib yang mesti ditunaikan.
Peresensi adalah Fahri Hilmi, admin @pikiranlelaki_. Dapat ditemui di @fahrihill.
Identitas Buku:
Judul: Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar!
Penulis: Kalis Mardiasih
Penerbit: Buku Mojok
Terbit: November 2019 (cet 2)
ISBN: 978-623-7284-14-7
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Pengacara dan Keluarga Yakin Arya Daru Meninggal Bukan Bunuh Diri
5
Khutbah Jumat: Menjaga Amanah dan Istiqamah dalam Kehidupan
6
Gus Yahya Ajak Warga NU Baca Istighfar dan Shalawat Bakda Maghrib Malam 12 Rabiul Awal
Terkini
Lihat Semua