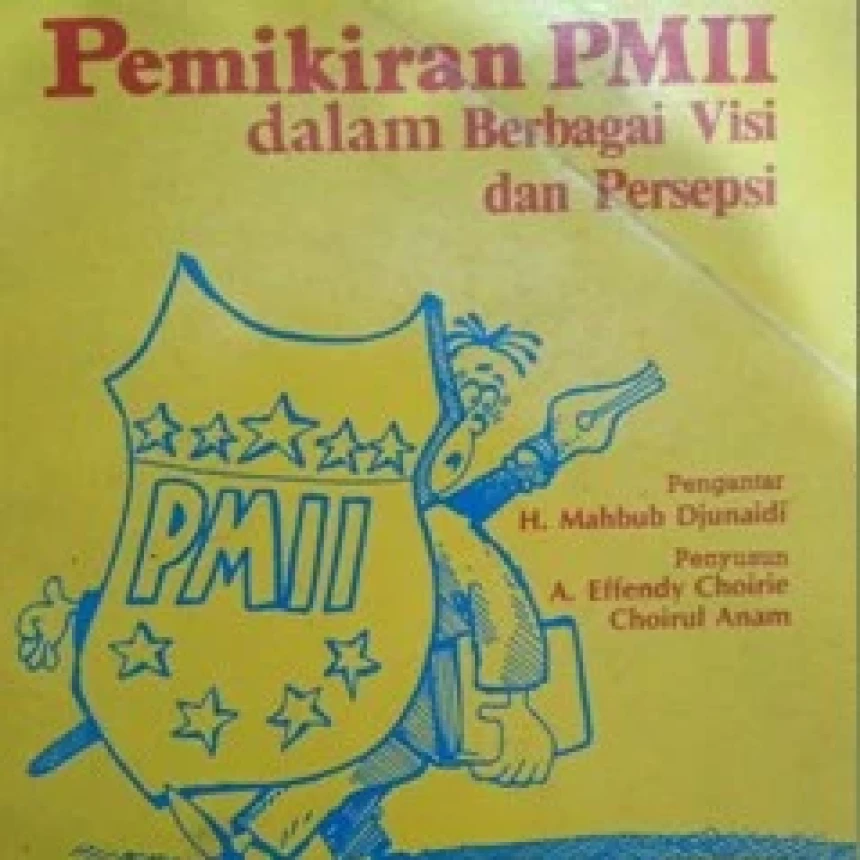4 Dekade Lakpesdam PBNU: Khittah, Kaderisasi dan Kekuasaan
NU Online · Jumat, 11 April 2025 | 14:00 WIB
Abi S Nugroho
Kolomnis
Bagi Robert Peterson, hidup dimulai ketika seseorang memasuki usia 40 tahun. Pandangan ini bukan motivasi, tapi cermin pencapaian kematangan psikologis dan eksistensial seseorang setelah melewati proses panjang pencarian jati diri. Buku yang telah sangat apik, cermat, dan jenaka diterjemahkan oleh H Mahbub Djunaidi diberi judul Hidup Baru di Umur 40 Tahun (1974).
Usia 40 manusia tak lagi dikuasai emosi yang ngelantur, melainkan digerakkan pengalaman yang telah menemukan bentuk, arah yang semakin presisi, dan memilih pekerjaan dengan sadar memberi kontribusi sebesar-besarnya.
Usia 40 tahun itu keramat. Angka yang dipercaya sebagai titik balik kehidupan manusia menuju puncak kematangan akal, spiritualitas, dan karakter. Dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15, Al-Qur’an menggambarkan usia ini sebagai fase ketika seseorang mulai benar-benar menyadari nikmat Allah dan pentingnya bersyukur, berbakti pada kedua orang tua, sembari berdoa agar dapat beramal saleh dan membimbing generasi penerus. Para ulama berpendapat, usia 40 menandai masa ketika watak seseorang cenderung ajeg, dan ketika itulah kesalehan serta kebijaksanaan ideal telah mengkristal. Bahkan, para nabi diangkat pada usia ini sebagai isyarat kesiapan penuh dalam menjalani misi kenabian (profetik).
40 tahun usia ketika Nabi Muhammad saw menerima wahyu pertama dari Allah swt melalui Malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, frasa “balagha asyuddahu” merujuk usia 40 tahun, usia kedewasaan penuh. Demikian juga Nabi Musa diutus memperingatkan Firaun. Saat itulah Nabi Musa menerima wahyu dan tugasnya. “Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami anugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu...” (QS Al-Qashash: 14).
Baca Juga
Lakpesdam, Pilar Keempat NU?
Dalam konteks organisasi, khususnya gerakan sosial keagamaan seperti Lakpesdam PBNU, usia 40 tahun bisa dibilang menandai fase kedewasaan institusional yang lebih teguh dalam pendirian pada nilai dan tidak bisa main-main, sudah seharusnya mengonsolidasikan visi, memperkuat struktur, dan mengefektifkan peran sosio kultural-strategisnya di tengah masyarakat.
Empat dekade adalah puncak kematangan akal dan batin. Maka, bagi sebuah organisasi, ini adalah saat merefleksikan jejak langkah, bagaimana mensyukuri atas panggilan sejarah, membalas jasa para pendiri dan pejuang awalnya, serta menguatkan kontribusi strategis bagi masyarakat dan bangsa. Merefleksikan kembali konsepsi Khittah dalam khidmah berjam’iyyah, memperkuat fondasi nilai-nilai dasar dengan keilmuan, keberpihakan, dan keberanian dalam menempuh jalan perubahan sosial.
Tanggal 7 April 2025 menandai momen berharga perjalanan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU). Tepat 40 tahun sejak didirikannya pada 1985, jika usia manusia sebagai analogi, maka usia 40 adalah titik balik: puncak kematangan, pintu masuk fase kebijaksanaan dan kontemplasi, sekaligus penanda masa di mana risiko stagnasi dan penyakit kronis bisa menyelinap tanpa disadari.
Kembali ke Khittah 1926 dan tugas kenabian
Bermula dari gagasan besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersama kelompok yang digerakkan dokter Fahmi Saifuddin, bahwa NU ingin memiliki pusat pengembangan SDM yang mendorong keberfungsian organisasi. Kelahiran Lakpesdam membawa misi memberdayakan NU dari dalam. Gagasannya sederhana namun revolusioner: NU tidak boleh hanya menjadi gerakan moral dan kultural semata, ia harus mampu memperkuat kapasitas kader, mempengaruhi kebijakan, dan hadir sebagai kekuatan gerakan sosial yang kritis.
Perjalanan dari sekadar lajnah pada 1984 pada Muktamar NU di Situbondo menjadi lembaga strategis pasca-Muktamar Cipasung 1994 menandai transisi penting. Namun seperti umumnya lembaga dalam tubuh organisasi besar, Lakpesdam pun tak lepas dari pasang surut, sempat vakum, lalu hidup kembali melalui intervensi PBNU. Justru dalam keterbatasan itu, Lakpesdam belajar bertahan dan bertumbuh, dan Lakpesdam tidak bisa dilepaskan dari sejarah kembali ke Khittah NU 1926.
Baca Juga
Ada Apa di Usia 40 Tahun?
Terpilihnya Gus Dur memimpin PBNU, Khittah NU menemukan gaung terbesarnya pasca Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Dalam momentum bersejarah itu, Nahdlatul Ulama memutuskan kembali kepada akar kelahirannya pada tahun 1926, sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berjarak dari arena politik praktis. Keputusan ini bukan sekadar taktik organisasi, melainkan sebuah refleksi mendalam atas perjalanan panjang NU yang sempat terlibat dalam konstelasi partai politik, mulai dari keterlibatannya Pemilu sempat mendirikan Partai NU hingga fusi membentuk PPP.
Dengan kembali ke Khittah 1926, NU menegaskan posisinya bukan sebagai kendaraan perebutan kekuasaan, melainkan sebagai kekuatan moral yang hadir di tengah masyarakat. Fokus utama NU diarahkan pada dakwah yang mencerahkan, pendidikan yang memanusiakan, gerakan sosial yang membebaskan, serta kebudayaan yang memelihara kearifan lokal. Khittah menjadi penanda bahwa perjuangan NU tidak akan lagi terjebak tarik-menarik politik elektoral, melainkan berdiri sebagai penyeimbang dan pelayan umat yang konsisten.
Dalam semangat itu, NU memperkuat fungsi keulamaan dengan merawat spiritualitas dan etika publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara luas. Keulamaan tidak hanya dilihat dari sisi keilmuan agama semata, tetapi juga dari komitmen memperjuangkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas kebangsaan, dan menghadirkan Islam yang ramah di tengah tantangan zaman. Kembali ke Khittah adalah cara NU menjaga marwah, agar tidak jadi penonton sejarah, tapi justru aktor kultural yang merawat nalar publik tetap kritis, waras dan adil dengan membangun kerjasama ke berbagai pihak baik dalam dan luar negeri.
Dari tiga mandat ke Bappenas NU
Dalam kegiatan Maret 2023, serah terima jabatan kepengurusan periode 2015–2021 ke 2022–2027, Wakil Ketua Umum PBNU, Nusron Wahid, dengan tegas menegaskan tiga mandat besar yang menuntut Lakpesdam tidak hanya berjalan dalam koridor administratif, melainkan bergerak aktif sebagai kekuatan epistemik dan praksis dalam tubuh NU. Mandat pertama adalah panggilan menjadi penggerak masyarakat sipil dan penyusun narasi keislaman kritis. Mandat ini tidak ringan. Ia menuntut keberanian Lakpesdam tetap menyuarakan kebenaran di tengah pusaran kekuasaan, sekaligus menjaga komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan pembebasan umat.
Mandat kedua beranjak ke wilayah pembentukan sumber daya manusia NU secara sistemik dan ideologis, yakni penyelenggaraan kaderisasi. Lakpesdam didorong menyusun model kaderisasi yang tidak hanya terpaku pada formalitas pelatihan semata, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan kapasitas transformatif kader di seluruh jenjang struktur NU. Penggabungan dua model sebelumnya, PKPNU dan MKNU menjadi satu kesatuan kaderisasi berjenjang adalah langkah penting guna menata ulang strategi regenerasi NU. Selain bersifat administratif, kaderisasi menekankan internalisasi nilai-nilai keulamaan, kerakyatan, dan keberpihakan pada yang lemah, sesuai nilai-nilai NU.
Mandat ketiga mempersiapkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Hal ini, menurutnya, belum tersentuh oleh kepengurusan Lakpesdam sebelumnya. Ketika Lakpesdam memikul mandat ini, ia tidak sekadar menjadi “lembaga” yang mengelola program, tetapi juga menjadi guardian of the soul bagi NU dalam merawat keberpihakan, keilmuan, dan integritas gerakan.
Mandat tersebut tidak lahir tiba-tiba dari ruang kosong. Konteks yang kita hadapi sekarang adalah tantangan besar bonus demografi menuju 2045. Laporan Indonesia Vision 2045 oleh Bappenas (2019) menegaskan, periode 2020–2045 adalah fase strategis di mana 70 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Namun, ini adalah potensi sekaligus ancaman. Tanpa pengelolaan SDM yang berkualitas, bonus demografi bisa berubah jadi demographic disaster. Dalam konteks ini, mandat ketiga Lakpesdam sebagai pengembang SDM tidak bisa main-main.
Namun, pertanyaannya: apakah NU sudah siap menjawab tantangan ini?
Pertama, studi CSIS (2021) mengenai Generasi Muda dan Demokrasi menunjukkan bahwa anak muda Indonesia semakin apatis terhadap isu-isu publik dan politik karena lemahnya institusi pendidikan kewargaan yang kontekstual. Ini paralel dengan kritik terhadap NU yang lebih banyak memproduksi kader loyalis, tetapi belum tentu memiliki kapasitas analitis, kepemimpinan visioner, egaliter dengan pemahaman lintas-disiplin yang dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas zaman.
Lakpesdam memiliki tanggung jawab membalikkan tren ini. Penggabungan PKPNU dan MKNU dalam satu desain kaderisasi berjenjang semestinya perlu diperkaya dengan strategi perubahan yang substansial guna melahirkan kader-kader ulul albab yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas, teks dan konteks, fikih dan etika publik.
Kedua, riset LPDP dan Pusat Studi Pendidikan UGM (2022) menunjukkan, hanya 12 persen penerima beasiswa LPDP yang berasal dari pesantren atau latar belakang organisasi Islam tradisional seperti NU. Padahal, jutaan santri setiap tahun lulus dari ribuan pesantren NU. Ini memperlihatkan ketimpangan yang tidak bisa diselesaikan dengan bimbingan belajar sporadis. Dibutuhkan ekosistem regenerasi SDM yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Lakpesdam dapat berperan sebagai penghubung antara pesantren dan sistem meritokrasi nasional dalam beasiswa, pendidikan tinggi, dan mobilitas sosial-ekonomi.
Ketiga, laporan UNDP (2023) menekankan pentingnya inclusive digital transformation dalam mendorong pertumbuhan yang adil. NU sebagai organisasi terbesar memiliki keunggulan jaringan hingga ke desa-desa. Namun, penguatan literasi digital belum menjadi bagian integral dari program kaderisasi atau pemberdayaan. Lakpesdam bisa membangun pusat inovasi desa berbasis pesantren, mendorong santri dan pemuda NU memecahkan masalah lokal dengan pendekatan sosio-digital.
Keempat, di banyak organisasi besar, termasuk dalam struktur NU, tantangan regenerasi seringkali terkendala oleh apa yang disebut Francis Fukuyama (2014) dalam Political Order and Political Decay sebagai institutional rigidity, yakni kecenderungan lembaga mempertahankan cara lama dan menolak inovasi yang disruptif. Dalam konteks ini, Lakpesdam harus berani menjadi “pengganggu positif” (positive disruptor) dengan menyalakan kembali semangat “menghidupkan Gus Dur”: keberanian berpikir dan bertindak di luar pakem untuk kebaikan yang lebih luas.
Sudah sejauh mana respons atas tantangan menyongsong generasi emas tersebut?
Medio Desember 2023 lalu, dalam sejumlah pidatonya, keputusan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Lakpesdam NU didasarkan pada visi strategis mentransformasi lembaga ini menjadi semacam “Bappenas”-nya NU, yakni badan perencana pembangunan jangka panjang organisasi. Dipertegas pandangan Sekjen PBNU, Gus Saifullah Yusuf, Lakpesdam tidak cukup hanya menjadi pusat kajian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, tetapi harus berevolusi sebagai lembaga teknokratis merumuskan arah pembangunan NU secara sistematis dan terukur. Untuk mewujudkan visi besar ini, dibutuhkan sosok yang tidak hanya paham struktur organisasi, tetapi juga memiliki pengalaman membangun sistem dan tata kelola kelembagaan yang kompleks. Pengalaman Erick Thohir sebagai pengusaha sukses, pengelola korporasi besar, dan pejabat publik di sektor BUMN dianggap sebagai bekal penting mengembangkan kapasitas teknokrasi dalam tubuh NU yang selama ini lebih dikenal berbasis pada kesukarelaan dan kultural pesantren.
Gus Yahya menyadari bahwa perubahan ini bukanlah sekadar penyesuaian struktural, melainkan upaya menyatukan dua dunia yang selama ini tampak berjauhan: nilai-nilai keikhlasan khas Nahdliyin dengan prinsip-prinsip tata kelola modern. Oleh karena itu, pengangkatan Erick Thohir diharapkan bisa menjadi jembatan antara idealisme kaum sarungan dan profesionalisme berorganisasi, antara merawat tradisi dan mendorong inovasi. Keberanian Gus Yahya mengambil langkah ini menandai sebuah tekad besar membawa NU memasuki fase baru: dari ormas keagamaan berbasis komunitas, menuju entitas keagamaan yang juga tangguh dalam perencanaan, pembangunan sosial, dan manajemen kelembagaan di era kontemporer. Apalagi NU sudah memasuki abad kedua. Transformasi ini, jika berhasil, tidak hanya akan mengangkat citra NU secara nasional, tetapi juga memperluas daya pengaruhnya dalam pembangunan bangsa.
Tentu semua harapan ini akan diuji sejarah. Sejauh mana langkah tersebut bisa direalisasikan? Apakah Erick bersungguh-sungguh atas penugasan yang diberikan?
Transformasi tugas kenabian
Pada titik ini, Lakpesdam tidak bisa hanya menjadi lembaga pengkajian, apalagi sekadar pelengkap struktur jam’iyyah. Ia harus menjadi pusat gravitasi perubahan di tubuh NU. Misinya kini lebih mirip dengan apa yang disebut Gus Dur sebagai “tugas kenabian”, yakni mampu membebaskan, mencerahkan, dan menumbuhkan harapan dalam lanskap sosial yang semakin kompleks dan tak pasti.
Transformasi Lakpesdam bukan sekadar soal konsolidasi kelembagaan atau penyusunan program kerja rutin, merumuskan renstra dan melegitimasi kebijakan, melainkan terus melakukan terobosan membangun paradigma yang mencerminkan keadilan. Pun harus memiliki sensitivitas pada sumber daya manusia di wilayah terpencil dan tertinggal serta dapat meletakkan timur Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan. Ini soal menghidupkan kembali semangat pembaruan dalam NU, sebagaimana yang dicontohkan Gus Dur, yang tak ragu bersikap kritis bahkan terhadap arus utama di internal NU jika benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai dasar.
Menginjak usia 40, Lakpesdam sedang memulai babak baru, tapi saat bersamaan berada dalam titik balik menetapkan arah lebih dalam dan melampaui kebiasaan. Ibarat manusia yang telah mencapai usia profetik, Lakpesdam harus berani meninggalkan zona nyaman dan menetapkan pijakan baru yang lebih strategis. Ia harus jadi think tank yang bukan hanya berpikir, tetapi juga menggerakkan dan menanamkan nilai.
Dengan ketiga mandat yang digariskan menuju teknokrasi ala Bappenas NU, tantangannya bukan lagi bagaimana sekadar berjalan, tetapi bagaimana berlari, menciptakan lompatan dengan arah yang tepat dan penuh kesadaran. Lakpesdam harus jadi pengarah kompas moral NU, penjaga nalar kritis, dan penggugah kesadaran kolektif agar NU tetap relevan, progresif, dan berpihak kepada mereka yang mengalami marjinalisasi.
Jika nabi diangkat sebagai rasul dan diutus pada usia 40, maka Lakpesdam hari ini sedang dipanggil menghidupkan kembali misi kenabian dalam wajah institusional: membebaskan umat dari keterkungkungan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan, sembari tetap teguh pada nilai-nilai Aswaja dan tradisi kebudayaan Nusantara yang menjadi aset utama kekuatannya.
Karena dalam dunia yang terus berubah, hanya dengan kekuatan nilai, dan visi yang jelas sesuatu akan mampu bertahan dan memimpin arah peradaban. Tapi perlu diingat, al-Qurtubi dan Ibn Hajar, menjelaskan pula, 40 tahun adalah usia sempurna kenabian sekaligus datangnya ujian terbesar. Usia 40 tahun juga bisa jadi penanda datangnya rupa-rupa penyakit yang diam-diam mampu melumpuhkan organ-organ vital.
Abi S Nugroho, Anggota Pengurus Lakpesdam PBNU
Terpopuler
1
Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi
2
Haul Ke-44 KH Abdul Hamid Pasuruan, Ini Rangkaian Acaranya
3
Gusdurian Desak Kapolri Mundur usai Marak Kekerasan Aparat
4
Prabowo Batalkan Kunjungan ke Tiongkok, Pilih Fokus Tangani Situasi Dalam Negeri
5
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat
6
Prabowo Instruksikan TNI-Polri Tak Ragu Ambil Langkah Tegas saat Hadapi Kerusuhan
Terkini
Lihat Semua