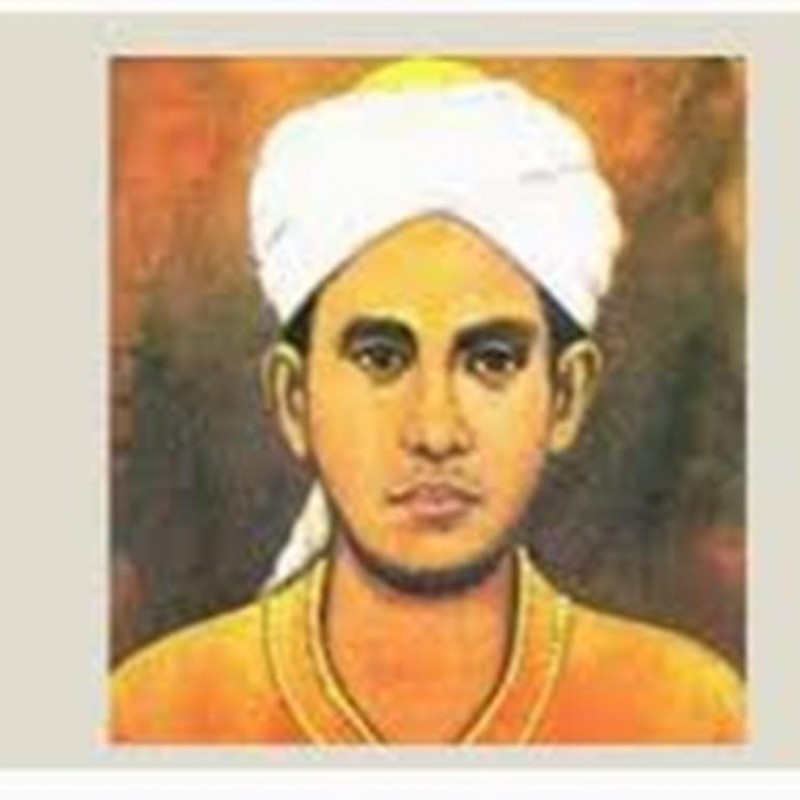Jakarta, NU Online
Old but Gold. Older but Better. (Tua tetapi Emas. Semakin Tua tetapi Semakin Baik). Istilah itu tepat untuk menggambarkan kontribusi pesantren untuk Indonesia, dan bahkan dunia. Sebagai institusi pendidikan tertua di republik ini, pesantren tidak pernah lelah memberikan kemaslahatan untuk umat manusia. Semakin tua, semakin giat berkarya.
Di tengah perkembangan dunia yang semakin bergerak maju, peran pesantren tidak pernah luntur, dan semakin menguat untuk terus menebar manfaat. Pesantren bergerak Bersama zaman. Bagi para alumni pesantren yang berkarir di berbagai profesi, ilmu pesantren adalah fondasi yang membentuk kepribadian dan kemampuan mereka dalam menjalani zaman.
Materi inilah yang dibahas dalam sebuah diskusi online bertajuk SantriTalk: Manfaat Ilmu Pesantren dalam Dunia Jurnalistik dan Diplomasi yang digelar oleh Initiative of Change Indonesia dan Qultura Institute, Rabu (29/4).
Ismail Fahmi, seorang santri yang juga seorang diplomat dan pernah bekerja sebagai jurnalis menyebut bahwa fondasi dasar tentang jurnalistik dan diplomasi justru didapatkannya dari dunia pesantren.
“Meski saya tidak tahu manfaat langsung ilmu yang saya pelajari ketika di pesantren, keilmuan itu justru bermanfaat ketika saya menjalani karir sebagai jurnalis dan diplomat," katanya.
Di pesantren, lanjutnya, kemampuan komunikasi publik diasah melalui Muhadloroh. Sementara kemampuan berdiplomasi diasah melalui ilmu-ilmu dasar lainnya semisal ilmu balaghoh dan ilmu mantiq.
Fahmi juga menyebut bahwa keluwesan dalam berdiplomasi juga dipengaruhi karaktek dasar santri yang luwes dan mudah bergaul dengan banyak pihak. Figur karismatik seorang kiai juga berperan besar dalam membentuk karakter santri yang adaptif dan menghargai orang-orang dengan latar belakang berbeda, sesuatu hal yang memang dihadapi sehari-hari dalam dunia diplomasi.
Selain itu, menurutnya, pesantren juga mempunyai tradisi yang kuat dalam melacak kebenaran sebuah sumber informasi, sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang jurnalis, diplomat dan bahkan akademisi.
Dalam tradisi menulis di Barat, penghargaan atas karya tulis orang lain diwujudkan dengan prosedur dan mekanisme dalam mengutip sebuah pendapat. Kesalahan dalam teknis mengutip bisa berujung dalam plagiasi, sebuah aib bagi seorang penulis.
Hal-hal seperti ini sebenarnya diajarkan di pesantren. Dalam kajian penelusuran sumber-sumber hadits, para santri diajarkan untuk melacak kebenaran sebuah hadis dengan mencari tahu siapa yang meriwayatkannya (perawi), sanadnya seperti apa, dan bahkan pada satu titik, ketika ingin mengutip seseorang, level kejujuran seseorang tersebut diteliti.
Dalam kajian barat, penelusuran rigid ala tradisi islam klasik tersebut tidak terjadi. Penelurusan tidak dilakukan sampai ke kepribadian sumber informasi dan referensi gaya barat lebih bersifat fungsional.
Modal Santri: Percaya Diri dan Tidak Kagetan
Dalam kesempatan yang sama, Cahya Yunizar, seorang santri asal Malang yang sedang menempuh pendidikan doktoral di University of Minnesota, USA, juga menuturkan hal yang sama. Ia sependapat bahwa keilmuan dan pengalaman hidup yang didapatkan di pesantren berpengaruh dalam pendidikan yang sedang dijalani.
Sebagai seorang Muslimah yang tinggal di sebuah negara liberal, pengalaman hidup sebagai santri dan seorang Muslimah di Indonesia berperan besar dalam proses adaptasi yang dijalaninya.
Cahya menyebut dua hal penting yang harus dipahami dalam menjalani peran sebagai mahasiswa muslim Indonesia di Amerika, yakni percaya diri dan tidak kagetan. Dalam tradisi negara liberal, penghargaan terhadap pendapat adalah nilai dasar yang dipercayai oleh orang-orang Amerika. Kepercayaan diri membantunya untuk mengungkapkan pendapat dan memberikan argumen, terlepas dari perbedaan pendapat yang ada.
“Kita boleh tidak setuju dengan sebuah teori atau pandangan, tapi ketika kita pede (percaya diri) dengan apa yang kita sampaikan, mereka akan menghargai dan mendengarkan dengan lebih baik," ungkapnya.
Sementara itu, tidak kagetan berarti bersikap bijaksana dengan perbedaan kultur yang ada. Kita boleh tidak setuju, tapi tidak boleh kagetan. Kita menerima pandangan tersebut sebagai pandangan dari seseorang dengan latar belakang kultur yang berbeda, perspektif mereka, kemudian kita renungkan. Kita menerima ilmu yang baru, kita serap, kita maknai dan tidak reaktif.
Cahya menyebut sikap tidak kagetan itu adalah ciri khas keilmuan di pesantren. Sejak dini lanjutnya, pesantren mengajarkan pandangan-pandangan keilmuan yang berbeda, dan dibahas bersama untuk memperkaya khazanah keilmuan. Dalam tradisi pesantren, Bahtsul Masail berperan besar dalam membentuk santri yang percaya diri dan tidak kagetan tersebut.
Penguatan Literasi di Pesantren
Dalam pengalamannya sebagai santri, Ismail Fahmi, alumnus Ash Shiddiqiyah Jakarta menyebut penguatan literasi di pesantren harus tetap dijaga dan bahkan diperkuat.
“Saya ingat, dulu setiap pagi saya membaca koran yang dipajang di tempat-tempat strategis. Itu membantu saya untuk memahami apa yang terjadi di luar sana. Perpustakaan yang nyaman juga menjadi tempat yang asik untuk membaca literatur yang tidak saya dapatkan di pesantren," katanya.
Fahmi menyebut bahwa pesantren harus memastikan bahwa santri memiliki akses yang besar dan lebar terhadap informasi. Di saat yang sama, santri harus dibekali oleh kemampuan literasi yang kuat. Literasi bukan hanya kemampuan untuk membaca, tapi kebijaksanaan dalam menggunakannya.
Jika sebuah informasi itu diibaratkan sebuah pisau, kita harus memastikan orang tersebut mampu menggunakan pisau dengan tepat. Literasi itu adalah kemampuan dan kebijaksanaan untuk menggunakan informasi tersebut.
Penguatan literasi juga bisa dilakukan dengan cara memperluas pergaulan dengan komunitas, kelompok dan masyarakat yang berbeda. Hal ini penting dilakukan untuk memperkaya perspektif sekaligus memahami sesuatu dari sudut padang orang lain dan membantu orang lain paham atas perspektif yang dimiliki oleh kita, para santri.
Santi harus mampu melihat sesuatu dari sudut 360 derajat, dan masuk ke komunitas lain membantu untuk memperkuat kemampuan literasi tersebut.
Santri sebagai Pembawa Pesan Damai
Dalam percaturan global, santri bisa berperan sebagai ‘diplomat’ pembawa pesan damai (peace messenger). Semua itu bisa dilakukan jika santri bisa memperkuat penguasaan atas ilmu-ilmu dasar yang diajarkan di pesantren seperti balaghah, mantiq, nahwu, sorof, dan ushul fiqh. Kemampuan-kemampuan dasar itu menjadi fondasi dalam menjalankan peran di masa depan, terlepas dari pilihan profesi yang dipilih.
Para santri harus terus memperkuat kemampuan dasar bidang-bidang keilmuan tersebut sekaligus kemampuan literasi yang memadai. Di tengah arus informasi yang cepat, fondasi keilmuan yang kokoh dan kemampuan literasi yang mumpuni akan membantu para santri, calon pemimpin masa depan, untuk memahami sebuah teks sebagai sebuah produk budaya. Tidak hanya terpaku pada teks yang disampaikan. Pada akhirnya, para santri akan terus memainkan peran penting dalam masyarakat dan menjadi penyebar pesan perdamaian.
Kontributor: Wendi Wijarwadi
Editor: Muhammad Faizin