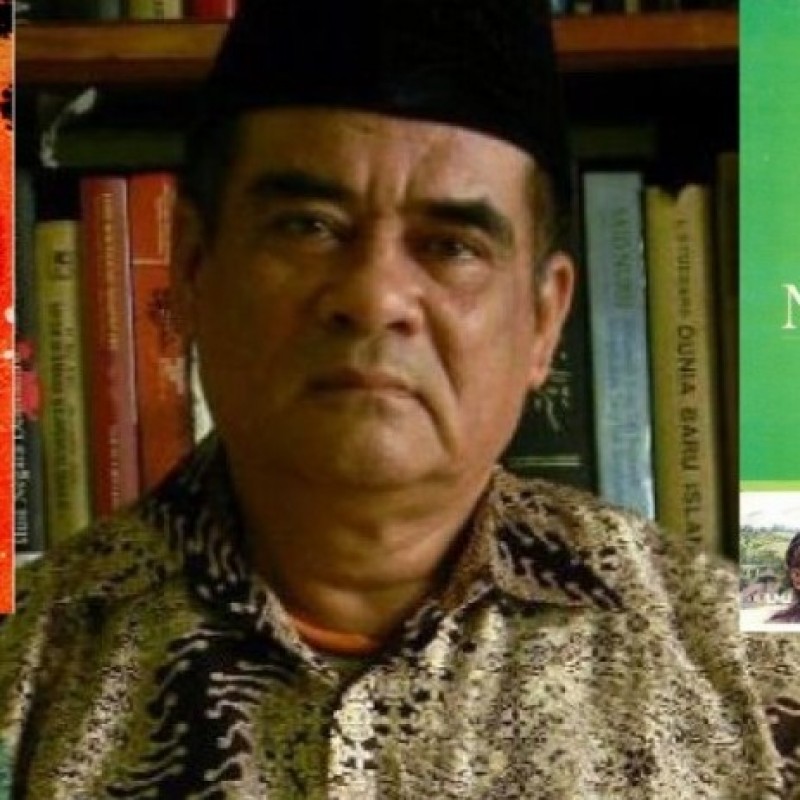Ada juga yang memahami Tuhan kemudian ia menjadi pembela Tuhan, seakan-akan eksistensi Tuhan terancam. (Ilustrasi: NU Online)
Aswab Mahasin
Kolomnis
“Untung Tuhan tak Pernah Bingung.” Itulah salah satu judul yang saya baca dalam buku Surat Kepada Kanjeng Nabi karya Emha Ainun Nadjib. Kalau boleh berandai-andai dan membayangkan, bagaimana dunia ini ketika Tuhannya bingung? Silakan Anda pikirkan, tapi jangan terlalu lama karena “Tuhan tak pernah bingung.”
Saya khawatir Anda yang jadi bingung. Pikiran Anda hanya sejengkal jari yang biasa mengukur kedalaman air di gelas, tak akan pernah mampu mengukur kedalaman air di laut. Begitulah kata Taufiq el-Hakim seorang sastrawan besar dari Mesir.
Dari dulu hingga sekarang, fitrah manusia itu bertuhan. Hanya saja pemaknaan dan ekspresi keyakinan seseorang terhadap Tuhan tidak sama. Ada yang memandang Tuhan kemudian dia baik, menebarkan kasih sayang, persahabatan, dan cinta damai.
Namun, ada juga yang memahami Tuhan kemudian ia menjadi pembela Tuhan, seakan-akan eksistensi Tuhan terancam. Ada juga yang memahami Tuhan lantas dia tidak percaya, serta ada juga yang memahami Tuhan ketika kepepet alias punya masalah, yang pasti banyak jenis prasangka.
Dalam wacana pemikiran yang lebih luas, persepsi tentang Tuhan terdapat perbedaan, antara masyarakat modern dan tradisional. Pemikir tradisional mengatakan bahwa Tuhan adalah dasar atau asas dari segala-galanya dan manusia adalah tafsiran Tuhan.
Tapi pemikir modern menyatakan, manusia adalah dasar dari realitas dunia dan Tuhan merupakan tafsiran pemikiran manusia. Pemikir modern ini diwakili oleh Karl Marx menafsirkan Tuhan pada suatu pengertian tertentu, Nietszche menafsirkan Tuhan dalam pengertian lain. Begitu pula Sigmund Freud dan Immanuel Kant.
Selain itu, bila menengok lebih jauh lagi, awal mulanya (zaman primitif), dahulu sekali, bagi manusia, Tuhan atau dewa-dewa itu tidak tunggal, polytheisme, kemudian Tuhan atau dewa-dewa itu diseleksi, ada Tuhan/dewa-dewa tingkat “kota dan desa”, kemudian bergeser ke era monotheisme, Tuhan itu satu.
Era monotheisme Tuhan merupakan kepastian absolut (kebenaran mutlak). Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ajaran Tuhan jelas termaktub dalam kitab suci sebagai pegangan hidup manusia (Al-Qur’an). Islam mengajarkan setiap manusia harus meneladani seluruh seruan kebaikan yang diajarkan Allah.
Allah mengajarkan kasih sayang terhadap sesama, Allah selalu mengingatkan manusia pada kebaikan, kerukunan, dan Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia sebagai pembawa berita kebaikan untuk disebarkan ke seluruh umat manusia.
Dalam konsep ketuhanan, Allah adalah satu-satunya yang merancang dan merencanakan kelahiran manusia dan alamnya melalui suatu “tipe induk” atau a’yan thabita dalam istilah Ibn ‘Arabi. Allah juga yang memberikan informasi kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk, dan Allah yang berhak menghakimi manusia, apakah orang itu masuk surga atau neraka.
Nah, di tengah masyarakat kita yang “baperan” seperti sekarang, persepsi kita tentang kebenaran tidak lagi berpuncak pada Keagungan Allah. Melainkan hanya egoisme yang dikedepankan. Padahal, ajaran langit itu objektif, seharusnya, ekspresi keberagamaan kita dalam berketuhanan harus menambah nilai, supaya ada perbaikan terus menurus terhadap diri kita.
Ajaran langit yang objektif harus dimaknai objektif pula pada realitas bumi. Kebenaran tentang kasih sayang, persahabatan, penerimaan perbedaan pendapat, dan seruan kebaikan itu objektif, ukurannya adalah rasa, rasa kita dalam menerjemahkan ajaran-ajaran Allah.
Kesalahan kita hari ini adalah kita belum memahami secara tuntas arti kebenaran rahman dan rahim-Nya Allah, yang kita miliki hanya “anggapan” kebenaran. Ini yang menjerumuskan kita mudah menghakimi orang lain, kita mudah menyalahkan. Kalau kata Gus Mus, “dikiranya ketika kita melakukan sesuatu, Allah menyetujui atas apa yang kita lakukan. Ketika kita maki-maki, dikiranya Allah sepakat”.
Jadi, kalau dalam memahami Tuhan tidak menjadikan Anda baik, malah tambah galak, artinya ada yang keliru pemahaman Anda tentang Tuhan. Kemarin pada saat ribut-ribut jilbab/hijab tidak wajib bagi wanita muslim, pernyataan yang dikeluarkan Ibu Sinta Nuriyah, banyak yang marah-marah, sampai bacanya tidak tega.
Mereka tidak membantah secara ilmiah, tetapi maki-maki. Seharusnya ketika tidak sepakat dengan suatu pendapat, menghalaunya dengan cara santun. Melihat peristiwa itu, akhirnya, saya mengamini judul buku Pak Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak.
Masyarakat yang baperan itu sebagai bukti dari hilangnya akhlak. Karena ukuran akhlaknya bersifat lokal. Ia berakhlak ketika dengan kelompoknya saja, di luar itu akhlak tidak penting. Padahal dasar dari manusia, pondasi utamanya adalah sikap baik. Sebenarnya ini fenomena apa?
Bila kita kaji lebih dalam, rentetan peristiwa demikian adalah munculnya budaya instan dalam pembelajaran agama. Mempunyai semangat beragama tinggi, tapi kering dalam pengetahuan. Seharusnya para pembelajar agama pemula (golongan hijrah) ada hal yang harus dipahami lebih dulu. Agama itu menyerukan kebaikan dan mencegah kejahatan sebagai pintu masuk mengenal Tuhan. Tidak bisa tidak, hanya agama yang mengetahui jalan pulang kepada Tuhan.
Agama sebagai Firman Tuhan mutlak, ia berada pada wilayah Ketuhanan. Tapi agama sebagai ajaran langit yang masuk pada realitas bumi disampaikan dengan bahasa manusia, kemudian mengakar dan menyejarah dalam aktivitas kehidupan manusia hingga saat ini dengan berbagai dinamika dan pasang-surutnya, yang biasa disebut dengan cara beragama. Dalam sejarahnya, tidak sedikit terjadi perselingkuhan antara agama (orang-orang yang memanfaatkan agama) dengan politik. Apakah hal tersebut masih murni sebagai ajaran langit yang mutlak?
Ada wilayah realitas dalam agama ketika gaya beragama dihadapkan pada pemahaman individualitas dan komunitas. Dalam hal ini, ekspresi keberagamaan tidak lagi bersifat langit, namun tersandera kepentingan. Agama lebih kepada tarik-ulur tafsiran selera yang memanfaatkannya. Seperti akhir-akhir ini yang sering kita lihat, boleh mengucapkan selamat natal bagi pejabat tertentu karena kewajiban, tapi bagi pejabat lainnya haram.
Dalam kaitan ini, agama sering dimanfaatkan secara berlebihan (khsususnya dalam politik dan kepentingan lainnya) untuk mempengaruhi umat dalam membangkitkan semangat dan kekuatan kepentingan dengan menempatkan ajaran agama sebagai topeng belaka.
Perlu digarisbawahi, ini tidak semua, hanya oknum yang ingin memanfaatkan. Namun efeknya, nampak semangat agama yang tinggi akhirnya mempengaruhi opini umat bahwa model keberagamaan yang benar adalah seperti itu, karena galak dan penuh simbol agamis.
Kemudian faktor baper itu muncul juga karena terlahirnya otoritas-otoritas baru, fenomena ini membuat umat bingung. Kita disuguhi banyak sekali varian model ustaz, dan pendakwah—sehingga umat menjadi terkotak-kotak. Apalagi mereka yang baru belajar agama, lalu masuk dalam lingkungan tertentu yang instan dalam proses belajar, tanpa alur pemahaman utuh. Akhirnya, pilihan pembelajaran terpaku pada selera semata. Sayangnya, selera itu terbentuk melalui opini pasar yang sedang berkembang. Dan pasar dakwah yang berkembang saat ini menjunjung tinggi baper.
Pasar beragama, menurut saya, bukan lagi dibentuk oleh substansi cara beragama yang baik (dari segi belajar maupun ekspresi). Melalui framing-framing media yang saling terhubung, seperti medsos, youtube, whatsapp, dan sejenisnya. Sehingga instrumen pasar itu yang membentuk pola beragama seseorang. Tidak hanya orang belajar agama saja yang terjebak opini pasar, tetapi para ustaz dan pendakwah ikut terjebak mengikuti instrumen pasar.
Bisa kita tengok, gaya-gaya ustaz karbitan terkenal itu, memiliki cara, ekspresi, dan penyampaian dakwah hampir sama. Karena pasar sedang menghendaki demikian. Susahnya, dalam potret yang lebih luas, muncul kesan, seakan-akan model begitulah yang benar. Akhirnya, orang terjebak pada satu arus tertentu dan mencoba menutup arus lainnya (akhirnya jadi baperan lagi).
Selanjutnya, narasi-narasi romantisme; ada kelompok tertentu yang mencoba merongrong kesatuan umat melalui impian Negara Islam. Tidak ada yang salah jika kita sekadar flashback menambah motivasi pembelajaran. Tapi, ketika memaksakan sebuah negara harus mengganti sistem khilafah, maka di sinilah letak salah kaprahnya.
Menyebabkan kesatuan umat tidak terwujud. Karena kesatuan umat dalam lingkaran universal tidak hanya dipahami sebagai kesatuan kelompok iman semata, melainkan kesatuan kerja tim (team work) lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis. Efek dari ini, jadi baperan lagi.
Dengan demikian, orang-orang baperan sebaiknya bergeser ke arah pemahaman utuh, bila perlu mondok dulu. Keluar dari pondok dijamin tidak baperan, tapi pondok yang afiliasinya ke Nahdlatul Ulama. Karena kita diajarkan banyak hal, kemandirian, kebersamaan, gojlokan, pembelajaran literatur Islam yang ketat, dan sebagainya.
Tidak hanya mantengin youtube, medsos, dan cari-cari orang kepleset lidah saja, karena tidak menyelesaikan kadar baperan Anda. Ingat, walaupun Tuhan ada di segala penjuru, jangan hanya menyapa-Nya via internet saja, karena Tuhan dan agama tidak keluar dari internet belaka.
Meminjam istilahnya Nawal El Saadawi, “Tuhan tidak keluar dari percetakan.” Artinya, kita tidak boleh berhenti belajar, banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita pahami, di manapun dan dari manapun, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mencerna fenomena yang terjadi di dunia ini dengan baik dan bijaksana tanpa baper. Wallahu a’lam bisshawab
Aswab Mahasin, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen, Jawa Tengah; pembaca setia NU Online
Terpopuler
1
Koordinator Aksi Demo ODOL Diringkus ke Polda Metro Jaya
2
Khutbah Jumat: Meraih Keutamaan Bulan Muharram
3
5 Fadilah Puasa Sunnah Muharram, Khusus Asyura Jadi Pelebur Dosa
4
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
5
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
6
5 Doa Pilihan untuk Hari Asyura 10 Muharram, Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
Terkini
Lihat Semua