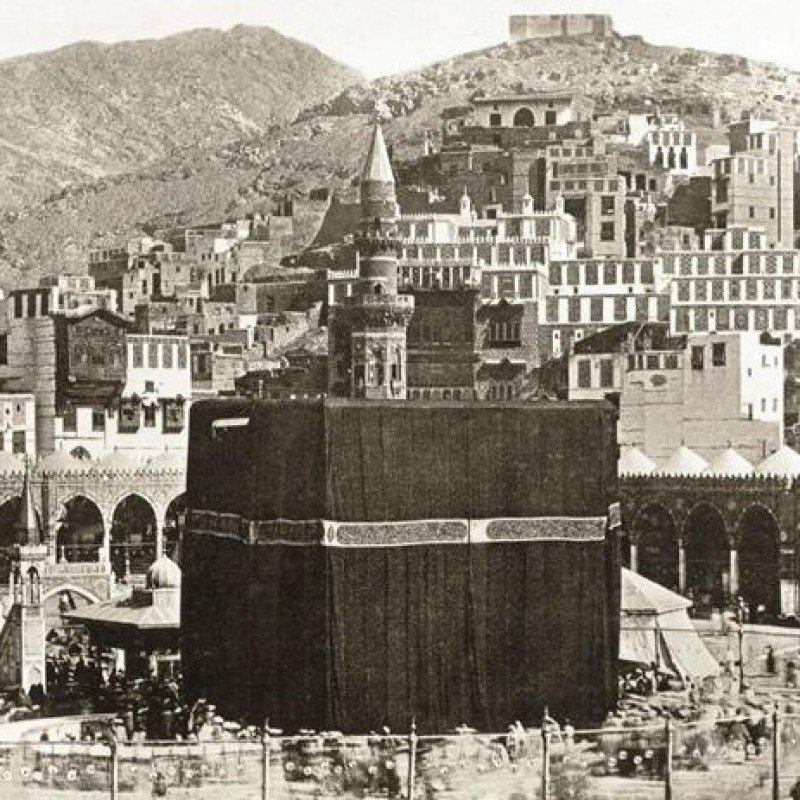Ushul Fiqih: Tidak Semua Sunnah Nabi Dimaksudkan Tasyri'
NU Online · Ahad, 1 Agustus 2021 | 13:00 WIB
Masih banyak orang memahami apapun yang muncul dari Nabi harus diikuti, sehingga sedikit-sedikit mereka mengatakan, “Kalau tidak memakai jubah atau tidak jenggotan berarti tidak nyunnah”. Bagaimana ushul fiqih menjawab fenomena ini?
Sunnah dalam terminologi ushul fiqih adalah segala ucapan, perbuatan, dan pengakuan (taqrîr) yang muncul dari Nabi saw. Namun tidak semua hal yang muncul dari Nabi dimaksudkan untuk tasyrî’ (pensyariatan hukum untuk diikuti). Hal tersebut hanya bisa menjadi hujah yang wajib diikuti apabila muncul dari Nabi saw dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Itu karena Nabi saw adalah manusia biasa sama seperti manusia yang lain. Hanya saja ia dipilih oleh Allah sebagai Rasul yang diutus kepada umat manusia dan mendapatkan wahyu dari-Nya. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ
Artinya, “Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu.” (QS Al-Kahfi: 110).
Dalam kitab 'Ilmu Ushûlil Fiqh karya Abdil Wahhâb Khallâf dijelaskan, ada tiga kondisi di mana sunnah Nabi saw tidak dimaksudkan tasyrî’, sehingga tidak menjadi hujah dan tidak ada kewajiban mengikutinya.
Kondisi pertama, sesuatu yang muncul dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa (tabiat manusiawi). Semisal berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, dan cara berpakaian. Semua ini bukan bagian dari risalah atau misi kerasulannya, akan tetapi muncul dari tabiat atau sifat kemanusiaannya sebagai manusia biasa.
Menurut mayoritas ulama, sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, Ushûl Fiqh al-Islâmi, kita sebagai umatnya tidak memiiki kewajiban mengikuti Nabi saw dalam jenis sunnah yang pertama ini. Sebagian ulama ada yang menganjurkan mengikutinya. Abdullah bin Umar ra adalah salah seorang sahabat yang bertekad kuat mengikuti segala hal yang muncul dari Nabi, termasuk dalam perbuatan tabiat manusiawinya. (Wahbah az-Zuhaili, Ushûl Fiqh al-Islâmi, [Damaskus, Dârul Fikr: 1406 H/1986 H], cetakan pertama, juz I, halaman 478).
Sekiranya kita ingin mengikuti Nabi saw dalam jenis pertama ini, tentu itu adalah hal baik. Abdullah bin Umar ra telah mencontohkannya. Tapi jangan sekali-kali Anda mencerca orang-orang yang tidak mengikuti Nabi dalam sunnah macam pertama ini apalagi sampai mengatakannya: “Tidak nyunnah”. Ini masalah khilâfiyah. Tidak perlu ada caci maki hanya karena berbeda dalam mengambil pendapat.
Kondisi kedua, sesuatu yang muncul dari Nabi saw dari sisi keahlian manusiawi, kecerdasan, dan pengalamannya dalam persoalan-persoalan dunia. Semisal berdagang, bercocok tanam, mengatur pasukan dan strategi perang, membuat resep obat untuk suatu penyakit. Itu semua bukan bagian dari risalah atau misi kerasulannya, melainkan muncul dari keahlian Nabi saw dalam persoalan dunia dan kemampuan individualnya sehingga bukan bagian dari tasyrî’. (Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushûlil Fiqh, [Maktabatul Da’wah al-Islâmiyyah], cetakan ke-8, halaman 43-44).
Sebagai contoh, salah satu riwayat pada saat perang badar, Nabi saw berpendapat untuk menempatkan pasukan di suatu tempat tertentu.
Salah seorang sahabat bertanya, “Apakah ini adalah tempat yang diwahyukan Allah kepadamu atau ini adalah pendapat dan strategi perangmu?”
“Itu adalah pendapat dan strategi perangku.” jawab Nabi saw.
“Kalau begitu, ini bukanlah tempat yang strategis”, kata sahabat tersebut.
Nabi saw kemudian menyetujui usulan sahabat tersebut dan mengisyaratkan untuk menempatkan pasukan sesuai usulannya.
Contoh lain adalah ketika melihat penduduk Madinah mengawinkan kurma, Nabi saw menyarankan agar tidak mengawinkannya. Mereka pun mengikuti usul Nabi saw untuk tidak mengawinkan kurmanya. Beberapa waktu kemudian, buah kurma mereka tidak berbuah lebat sebagaimana sebelumnya. Lalu Nabi saw bersabda, “Kawinkanlah (kurma-kurma itu), kalian lebih mengetahui persoalan-persoalan dunia kalian.”
Kondisi ketiga, sesuatu yang muncul dari Nabi saw dan terdapat dalil yang menunjukkan hal itu berlaku khususnya, tidak untuk umatnya. Semisal Nabi saw menikah lebih dari empat istri, padahal nash menyatakan bahwa batas maksimal menikah adalah empat istri. Allah berfirman:
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... (النساء: 3)
Artinya, “Maka nikahilah perempuan yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat …” (QS an-Nisa’: 3).
Contoh lain adalah tindakan Nabi saw mencukupkan kesaksian satu orang saksi, yaitu Khuzaimah bin Tsabit al-Anshari dalam menetapkan gugatan, padahal nash secara tegas menyatakan bahwa di dalam memutuskan gugatan harus mendatangkan dua saksi. Allah berfirman:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ (الطلاق: 2)
Artinya, “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (QS At-Thalaq: 02).
Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang muncul dari Nabi saw, baik perkataan atau perbuatan, dalam tiga situasi di atas adalah termasuk sunnah Nabi saw, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk tasyrî’ yang wajib diikuti. Selain dari itu, maka kita wajib mengikuti dan meneladani Nabi saw.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب: 21)
Artinya, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik.” (QS al-Ahzab: 21). Wallâhu a’lam.
Hamim Maftuh Emy, Mahasantri Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo.
Terpopuler
1
Inilah Niat Puasa Asyura Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
2
10 Muharram Waktu Terjadinya 7 Peristiwa Penting Para Nabi
3
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
4
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
5
Doa-Doa Pilihan di Hari Asyura, Dapat Hindarkan dari Matinya Hati
6
Khutbah Jumat: Keistimewaan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua
Terkini
Lihat Semua