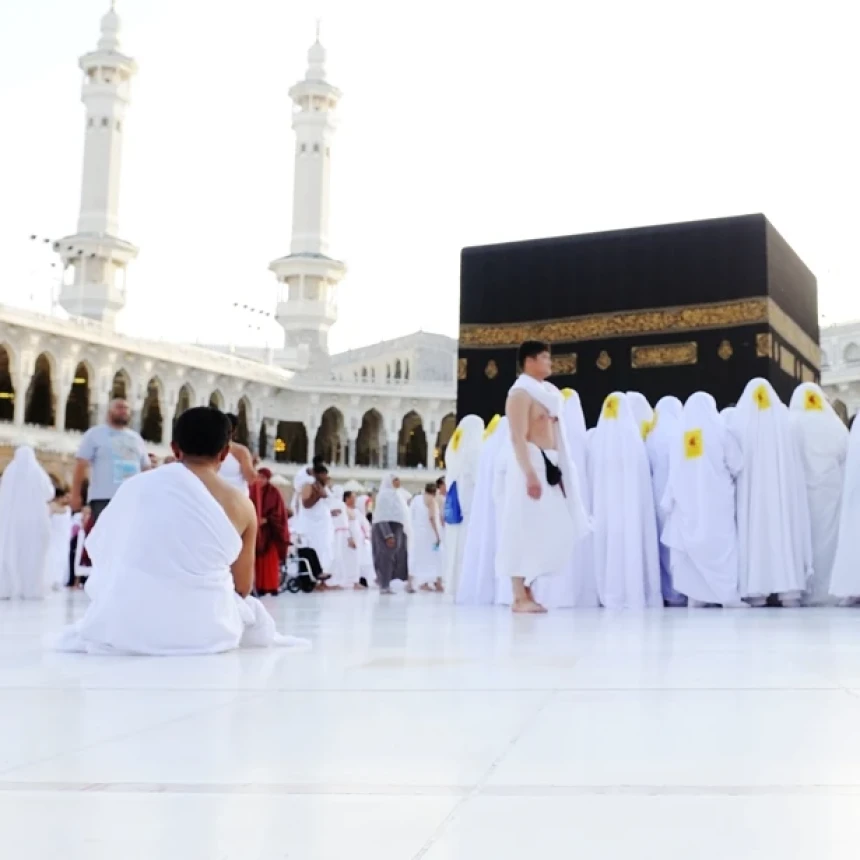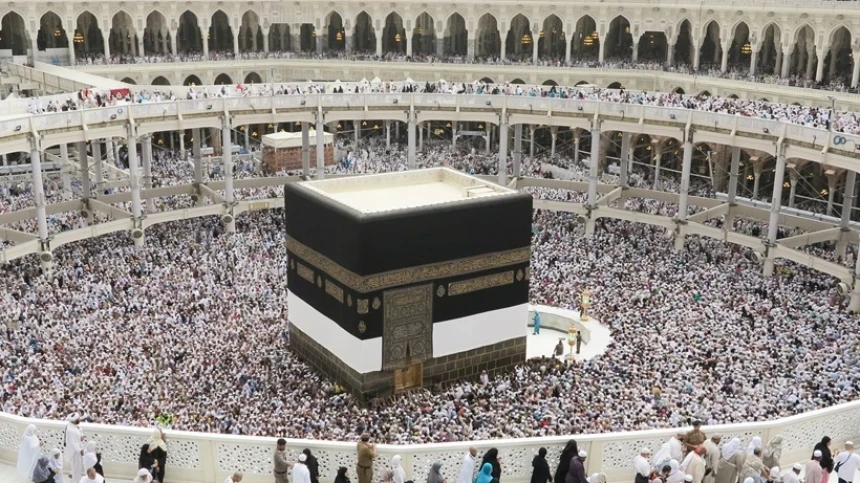Pentingnya Kamp Pengungsian Bencana yang Aman dari Disorientasi Seksual
Jum, 24 Januari 2020 | 05:30 WIB
Muhammad Syamsudin
Kolomnis
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah kira-kira pepatah yang menggambarkan situasi yang melanda para korban bencana. Duka lama belum usai sudah datang sumber duka yang baru. Akibat selama beberapa hari wilayah terkena bencana, para korban terpaksa berkumpul di satu tempat, bercampur menjadi satu dengan pengungsi yang lain.
Sebagai konsekuensi berkumpul dalam satu tempat, dalam kondisi ruang berkomunikasi satu sama lain tak terbatasi, mengakibatkan timbulnya niat jahat dari sesama korban bencana.
Sebuah fakta di Palu menunjukkan hal itu. Demikian sebagaimana dicatat oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Setelah tsunami datang menerjang, satu orang anak SD diperkosa tiga orang pemuda di lokasi pengungsian. Menurut laporan BBC, di Kabupaten Donggala, tercatat lebih dari 20 kasus kekerasan dan pelecehan seksual oleh pelaku korban bencana, 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tenda pengungsian, 42 kekerasan berbasis gender. Bahkan, situs Tirto melaporkan setidaknya 57 kasus kekerasan seksual terjadi di lokasi bencana Palu berdasarkan laporan Koordinator Nasional Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Darurat Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), Ita Fatia Nadia.
Adapun tempat yang acap dijadikan lokasi kekerasan dan pelecehan seksual oleh korban bencana adalah lokasi tempat mandi, cuci, kakus, area gelap dan terisolasi, kamp dan tenda-tenda pengungsian. Setidaknya, berbekal sejumlah catatan ini, kita patut mempertanyakan, apa yang menjadi faktor pemicu kekerasan dan pelecehan seksual di lokasi bencana?
Sebagian analisa mengaitkan dengan sifat bencana dan pola penanganan yang dilakukan pemerintah dan juga pihak berwenang lainnya. Bencana Palu kala itu memang meluluhlantakkan desa dan bangunan tempat tinggal warga sehingga praktis korban bencana sudah tidak memiliki tempat tinggal. Sebagai konsekuensinya, mereka harus tinggal dan menetap bersama dengan keluarga lain yang mungkin baru dikenalnya di lokasi pengungsian.
Yang lebih merepotkan lagi adalah ketika harus lama tinggal di lokasi pengungsian dalam waktu yang lama. Faktor ini kemudian menjadi pemicu timbulnya disorientasi seksual. Kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu cukup lama memunculkan orang-orang yang nekad menyalurkannya dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat.
Meskipun hal ini juga tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa pelaku yang diketahui masih pemuda dan belum menikah. Dalam konteks ini, berarti faktor pemicu bukan disebabkan karena tidak tersalurkannya kebutuhan biologis, melainkan karena faktor ikhtilath (percampuran) yang tak dapat dihindari dan menjadi sumber utama. Misalnya, di saat posisi seseorang sedang tidur di kamp pengungsian, ia tidak sadar bila auratnya terbuka sehingga dilihat oleh para pelaku kejahatan. Akibatnya, timbul disorientasi seksual tadi.
Ada beberapa sikap yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah atau pihak penyandang dana bantuan korban bencana guna mengantisipasi kemungkinan maraknya kasus disorientasi seksual. Berikut ini adalah beberapa analisa penulis yang mungkin perlu mendapatkan telaah lagi dari pihak yang berwenang.
Pertama, segera membangun kamp yang dilengkapi dengan sekat untuk setiap pasangan keluarga yang menjadi korban bencana. Tujuan dari membangun sekat ini untuk menghindari timbulnya fitnah, apalagi bila masa berada di kamp itu berlangsung cukup lama. Adapun batasan dari ketakutan timbulnya fitnah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Shalah radliyallahu ‘anhu:
وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا
Artinya, “Bukanlah yang dimaksud sebagai ‘takut fitnah’ itu hanya berdasar prasangka kuat akan terjadinya fitnah, melainkan meskipun percampuran itu jarang terjadi (asal ada kemungkinan timbulnya fitnah, maka di situ berlaku illat khauf al-fitnah).” (I’anatu al-Thalibin, Juz III, halaman 263).
Sudah pasti upaya ini membutuhkan biaya sangat besar dan kelihatannya tidak praktis. Akan tetapi, ruang sekat ini merupakan kebutuhan paling mendasar setelah tercukupinya kebutuhan pokok korban. Dengan mendirikan sekat, kemungkinan besar kebutuhan biologis para korban bencana menjadi terpenuhi.
Sebenarnya kebutuhan pendirian sekat atau kamp berbasis keluarga ini dapat diminimalisir dengan menyediakan ruang privasi khusus korban bencana. Misalnya, menyediakan bilik bercinta. Meski hal ini sedikit tabu, tetapi diduga kuat juga mampu meredam gejolak keinginan mereka setelah mendapatkan penyalurannya secara sah menurut syariat. Mungkin ada yang memprotes, jika disediakan bilik bercinta, bukankah hal itu juga ada kemungkinan terdengarnya suara-suara yang mengundang hasrat pengungsi yang lain? Dalam menjawab ini, ada sebuah wajah dalil pendapat mu’tamad dari Imam Nawawi rahimahullah, yaitu:
وما ذكره من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا
Artinya, “Keterangan yang menyebutkan bahwa illat keharaman adalah disebabkan karena ‘timbulnya syahwat’ sebagaimana ini pendapat dari Imam al-Rafii, namun menurut qaul mu’tamad dari Imam al-Nawawi, illat keharaman itu disebabkan karena haramnya memandang secara mutlak, baik disertai kehadiran syahwat, adanya takut fitnah, atau tidak.” (I’anatu al-Thalibin, Juz III, halaman 263).
Berdasar hal ini, unsur keharaman minimal adalah “memandang” percintaan insan lain dengan pandangan “mata,” bukan akibat mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat dan semacamnya. Lain halnya dengan Imam al-Rafii, yang mendengar suara mengundang birahi saja hukumnya sudah langsung diputus haram. Jadi, nilai kemaslahatan yang lebih besar dalam hemat penulis, dalam konteks bencana semacam ini, pendapat Imam Nawawi layak dijadikan pedoman.
Tentu dalam konteks ini, peran pemerintah sangat diperlukan, karena harus mengatur atau menjadwal setiap pasangan. Dan ini adalah risiko bila disediakan bilik bercinta bagi pasangan di lokasi bencana.
Kedua, memisahkan antara pengungsi laki-laki dan perempuan. Kondisi ini memungkinkan terjadi, manakala bencana membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya. Pemisahan antara pengungsi laki dan perempuan, meskipun sudah beristri paling tidak juga disinyalir mampu meredam gejolak hasrat seksualnya. Karena disorientasi seksual itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
Artinya, “Yang dimaksud dengan fitnah adalah zina dan hal yang bisa mengantarkan pada zina, termasuk di antaranya adalah melihat, berduaan, menyentuh dan lain-lain.”
Untuk itu, salah satu cara menjauhkan disorientasi seksual dilakukan dengan pemisahan ruangan.
Ketiga, memastikan agar tempat-tempat yang rawan terjadi kekerasan dan pelecehan seksual senantiasa mendapatkan pengawasan petugas, seperti lokasi kamar mandi, kakus, tempat mencuci, dan sarana umum lainnya.
Keempat, menyediakan ruang informasi dan pengaduan bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual, dengan jaminan kerahasiaan dan keamanannya tetap terjaga. Petugas yang berwenang hendaknya segera merespon laporan atau aduan korban guna mencegah terjadinya hal-hal lain di luar perhitungan, seperti ancaman dan sejenisnya.
Keempat langkah ini merupakan upaya preventif semata (saddu al-dzari’ah) agar tidak bermunculan korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual berikutnya saat bencana melanda, khususnya di lokasi kamp pengungsian. Bagaimanapun juga, hal ini menuntut pihak yang memikirkan, seiiring intensitas, dan daya rusak bencana yang tidak bisa diprediksi, serta kasus pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan waktu yang lama. Sudah barang tentu, keempat hal di atas juga tidak berlaku untuk kasus bencana seperti yang terjadi pada kasus banjir Jakarta awal Januari 2020 yang lalu. Mengapa? Karena dalam kondisi banjir, tidak terjadi kerusakan yang berimbas fatal dan massal, seperti hilangnya rumah secara massal, dan sejenisnya.
Walhasil, kaidah yang diikuti dalam pencegahan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kamp pengungsian ini mengikuti penerapan kaidah:
إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما
Artinya, “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”
Menyediakan sekat, bilik bercinta, atau tenda kemah berbasis keluarga, sudah pasti ada mafsadatnya, karena dana menjadi tersalurkan tidak pada kebutuhan pokok. Akan tetapi, karena penjagaan nasab dan kehormatan merupakan hal penting dalam syariat, maka bisa jadi mafsadat penyediaan bilik bercinta ini merupakan mafsadat paling ringan dibanding ketaktersediannya. Wallahu a’lam bish shawab
Muhammad Syamsudin, Peneliti Aswaja NU Center PWNU Jatim
Terpopuler
1
Membatalkan Puasa Syawal karena Disuguhi Hidangan saat Bertamu, Bagaimana Hukumnya?
2
Festival Ketupat Lebaran Idul Fitri, Warga Kediri dan Pengguna Jalan Dapat Nikmati Makan Gratis
3
Sungkeman saat Lebaran Idul Fitri, Bagaimana Hukumnya?
4
Doa Arus Balik Lebaran, Dibaca Sepanjang Perjalanan
5
Tellasan Topak, Tradisi Perayaan Lebaran Ketupat di Madura pada 8 Syawal
6
Hadapi Qatar di Piala Asia U-23 2024, Begini Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia
Terkini
Lihat Semua