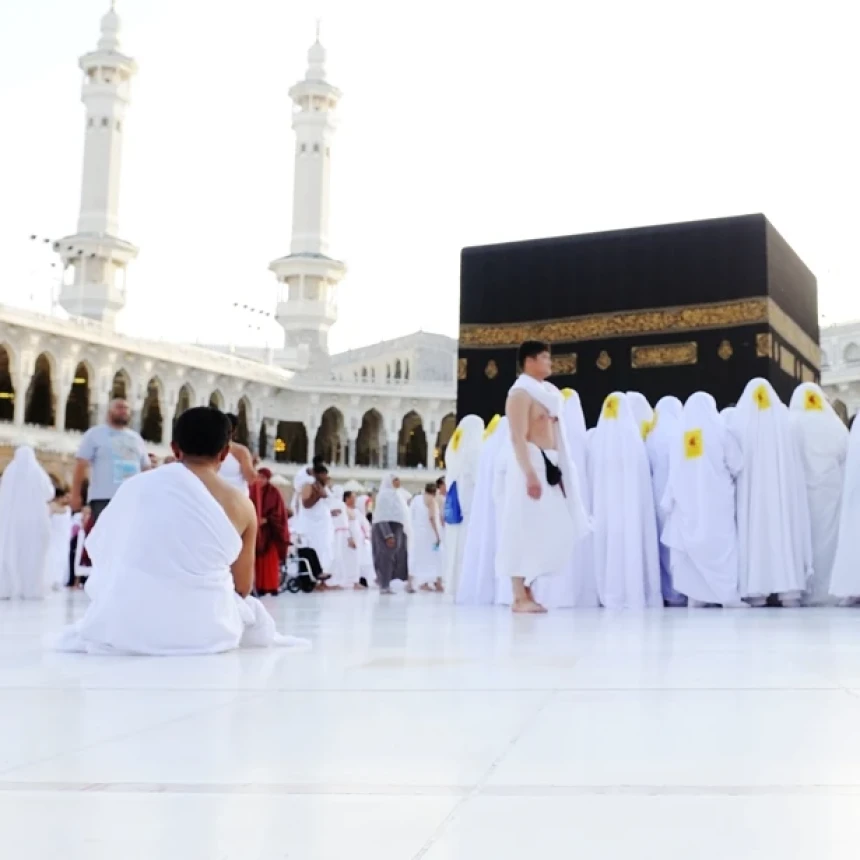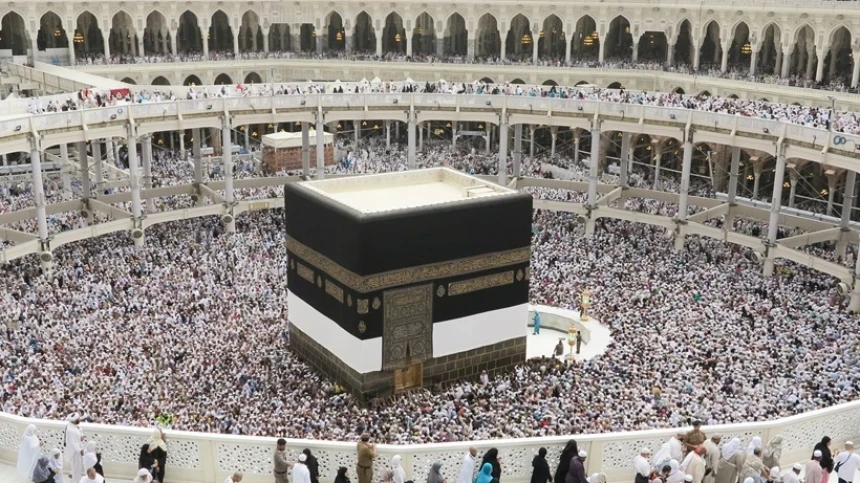Sebesar apa pun menggebunya semangat beragama, semua yang dilakukan mesti dilakukan dengan bekal ilmu yang cukup.
Ahmad Mundzir
Kolomnis
Di antara gejala yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah kian meningkatnya semangat beragama sebagian orang. Gairah ini bisa bermula dari perasaan bersalah karena menyia-nyiakan umur sekian tahun dengan shalat tidak rajin dan tak cakap baca Al-Qur’an, lalu tekad menggebu untuk melakukan perubahan dalam diri. Bahkan seringkali semangat itu mengejawantah dalam wujud yang lebih luas: tekad bulat untuk membaktikan diri kepada agama Islam sebagai upaya untuk menambal kekurangan tersebut. Berikutnya, sebagian berikrar, “Saya Wakafkan Diri saya untuk Islam”.
Hati manusia bisa selalu berubah. Dalam bahasa Arab, hati diistilahkan dengan nama qalb. Qalb artinya berbalik. Maksudnya, hati adalah sesuatu yang sangat berpotensi untuk bolak-balik, berubah-ubah. Pada masa periode tobat, mungkin semangatnya sedang menggebu-gebu. Namun belum pasti dua tahun kemudian, kondisi serupa itu masih dijumpai. Bagaimana jika dua tahun kemudian, orang yang pernah ikrar mewakafkan dirinya tersebut tiba-tiba menjadi kendor, misalnya, karena kebutuhan keluarga yang mendesak atau satu dua hal lain, sehingga ia tidak bisa total dalam berbakti kepada agama. Apakah orang yang “mewakafkan diri” itu mendapatkan dosa dengan sebab membagi waktu untuk kebutuhan pribadi dengan melayani agama?
Sebelumnya, perlu kita ketahui bagaimana definisi wakaf menurut ulama fiqih:
الوقف وهو لغةً الحبس، وشرعًا حبسُ مالٍ مُعَيَّن قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى.
Artinya: “Wakaf secara bahasa adalah menahan. Sedangkan wakaf secara istilah adalah menahan harta spesifik yang bisa dipindahtangankan dan bisa dimanfaatkan, bendanya bersifat abadi, arah pendayagunaannya khusus hal-hal baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, Fathul Qarib al-Mujib, [Daru Ibn Hazm, Beirut, 2005], hal. 204)
Para ulama fiqih bisa jadi memberikan definisi berbeda tapi secara substansi tetaplah sama. Masalah definisi menjadi penting karena akan mempengaruhi pengaturan syarat-syarat wakaf pada pembahasan lebih lanjut. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain menyatakan bahwa syarat wakaf ada empat pilar, yakni waqif (pemberi wakaf), mauquf (benda yang diwakafkan), shighat (transaksi), dan mauquf ‘alaih (penerima wakaf).
Sebagaimana syarat kedua di atas yaitu harus ada benda yang diwakafkan, maka benda yang diwakafkan harus berupa benda fisik, tidak sekadar manfaatnya tanpa wujud benda. Misalnya, orang mewakafkan akses wifi di salah satu tempat, maka hukumnya tidak sah karena hanya unsur manfaatnya saja yang diwakafkan, bukan bendanya. Berbeda jika yang diwakafkan alat pemancar wifi-nya, maka sah sebab hal itu masuk kategori benda fisik yang konkret.
Selain yang diwakafkan harus berupa benda konkret, benda tersebut harus bisa dimiliki, walaupun tidak milik pribadi pemberi wakaf. Contoh, ada pemerintah mempunyai kas negara, berdasarkan atas pertimbangan maslahat, pemerintah mendirikan masjid dari tanah wakaf yang dibeli dari harta kas negara. Wakaf seperti ini hukumnya sah sebab tanah dan bangunan merupakan harta yang riil fisiknya dan seumpama diwakafkan kepada perorangan bisa dipindahtangankan walaupun yang mengikrarkan wakaf tidak memiliki secara pribadi. Pemerintah hanya sebagai pengatur kebijakan saja.
Bagaimana dengan orang yang mewakafkan dirinya sendiri? Orang merdeka (tidak budak) merupakan manusia yang mempunyai kebebasan sebebas-bebasnya. Ia tidak dimiliki dan tidak akan bisa dimiliki oleh siapa pun. Berbeda dengan budak. Budak merupakan manusia, tapi secara fisik, ia menjadi milik orang lain, dia bisa diwakafkan. Di dunia modern ini, perbudakan nyaris sudah tak ada lagi.
Manusia merdeka tidak bisa dimiliki oleh siapa pun, maka orang mewakafkan orang merdeka baik seseorang mewakafkan dirinya sendiri baik untuk agama maupun untuk apa pun, hukum wakafnya tidak sah. Efek dari ketidakabsahan itu, orang yang terlanjur berikrar mewakafkan dirinya atau bahkan anaknya dan anggota keluarga yang lain, tidak ada konskuensi hukumnya karena ikrar wakafnya tidak mendapat legalitas syara’.
فَلَا يَصح وقف حر نَفسه لِأَن ذَاته غير مَمْلُوكَة لَهُ
Artinya: “Maka tidak sah wakafnya orang merdeka dengan mewakafkan dirinya sendiri. Karena pribadinya tidak bisa dimiliki oleh siapa pun” (Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani, Nihayatuz Zain, [Darul Fikr, Beirut, tt], hlm. 268).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang mewakafkan dirinya sendiri, hukum pewakafannya tidak sah yang berarti ikrar wakafnya tidak memberikan konskuensi hukum syara’. Apalagi bila ungkapan “mewakafkan diri” itu sejak awal memang dimaksudkan untuk kiasan atas komitmen yang bulat dan utuh untuk berjuang atau mengabdikan diri. Sebagai catatan, sebesar apa pun menggebunya semangat beragama, semua yang dilakukan mesti dilakukan dengan bekal ilmu yang cukup. Sehingga, beragama menjadi tetap terarah dan tidak terjebak pada dorongan nafsu pribadi. Wallahu a’lam.
Ustadz Ahmad Mundzir, Pengajar di Pesantren Radhatul Qur’an an-Nasimiyyah, Semarang
Terpopuler
1
Membatalkan Puasa Syawal karena Disuguhi Hidangan saat Bertamu, Bagaimana Hukumnya?
2
Khutbah Jumat: Meraih Pahala Berlimpah dengan Puasa Syawal
3
Hukum Mengulang Akad Nikah karena Grogi
4
Tellasan Topak, Tradisi Perayaan Lebaran Ketupat di Madura pada 8 Syawal
5
Sejarah Awal Berdirinya Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
6
Indonesia Kalah 2-0 dari Qatar, Suporter Timnas Sebut Wasit Berlebihan Dukung Tuan Rumah
Terkini
Lihat Semua