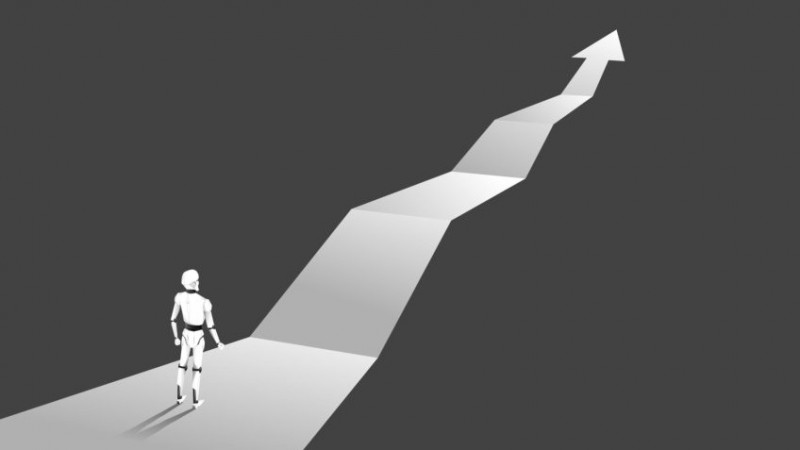
Di manakah kita sebelum sekarang? Ke mana pula kita setelah dari sini? Arah mana yang hendak kautuju? Apa sejatinya tujuan hidupmu?
Ren Muhammad
Kolomnis
Petaka global terjadi silih berganti saat penduduk di planet biru ini masih direjam pandemi Korona—yang terus bermutasi. Malah sejak Mei 2021, India kembali dihajar wabah jamur hitam yang tak kalah mematikan. Dua bulan berselang, Jerman, Italia, Belgia, Russia, dan China, tiba-tiba dihantam banjir bandang yang menelan ribuan korban jiwa. Tak hanya itu, Negeri Tirai Bambu tersebut juga dilamun topan In-Fa, yang merusak begitu banyak fasilitas publik. Alhasil, kita seperti melihat purwarupa kiamat yang mungkin telah pula menimpa generasi manusia sebelumnya.
Soal yang kita hadapi, sejatinya tak melulu bencana berskala besar. Ancaman populasi manusia, justru dimulai dari ras Homo Sapien yang pernah mengubur saudara Neanderthal-nya dalam sejarah peradaban. Tengoklah samudera kita yang kian tercemar oleh limbah mikroplastik. Biota laut yang punah karenanya, secara tidak langsung turut memengaruhi rantai ekosistem makhluk hidup. Udara yang kita hirup, tanah yang menghidupi kita, juga tak jauh berbeda. Setahun belakangan ini, manakala umat manusia tak henti dihantui wabah, segelintir orang-orang kaya malah terbang menjelajah antariksa.
Ada di antara mereka yang ingin membuat koloni di Mars. Ada pula yang ingin menjajal Venus sebagai rumah baru. Tapi bukan itu yang penting. Tanpa mereka sadari, eksplorasi ruang angkasa yang telah dimulai sejak era 1960-an ini, menyisakan sampah di lapisan ozon bumi—yang kemudian terjun bebas ke laut lepas di bawahnya. Pertanyaan kita, sebenarnya apa yang hendak mereka cari di atas sana? Apa yang ingin mereka tunjukkan pada kita? Prilaku apakah namanya yang seperti itu?
Jika memang mereka jengah dengan kehidupan di bumi, yang padahal mereka juga yang merusak, kenapa tidak turut andil memperbaiki kerusakan itu dengan harta kekayaan mereka yang berlimpah ruah? Mari kita renungkan. Sementara sebagian besar penduduk bumi menjerit lantaran dijepit pandemi, mereka malah menghabiskan dana sedemikian besar demi memuaskan ambisi pribadi. Wajar bila kemudian apa yang mereka lakukan mendapat begitu banyak penentangan dari orang lain, yang terganggu rasa kemanusiaannya. Pun mungkin begitu dengan kita.
Rangkaian peristiwa penting yang kami paparkan di atas, kemudian menerbitkan pertanyaan primordial yang telah lama terpendam dalam sanubari seluruh umat manusia.
Adakah di antara kita yang ingin dilahirkan ke dunia? Lantas kenapa kita mengada di sini? Apa yang hendak kita cari? Apa yang sungguh benar kita butuhkan? Di manakah kita sebelum sekarang? Ke mana pula kita setelah dari sini? Arah mana yang hendak kautuju? Apa sejatinya tujuan hidupmu?
Mari sejenak merenung.
Semua yang kaualami-jalani hari ini, jadi benih kejadian pada masa depan. Segala yang terjadi pada masa lalu, kita ulangi juga pada saat ini. Ada yang terlahir sebagai anak, tapi sebenarnya buyut yang terlahir kembali. Terkadang tak hanya sama persis secara karakter, malah sampai pada tingkat perwajahan. Sampai di sini, Islam sejatinya punya konsep reinkarnasi sebagaimana diyakini Hindu-Buddha. Sayangnya, belum sama sekali digali dengan baik.
Delapan abad silam, Rumi (1207-1273) menggubah puisi yang ia beri judul Akan jadi apa Diriku?:
Aku terus dan terus tumbuh seperti rumput;
Aku telah alami tujuh ratus dan tujuh puluh bentuk.
Aku mati dari mineral dan menjadi sayur-sayuran;
Dan dari sayuran Aku mati dan menjadi binatang.
Aku mati dari kebinatangan menjadi manusia.
Maka mengapa takut hilang melalui kematian?
Kelak aku akan mati
Membawa sayap dan bulu seperti malaikat:
Kemudian melambung lebih tinggi dari malaikat —
Apa yang tidak dapat kau bayangkan.
Aku akan menjadi itu.
Barangkali, puisi tersebut lahir dari pembacaan mendalam Rumi berdasar ayat Al-Qur’an yang berbunyi, “Jadilah kamu sekalian batu atau besi.” (QS Al Isra’ [17]: 50). Bila kita menggunakan logika berpikir pun, mudah sekali memahami prihal ini. Ketika wafat dan tubuh kita dikebumikan, para makhluk renik akan segera bekerja mengurainya. Maka tubuh kita yang sudah berubah bangkai itu pun, pelan tapi pasti, kembali ke anasir pembentuknya. Tanah, air, api, udara. Manusia yang lahir kemudian, kelak memakai empat anasir itu sebagai bagan baku tubuh mereka—sebagaimana yang kini juga kita alami.
Letak perbedaannya adalah, masing-masing kita membawa kodrat universal sebagai ciptaan, berikut segala manfaat ketika awal mengada. Kita punya “jalan ninja” sendiri yang tak pernah bisa dimengerti liyan. Pun sebaliknya. Begini cara menalarnya: tak semua santri jadi kiai, tak semua murid jadi guru, tak semua mahasiswa jadi dosen. Merujuk pada Al-Qur’an, maka kita akan menemukan keterangan yang berbunyi, “Wa mâ khalaqtul jinna wa l-insa illâ liya’budûn: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS Az-Zariyat [51]: 56).
Ada segelintir pendakwah Islam yang cenderung menerjemahkan kata liya’budun dalam ayat tersebut dengan beribadah. Tidak salah memang. Tapi jika kita menggunakan kaidah fiqih, ibadah pasti berkonotasi dengan shalat, zakat, puasa, haji. Namun bila akar katanya yang kita selami, yaitu ‘abd (hamba sahaya), maka yang muncul adalah penghambaan-pengabdian. Ya, kita semua adalah hamba bagi tuhan. Budak yang Dia cintai lagi sayangi. Selaiknya hamba, kita tak punya pilihan lain kecuali manut kersane Gusti Pangeran, dengan terus mengasah diri agar menyadari bahwa apa yang kita alami-lakukan, adalah bagian dari ketentuan-Nya yang misterius.
Kita memang menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi—dengan segala yantra yang kita miliki. Tapi secara peran dan fungsi, manusia bukan yang utama di jagat raya ini. Silakan Anda mengagulkan diri sebagai “puncak” penciptaan Tuhan, namun tanpa air yang turun dari langit, dan tanur yang memancar dari perut bumi, Anda hanya seonggok daging yang kepayahan. Triliunan makhluk yang berdiam dalam tubuh kita sekarang, turut membantu kita menjalani laku lampah kehidupan yang dibabar oleh semesta.
Jangan terlampau jauh melanglang buana ke luar diri. Pulanglah ke haribaan diri yang sejati. Kita punya kemampuan hidup bebas tanpa tekanan, dengan rasa damai tertinggi dalam pikiran-perasaan. Setiap tindakan yang kaulakukan, jadi bagian tak terpisah dari semarak kehidupan. Segala peristiwa dalam hidupmu, terjadi demikian adanya. Karena kaumampu menghadapinya dengan ketahanan alamimu. Hal itu karena kita tidak sendirian di sini.
Semesta adalah kesatuan yang diatur kecerdasan adiluhung, dan jiwa kita adalah bagian dari kecenderungan itu. Semua mahluk istimewa lantaran tercipta dari keagungan-Nya. Tetesan Rahmat-Nya mengucur tak hingga. Cahaya jagat mayapada, adalah Cahaya-Nya. Indah yang dipandang mata, tak lain Keindahan-Nya semata. Alam raya menubuh jadi kita—yang disusun oleh tujuh oktilion atom (7x10^27 [diikuti dua puluh tujuh nol]). Tanah, air, api, udara, membentuk kita sesuai anasirnya. Keempat unsur itu disatukan udara. Karena itulah kita jadi sa-udara. Dipersaudarakan langit-bumi, dalam ikatan yang sama: Hidup. Abadi bersama Sang Maha Hidup dan Hidup dalam Keabadian.
Sang Hyang Moho Suci lebih dekat daripada urat leher kita (QS Qaf [50]: 16), dan kita tak pernah berpisah dengan-Nya, dalam segala kejadian. Kita bersatu tapi tak menyatu-padu. Seolah jauh namun berdekatan. Kita manunggal bersama dan berada di dalam Diri-Nya. Menjadi wajar bila kemudian satu demi satu kita pergi, tapi yang terjadi adalah, kita selalu menjadi dan terus mengada. Dalam semesta yang diliputi-Nya.
Para fisikawan mengatakan bahwa graviton (interaksi gravitasi), gluon (interaksi kuat), foton (interaksi elektromagnetik), Z dan W (interaksi lemah), dan Partikel Tuhan (Higgs Boson), melambari kehidupan kita yang misteri. Tak terpecahkan sampai kapan pun. Tak terpahami oleh siapa pun. Kita hanya subatom dari karya besar Sang Hyang Murba Wisesa. Tanpa kita, semesta tetap ada. Tanpa semesta, kita tetap ada.
Itulah paradoks purba keadaan kita. Itu pula kenyataan kita yang bertolak belakang. Tak ada yang sungguh benar kita. Tak ada yang sungguh benar tiada. Lantaran tiada itu pun ada, dalam semua dimensi yang berkelindan bersama diri-Nya. Mengejawantah dalam kemungkinan tak berbatas yang niscaya. Sedemikian pula renjana yang tercipta bagi kita, selaku manusia. Segala ketakhinggaan itu, melampaui seluruh konsep yang entah bagaimana, kadung mengurung diri kita dalam ruang-waktu.
Ren Muhammad, pendiri Khatulistiwamuda yang bergerak pendidikan, sosial budaya, dan spiritualitas; Ketua Bidang Program Yayasan Aku dan Sukarno, serta Direktur Eksekutif di Candra Malik Institute
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Meraih Keutamaan Bulan Muharram
2
Koordinator Aksi Demo ODOL Diringkus ke Polda Metro Jaya
3
5 Fadilah Puasa Sunnah Muharram, Khusus Asyura Jadi Pelebur Dosa
4
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
5
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
6
5 Doa Pilihan untuk Hari Asyura 10 Muharram, Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
Terkini
Lihat Semua










