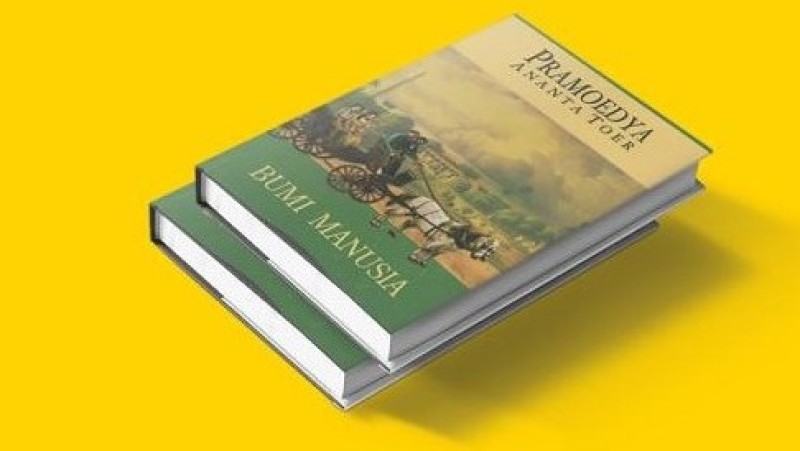Oleh Muhamad Muckhlisin
Dalam novel-novel Pramoedya Ananta Toer, Tetralogi Buru, pembaca seakan dibimbing untuk menelusuri identitas diri yang disebut 'manusia Indonesia'. Meskipun pada prinsipnya, identitas kebangsaan bukanlah suatu produk yang bersifat tetap dan final, akan tetapi ia terus mengalami proses sesuai dengan konteks situasi dan kondisi yang terus-menerus mengalami perubahan.
Ketidaktetapan identitas kebangsaan sejalan dengan teori yang ditawarkan sosiolog Stuart Hall (1994), mengenai individu yang meniru individu lain, hingga lama kelamaan menjelma sebagai individu baru (yang berbeda). Individu baru yang 'terpengaruh' itu dapat dikatakan hampir serupa tapi tak sama. Selain itu, dalam teori antropologi dikenal istilah ruang ketiga (the third space), sebagai ruang alternatif yang sanggup melihat dari perspektif baru yang lain, ketimbang konsep yang ditemukan sebelumnya.
Posisi third space mampu memandang manusia tidak hanya berdasarkan sudut pandang salah satu dari kedua belah pihak, namun sekaligus mampu melampaui keduanya, sehingga di situlah tampak adanya obyektivitas. Dalam teori ilmiah, kita juga mengenal adanya 'sintesis' yang berhasil memadukan, atau bahkan melampaui konsep yang berlandaskan tesis dan antitesis. Jadi, wawasan seseorang sudah melampaui keduanya, atau menciptakan posisi baru di luar keduanya. Boleh saja ia berdiri tegak dan membumi, namun sudah mengatasi indra dan melampaui buana.
Dalam novelnya yang berjudul By the Sea (2002), Abdulrazak Gurnah menyibak permasalahan identitas yang dialami oleh masyarakat Zanzibar, yang digambarkan sebagai masyarakat multikultural bekas koloni Inggris. Secara antropologis, identitas dalam novel itu dibentuk berdasarkan latar belakang agama, bahasa, budaya, bahkan ras dan warna kulit. Permasalahan identitas muncul karena komlepksitas masyarakat yang hidup dalam ruang dan waktu yang sama–namun dengan latar belakang berbeda–saling berselisih paham antarasatu dengan yang lainnya. Bahkan, konflik itu pun senantiasa muncul dari individu-individu dengan latar belakang yang sama, namun dalam perjalanannya mengalami proses pemikiran dan pemahaman yang berbeda.
Sebagai penulis kelahiran Zanzibar yang menulis tentang masyarakat daerahnya, Abdulrazak Gurnah pernah menempuh pendidikan di Inggris dan menetap di negeri itu. Hal ini dikemukakan sendiri oleh Gurnah melalui artikelnya Writing and Place, bahwa suatu karya sastra yang baik tak lepas dari latar peradaban di mana penulisnya pernah tinggal dan tumbuh, hingga mampu meresapi perasaan-perasaan manusia di dalamnya.
Namun demikian, sang penulis–meskipun berpijak di bumi–harus berpikir mengangkasa, hingga sanggup menembus ketinggian langit. Karena itu, seorang penulis kelahiran Banten bisa menulis tentang Banten, namun pikiran dan perasaannya sudah melampaui Banten, bahkan pasca-Indonesia. Dalam hal ini, Bung Karno pernah memberi amanat bahwa, 'Seorang Jawa harus menjadi pasca-Jawa, bahkan seorang Indonesia, tidak cukup dengan menjadi manusia Indonesia, tetapi harus berpikir mendunia."
Tidak sedikit budayawan dan intelektual Barat cenderung menilai sosok Gurnah, melalui narasi-narasi dalam novelnya seakan-akan sastrawan berkulit hitam yang terpengaruh budaya Barat (westernized easterner), atau orang timur yang kebarat-baratan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, selain dapat mengetahui bagaimana problematika identitas melalui permainan posisi narator, juga bisa diketahui bagaimana narator memosisikan dan membangun identitas narasinya.
Bagi saya, Gurnah sangat mahir menampilkan pesan-pesan moral dalam penyampaian narasi melalui tokoh-tokohnya. Sehingga, ia telah sanggup memberi petuah bagi manusia Barat sekaligus manusia Timur, terlebih bagi bangsanya sendiri. Dalam identitas manusia yang terus mengalami perubahan, mereka saling memengaruhi dan saling mengisi satu sama lain, hingga pada gilirannya mampu melakukan sanering dan perbandingan antara satu peradaban dengan peradaban lainnya. Di sisi lain, karya-karya Gurnah memang cakap menampilkan identitas kebangsaan–sebagaimana Pramoedya melalui Bumi Manusia–bahwa hakikat kemanusiaan bukan sesuatu yang menjadi (being), tetapi merupakan proses produksi yang tak pernah berhenti (becoming).
Sudut pandang narator memang tidak menempatkan posisinya secara vulgar antara hitam dan putih, buruk dan baik, tetapi dengan begitu justru penulis dengan bebas berpindah-pindah bahkan menerabas batas-batas antara keduanya. Dengan perspektif ini, dimungkinkan adanya proses penafsiran antar-kelompok dengan latar belakang berbeda, sehingga narasi bisa memiliki pandangan lebih luas, tidak terbatas pada sekat-sekat kepentingan kelompok tertentu.
Sebagaimana novel Anak Semua Bangsa (Pramoedya) tergambar suatu nasion yang multikultural, tak lepas dari keberadaan masyarakat yang mengalami permasalahan identitas. Konteks sejarah juga disampaikan melalui gaya penuturan yang kompleks. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian ilmiah seperti halnya Pikiran Orang Indonesia (2014), di mana penulisnya mengadakan riset historical memories selama bertahun-tahun demi untuk mengejawantahkan hasil risetnya mengenai korban-korban politik 1965.
Penelitian sejarah dibutuhkan untuk menunjukan keterkaitan strategi naratif yang digunakan dengan pembentukan identitas karakter dalam proses penulisan karya sastra. Selain itu, juga kemampuan mendeskripsikan fitur-fitur tekstual dan gaya penceritaan dalam membangun usaha teks agar menjadi obyektif terkait dengan siapa yang berbicara, siapa yang dibicarakan, dan bagaimana gaya penceritaannya.
Persentuhan budaya dan peradaban dalam masyarakat multikultural di Zanzibar menimbulkan adanya saling memengaruhi satu sama lain karena adanya proses transaksi antar berbagai pihak. Hingga kemudian, bukan hanya memuculkan 'orang timur yang kebarat-baratan' (westernized easterner), tetapi juga melahirkan 'orang barat yang ketimur-timuran' (easternized westerner).
Pengelompokan semacam itu akan memudahkan pembaca–sebagaimana novel Perasaan Orang Banten (2012)–hingga mampu menganalisis pola naratif antara posisi sang narator dalam perbandingannya dengan psosisi karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Melalui sikap dan cara pandang terhadap isu-isu di sekitarnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemaparan narasi dalam karya-karya Gurnah, tak beda jauh dengan Perasaan Orang Banten, yakni karakteristik orang-orang Banten (timur) yang terpengaruh budaya Barat (Amerika) hingga dapat digolongkan ke dalam kelompok westernized easterner.
Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat agamis, tampak jelas pada karya Gurnah berjudul Desertion (2005), yang menggambarkan orang-orang Zanzibar telah kehilangan ketimurannya. Dalam karya tersebut tampak jelas hukum-hukum agama (Islam) ditampilkan, namun bukan berupa doktrin yang membelenggu ruang-gerak, melainkan pengajuan hal-hal rasional bahwa sesuatu yang dilarang atau dibolehkan, harus disertai penjelasan yang masuk akal. Misalnya, efek minuman keras dan mabuk-mabukan. Di sini, pihak lain (liyan) bisa memandang bagaimana Islam melarang mabuk-mabukan, dan perlu meninggalkannya secara bertahap. Persinggungan peradaban semacam ini adalah tawaran tersendiri tentang ukuran manusia 'beradab' di antara peradaban lainnya.
Abdulrazak Gurnah sangat fasih menampilkan berbagai bangsa yang memiliki penilaian berbeda tentang konsep 'keberadaban'. Apa ukuran seorang manusia disebut beradab dan tidak beradab, sehingga pembaca disodorkan pada suatu pertanyaan universal: adakah definisi yang mutlak tentang ukuran manusia beradab pada satu bangsa dibanding bangsa lainnya?
Penulis adalah cerpenis dan peneliti sastra mutakhir Indonesia, pernah memenangkan Lomba Cerpen Cagar Budaya Nasional (2016), juga pemenang pertama Lomba Cerpen Nasional yang diselenggarakan Rakyat Sumbar (2017).
Terpopuler
1
Daftar Tanggal Merah Bulan Mei 2024; Ada 2 Libur Panjang
2
Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024: Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin Ditolak MK
3
Ketika Cuaca Buruk Bolehkah Mengumandangkan Adzan Shallu fi Rihalikum atau fi Buyutikum?
4
Mandi Malam Sebabkan Rematik, Mitos atau Fakta?
5
Ini Profil Delapan Hakim MK yang Putuskan Sengketa Pilpres 2024
6
Flu dan Batuk Tak Kunjung Sembuh, Ketahui Penyebab dan Cara Mengobatinya
Terkini
Lihat Semua