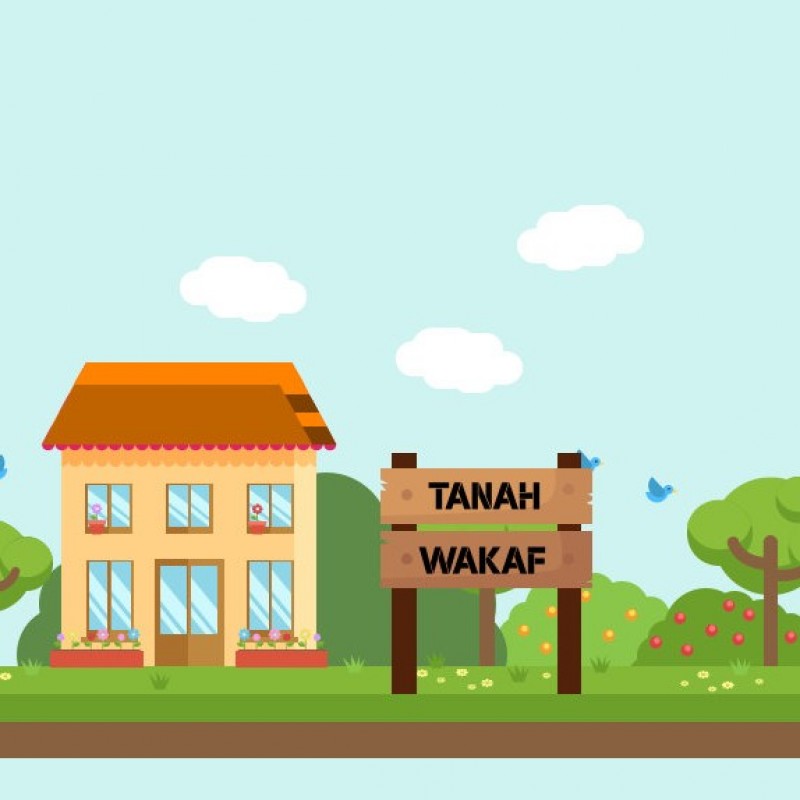Banyak yang masih bingung mengenai perbedaan masjid dan mushala. Ada yang memahami masjid adalah tempat jamaah shalat yang dibuat shalat Jumat, sementara mushala adalah tempat jamaah shalat lima waktu biasa yang tidak dipakai shalat Jumat. Kejanggalan juga terjadi dalam persoalan mushala wakafan. Ada yang memahami statusnya adalah masjid karena melihat
wakafnya, sebagian yang lain menganggap itu bukan masjid. Bagaimana penjelasannya secara fiqih?
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mushala (KBBI menggunakan kata “musala”) didefinisikan dengan tempat shalat, langgar atau surau. Sementara masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.
Secara istilah syariat, masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat dengan niat menjadikannya masjid. Sementara mushala adalah tempat shalat secara mutlak, baik berupa wakafan, milik pribadi, hibah, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa masjid sudah pasti wakaf, sedangkan mushala belum tentu wakaf.
Dari definisi tersebut juga bisa dipahami bahwa penggunaan tempat untuk jamaah shalat Jumat bukan menjadi prinsip dalam menentukan status masjid, tapi ditentukan oleh sighat (ucapan) pewakaf. Bila ada tanah yang diwakafkan sebagai masjid, maka statusnya adalah masjid, meski tidak pernah dipakai shalat Jumat.
Dari definisi di atas, para fuqaha Syafi’iyah menjelaskan bahwa tidak semua tempat yang diwakafkan untuk shalat berstatus masjid. Namun harus dilihat dari shighat/ucapan pewakafannya.
Shighat pewakafan masjid terbagi menjadi dua. Pertama, sharih (yang jelas), yaitu setiap ucapan yang secara tegas mengarah kepada wakaf masjid, tidak bisa diarahkan kepada makna lain. Kedua, kinayah, yaitu ucapan yang memungkinkan untuk diarahkan kepada pewakafan masjid dan makna lain. Agar menjadi masjid, shighat sharih tidak membutuhkan niat, sedangkan shighat kinayah butuh niat.
Contoh ungkapan sharih dalam pewakafan masjid adalah “Aku jadikan tanah ini menjadi masjid”, “Aku wakafkan tanah ini menjadi masjid”, dan lain sebagainya. Hanya dengan ucapan pewakaf sejenis itu, status tanah sudah sah menjadi masjid, tanpa harus disertai niat menjadikannya sebagai masjid.
Contoh shighat kinayah adalah “Aku wakafkan tempat ini untuk shalat”. Dalam ucapan ini, secara tegas mengarah kepada arti wakaf tempat shalat, namun secara lebih spesifik mengarah kepada arti wakaf masjid masih sebatas isyarat (belum tegas), ucapan tersebut memiliki dua kemungkinan makna, yaitu wakaf mushala biasa dan wakaf masjid. Sehingga untuk berstatus sebagai masjid, harus diniatkan menjadi masjid. Jika tidak diniati menjadi masjid, maka hanya bersatus wakaf untuk shalat, bukan masjid.
Status sebuah tanah menjadi masjid memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan wakaf mushala biasa, seperti haramnya berdiam diri bagi orang junub, sahnya i’tikaf, bertambahnya pahala shalat dan lain-lain. Dengan demikian, mushala wakaf tidak sah untuk menjadi tempat i’tikaf, tidak haram bagi orang junub berdiam diri di dalamnya dan lain sebagainya. Berbeda dengan wakaf masjid yang berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya seperti sahnya i’tikaf, haramnya berdiam diri bagi wanita haidl dan lain sebagainya.
Baca juga:
Penjelasan di atas merujuk kepada referensi dari kitab Umdah al-Mufti wa al-Mustafti sebagai berikut:
مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمَنَاوِي فِي التَّيْسِيْرِ قَوْلُهُ وَقَفْتُ هَذَا لِلصَّلَاةِ صَرِيْحٌ فِي وَقْفِهِ لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ فِي خُصُوْصِ وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْمَسْجِدَ صَارَ مَسْجِدًا وَإِلَّا فَلَا كَالْمَدْرَسَةِ. وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَأَمْرٌ زَائِدٌ يَكْثُرُ فِيْهِ الْأَجْرُ وَيُعْتَكَفُ فِيْهِ وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ الْمُكْثُ فِيْهِ وَلَهُ أَحْكَامٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا وُقِفَ لِلصَّلَاةِ كَمُصَلَّى الْعِيْدِ فَإِنَّهُ وَقْفٌ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِيْرُ وَقْفًا بِالْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ فِيْهِ.
“Sebuah permasalahan. Al-Manawi berkata dalam kitab al-Taisir, ucapan seseorang aku mewakafkan tempat ini untuk shalat tegas mengarah kepada makna mewakafkan untuk shalat, kinayah untuk kekhususan wakaf masjidnya, bila ia meniatkannya sebagai masjid, maka berstatus masjid, bila tidak ada niat, maka tidak menjadi masjid seperti wakaf madrasah. Adapun masjid adalah perkara yang memiliki nilai lebih yang banyak pahala di dalamnya, sah dibuat I’tikaf, dan haram bagi yang berhadats besar berdiam diri di dalamnya. Masjid memiliki hukum-hukum yang melebihi tempat yang diwakafkan untuk shalat, seperti mushala shalat ‘Ied, sesungguhnya mushala tersebut diwakafkan untuk shalat namun tidak memiliki kehormatan seperti masjid. Dan tidak menjadi wakaf dengan memberi izin shalat di dalamnya” (Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal, ‘Umdah al-Mufti wa al-Mustafti, juz 2, hal. 258).
Uraian di atas pernah disinggung oleh para kiai dalam forum Muktamar Nahdlatul Ulama ke-10 di Surakarta pada tanggal 10 Muharram 1354 H/April 1935 M. Berikut ini bunyi keputusannya:
Soal: Bagaimana hukumnya tempat yang diwakafkan untuk sembahyang, apakah tempat itu menjadi masjid sebagaimana keterangan dalam kitab Safinah?
Jawaban: Bahwa tempat itu tidak menjadi masjid apabila tidak diniatkan menjadi masjid.
Para masyayikh dalam forum tersebut merujuk pada beberapa referensi sebagai berikut:
1. Mughni al-Muhtaj
وَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ إِلاَّ بِلَفْظٍ مِنْ نَاطِقٍ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ إِلَى أَنْ قَالَ تَنْبِيْهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ مَا إِذَا بَنَى مَسْجِدًا فِيْ مَوَاتٍ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِيْرُ مَسْجِدًا وَلَمْ يَحْتَجَّ إِلَى لَفْظٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْماَوَرْدِي لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النِّيَّةِ مُغْنِيَانِ عَنِ الْقَوْلِ. وَوَجَّهَهُ السُّبُكِيّ بِأَنَّ الْمَوَاتِ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا احْتِيْجَ لِلَفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ اْلإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ إِجْرَاؤُهُ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنَ الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَغَيْرِهَمَا وَكَلاَمُ الرَّافِعِي فِيْ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ.
“Wakaf itu tidak sah kecuali disertai ucapan (dari yang mewakafkan) yang memberikan pengertian (pewakafan) yang dimaksud ... dikecualikan dari syarat mengucapan, bila seseorang membangun masjid di lahan bebas, dan ia berniat menjadikannya masjid, maka bangunan tersebut menjadi masjid tanpa memerlukan ucapan pewakafan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Rif’ah dalam kitab al-Kifayah dengan mengikuti al-Mawardi: “Sebab aktifitas membangun disertai niat menjadikannya masjid sudah mencukupi pewakafan dari pengucapan wakaf. Al-Subki memperkuatnya, bahwa lahan bebas tersebut tidak menjadi milik seseorang yang membukanya sebagai masjid. Diperlukannya pengucapan wakaf itu untuk mengeluarkan lahan dari kepemilikan seseorang. Dan untuk bangunannya diberlakukan hukum masjid karena mengikuti lahannya. Al-Isnawi berpendapat: “Dan hukum qiyas kasus tersebut adalah pemberlakuannya pada selain masjid, yaitu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dan selainnya. Pendapat al-Rafi’i dalam bab Ihya al-Mawat juga menunjukkan demikian.
2. I’anah al-Thalibin
)قَوْلُهُ وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلاَةِ إِلَخ) أَيْ وَإِذَا قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْتُ هَذَا الْمَكَانَ لِلصَّلاَةِ فَهُوَ صَرِيْحٌ فِيْ مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكِنَايَةٌ فِيْ خُصُوْصِ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا) فَإِنْ نَوَى الْمَسْجِدِيَّةَ صَارَ مَسْجِدًا وَإِلاَّ صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلاَةِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا كَالْمَدْرَسَةِ.
“(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Saya mewakafkannya untuk shalat.”), yakni jika si pewakaf berkata: “Saya wakafkan tempat ini untuk shalat.” Maka ucapan itu termasuk sharih (jelas) dalam kemutlakan wakaf. (Ungkapan beliau: “Dan kinayah dalam kekhususannya sebagai masjid, maka harus ada niat menjadikannya masjid”) Jika ia berniat menjadikan masjid, maka tempat tersebut menjadi masjid. Jika tidak, maka hanya menjadi wakaf untuk shalat saja, dan tidak menjadi masjid seperti sekolahan.”
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.